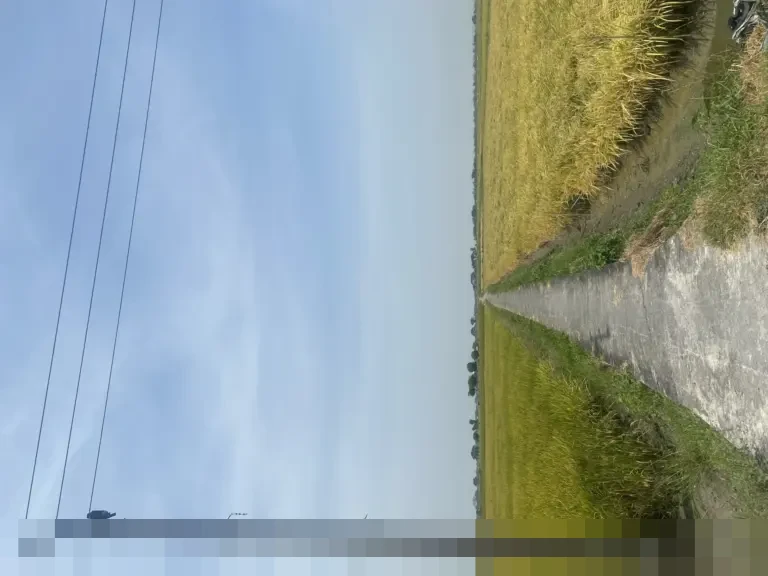Musibah banjir, yang kerap membawa duka dan kehancuran, ternyata dapat menjadi sebuah lorong sunyi yang mengantarkan manusia pada kedekatan dengan Tuhannya. Demikian pandangan Asep Abdurrohman, seorang Dosen Program Pascasarjana, yang melihat bencana bukan sekadar peristiwa hampa makna.
Banjir yang melanda wilayah Sumatra dan Aceh pada Desember 2025 lalu, dalam kacamata agama, bukanlah semata-mata fenomena alam biasa. Di balik kepedihan, terdapat potensi kehidupan baru bagi mereka yang menyadari kasih sayang Allah.
Ikuti artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Mureks mencatat bahwa berdasarkan pantauan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) per 6 Januari 2026, jumlah korban di Aceh dan Sumatra telah mencapai 1.178 orang. Bagi para korban yang meninggal dunia, Asep Abdurrohman meyakini mereka akan mendapatkan nilai syahid di sisi Allah.
Bagi mereka yang terdampak langsung, musibah banjir memberikan pelajaran berharga tentang hakikat kehidupan. Hidup tak ubahnya perjalanan yang terkadang menyusuri jalan tanjakan, terkadang berkelok, licin, dan penuh bebatuan. Kebahagiaan dan kesulitan, menurutnya, hampir selalu bergantian hadir.
Asep Abdurrohman mengingatkan, adalah sebuah kekeliruan jika seseorang merasa selalu bahagia, sebab pada suatu waktu ia pasti akan menghadapi kesulitan dan kepedihan. Dua situasi ini berfungsi sebagai ‘kawah candradimuka’, sebuah tempat penggemblengan dalam istilah pewayangan, yang bertujuan agar manusia menjadi kuat dan tidak cengeng.
Memang, musibah banjir seringkali merenggut harta benda, orang-orang tercinta, serta menghilangkan rasa nyaman dan kedamaian. Namun, di sisi lain, kondisi sulit ini juga dapat memicu energi baru untuk bangkit dari keterpurukan.
Kebangkitan dari keterpurukan, dalam konteks agama, mendorong seseorang untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Asep Abdurrohman mengamati, pada umumnya, saat berada dalam kondisi bahagia, banyak orang cenderung lupa atau menjaga jarak dengan Tuhannya. Namun, ketika musibah dan kesulitan menghampiri, tidak sedikit manusia yang justru mendekat, meskipun ada pula yang lepas kendali.
Dalam kondisi sulit, jiwa seseorang menjerit dan mengadu kepada Tuhannya. Musibah berupa banjir kayu dan lumpur, seringkali membuat mulut orang beriman spontan mengeluarkan kata-kata thayyibah, seperti “ya Allah”, “Allah Akbar”, atau “innalillahi wa innailaihi rojiun.”
Tidak hanya itu, setiap salat dilakukan dengan khusyuk, bahkan diiringi isak tangis saat menyebut nama Tuhannya. Terlebih lagi, saat terbangun di tengah malam, waktu yang dianggap mustajab bagi mereka yang mengalami musibah untuk mengadu dan mencurahkan isi hati kepada Tuhan.
Pada waktu yang mustajab itu, para korban musibah menengadahkan tangan, memohon kekuatan dan hikmah besar dari setiap cobaan yang datang. Mereka juga memohon agar keluarga korban yang meninggal dunia diberikan nilai syahid di sisi-Nya.
Proposal doa itu terus menerus diucapkan oleh sang hamba yang terkena musibah. Datang waktu salat dan malam tiba, sajadah menjadi kumal dan lusuh, pertanda seringnya digunakan. Sajadah itu pun menjadi saksi sekaligus sahabat terbaik yang membantu menghadirkan rasa damai saat mengadu kepada-Nya.
Meskipun kumal dan lusuh, sajadah itu sebenarnya penuh dengan cahaya. Karpet, dinding, dan semua benda di kamar seolah merespons dan menyimpan energi spiritual dengan baik. Semesta alam pun ikut memberi dukungan dengan semilir angin kedamaian yang menyibak suasana keheningan di tengah malam.
Suara jangkrik, kodok, dan hewan lain ikut menjadi saksi dan memberikan dukungan atas proposal pengaduan doa kepada Tuhan. Derai air mata dan tangan tak henti-hentinya menengadah. Salat tahajud menjadi khusyuk dan durasinya pun lebih lama.
Sebelum salat tahajud, menunaikan salat taubat dua rakaat menjadi langkah awal. Selesainya, langsung beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas kesalahan tata kelola hutan dan kota yang mungkin menjadi penyebab bencana. Lagi-lagi, tangan terus menengadah, tak bosan-bosannya meminta kepada-Nya.
Keesokan harinya, saat bangun tengah malam, hamba beriman yang terkena musibah kembali bersimpuh. Sebelum bersimpuh, berwudu dengan sebaik-baiknya, menghadap kiblat. Setiap basuhan dihayati, merenungi apakah mulut, mata, atau hidung pernah menyusahkan orang lain karena ulah sikapnya.
Membasuh tangan diresapi, membayangkan apakah ada nasib orang yang menjadi korban karena kekuatan tanda tangannya. Semua anggota wudu saat dibasuh disesali, membayangkan apakah ada sikap dan perilaku yang mendatangkan murka Allah.
Selesai berwudu, tidak lupa menghadap kiblat sambil menengadah ke langit dan mengangkat tangan dengan mengucapkan doa setelah wudu. Makna doa itu diresapi, di dalamnya terdapat syahadat sebagai bentuk peneguhan tauhid, serta doa agar menjadi orang yang suka bertobat dan membersihkan diri.
Setelah itu, beranjak ke kamar kecil khusus untuk berkhalwat dengan Tuhannya. Sajadah dihamparkan, lampu dimatikan, takbir dimulai, dan suara sayup bercampur sedih bergemuruh seiring ucapan takbir yang menggetarkan jiwa.
Suaranya terkadang serak dan parau. Bacaan demi bacaan terasa disaksikan oleh Allah. Ketika membaca surat Al-Fatihah, seolah-olah sedang berdialog langsung dengan Allah. Jiwanya menjadi luluh dan penuh harap.
Rukunya lama dan sujudnya juga lama. Saat sujud, air mata berlinang membasahi kavling kecil berupa sajadah. Bacaan tasyahud akhir terasa seperti mengucapkan janji dan doa penuh khusyuk, hingga tak terasa subuh segera tiba, menyapa dan mengarahkan agar segera bersiap pergi ke masjid. Semoga bermanfaat.