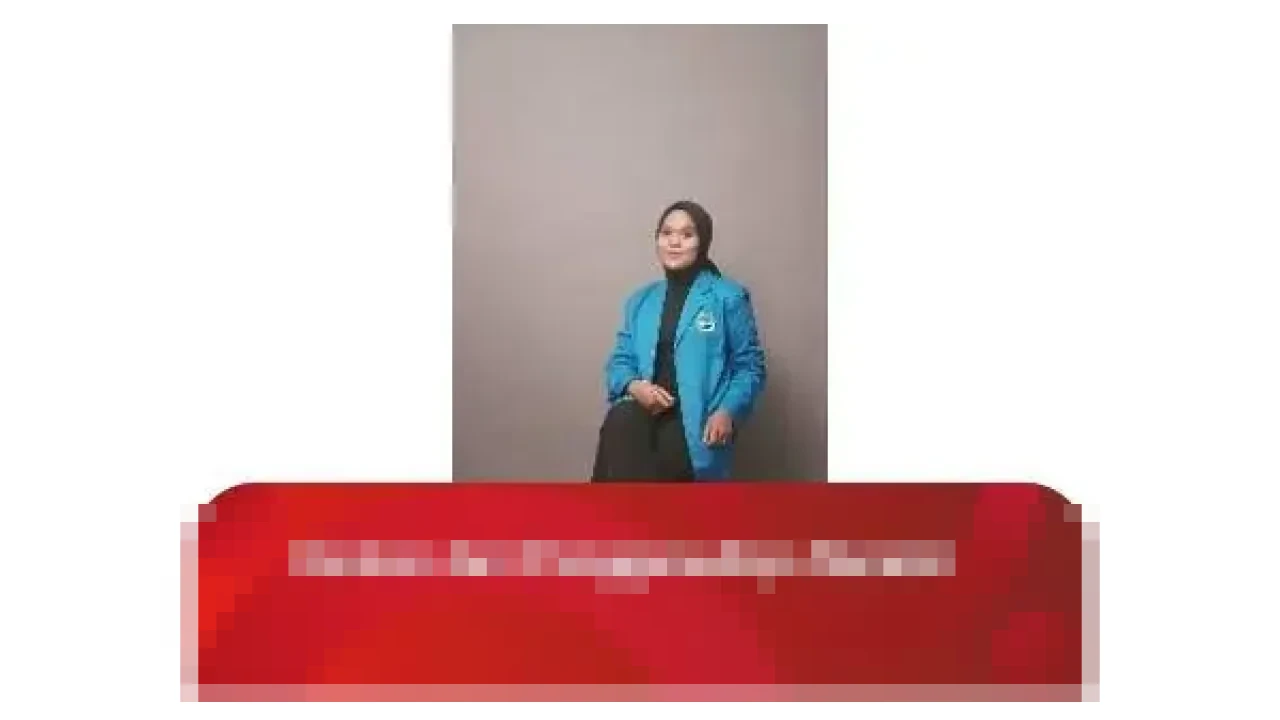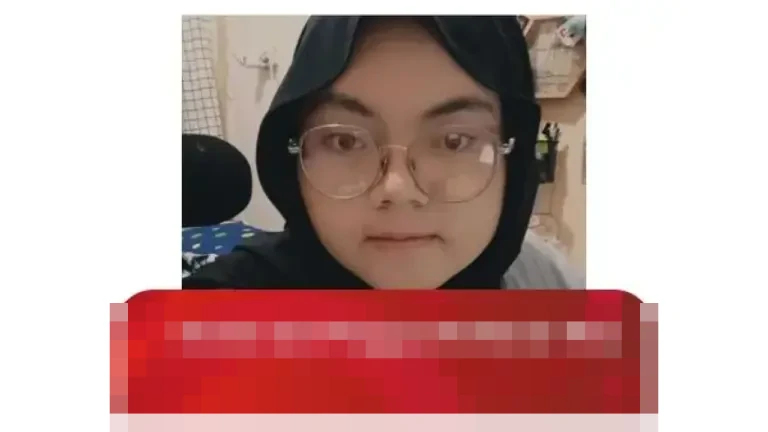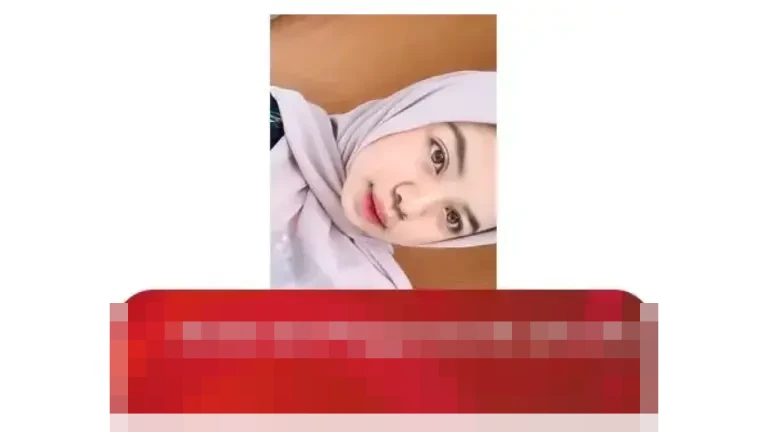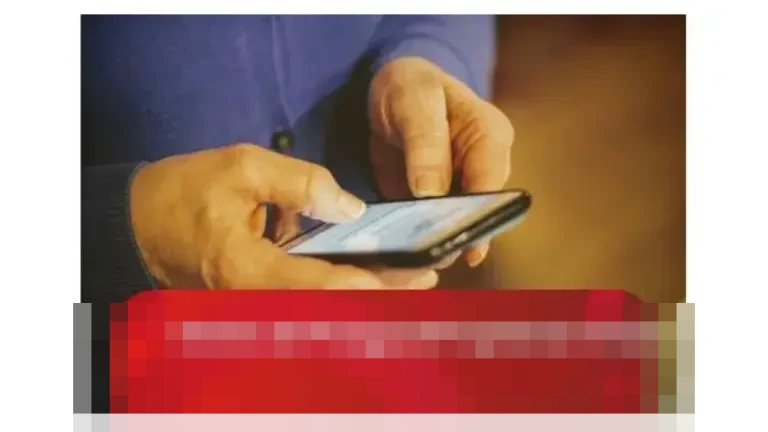Analisis sastra terbaru yang dilakukan oleh Alya Nuraini, seorang mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyoroti bagaimana pengalaman kehilangan, cinta, dan ikatan keluarga dihadirkan secara mendalam melalui tindakan-tindakan tubuh yang sederhana dan berulang di ruang domestik. Studi ini secara spesifik membedah cerpen ‘Semangkuk Perpisahan di Meja Makan’ dan ‘Lidah Masakan Ibu’ menggunakan kerangka fenomenologi kebertubuhan Maurice Merleau-Ponty.
Dalam kedua cerpen tersebut, dapur, masakan, dan meja makan bukan sekadar latar, melainkan medan di mana ingatan bekerja sebagai pengalaman yang dijalani. Ini terlihat dari tangan yang mengulek bumbu, lidah yang mengenali rasa, hingga tubuh yang mengulang kebiasaan yang diwariskan. Makna tidak lahir dari penjelasan rasional tokoh, melainkan tumbuh dari relasi tubuh dengan dunia sekitarnya serta dengan orang lain yang hadir atau telah tiada. Pendekatan ini menuntut pembacaan pada pengalaman hidup yang dihayati secara langsung, sebuah titik pijak yang mengantar pada kerangka fenomenologi Merleau-Ponty.
Baca artikel informatif lainnya di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Fenomenologi Kebertubuhan Maurice Merleau-Ponty
Fenomenologi Maurice Merleau-Ponty berangkat dari kritik terhadap cara berpikir modern yang memusatkan kesadaran pada rasio dan memisahkan pikiran dari tubuh. Dalam pandangan ini, tubuh kerap dipahami sekadar sebagai alat biologis yang dikendalikan oleh pikiran. Merleau-Ponty menolak pemisahan tersebut dengan menegaskan bahwa manusia pada dasarnya adalah subjek yang bertubuh. Dunia tidak pertama-tama hadir melalui pemikiran abstrak, melainkan melalui pengalaman hidup yang konkret sebagaimana dialami secara langsung.
Persepsi menjadi fondasi utama pengalaman manusia, bukan sebagai penerimaan rangsangan secara pasif, melainkan sebagai keterlibatan aktif tubuh dengan dunia. Manusia selalu sudah berada di dalam dunia, dan melalui tubuh itulah dunia tampil sebagai sesuatu yang bermakna. Pandangan ini menegaskan bahwa tubuh dan dunia membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tubuh merupakan “jangkar” manusia di dunia, yakni cara manusia hadir, bergerak, dan berelasi dalam suatu lingkungan pengalaman atau milieu. Dunia hadir menjadi medan pengalaman yang senantiasa dihayati melalui tubuh. Relasi tubuh dan dunia bersifat terbuka dan tidak pernah selesai, karena pengalaman manusia selalu berlangsung dalam keterbatasan ruang dan waktu. Dalam konteks ini, makna lahir dari relasi langsung antara tubuh dan dunia yang dialami secara konkret.
Merleau-Ponty menunjukkan bahwa kesadaran manusia tidak selalu bersifat reflektif dan verbal. Ia memperkenalkan gagasan tentang kesadaran ragawi dan kesadaran bisu, yaitu bentuk kesadaran yang bekerja sebelum bahasa dan konsep muncul. Tubuh menyimpan pengetahuan melalui kebiasaan, gerak, dan ritme yang dijalani secara berulang. Relasi dengan orang lain pun berakar pada kesatuan pra-reflektif, ketika tubuh diri dan tubuh orang lain saling berjumpa dalam satu medan pengalaman bersama. Fenomenologi Merleau-Ponty memberikan landasan bagi pembacaan sastra yang menempatkan pengalaman manusia sebagai pengalaman yang dihayati melalui tubuh, baik dalam relasinya dengan dunia maupun dengan orang lain.
Analisis Alya Nuraini selanjutnya membahas fenomenologi Maurice Merleau-Ponty sebagai landasan pembacaan sastra dengan menitikberatkan pada empat pokok gagasan utama: teori persepsi, relasi tubuh dan dunia, tubuh dan kesadaran, serta hubungan antara tubuh, diri, dan orang lain. Keempat aspek ini digunakan untuk menelusuri bagaimana pengalaman manusia dalam teks sastra tidak disajikan sebagai hasil pemikiran abstrak semata, melainkan sebagai pengalaman yang dihayati melalui keberadaan tubuh di dalam dunia. Dengan pendekatan ini, pembacaan diarahkan pada cara tokoh mengalami, merasakan, dan menjalani dunianya, serta bagaimana relasi dengan lingkungan dan orang lain terbentuk melalui pengalaman ragawi yang konkret.
Persepsi
Dalam ‘Semangkuk Perpisahan di Meja Makan’ dan ‘Lidah Masakan Ibu’, memasak tidak pernah hadir sebagai aktivitas netral. Ia dialami melalui persepsi yang lahir dari keterlibatan langsung tubuh dengan dunia. Perbedaan utama kedua cerpen ini terletak pada arah persepsi tokohnya. Tokoh “saya” dalam cerpen ‘Semangkuk Perpisahan di Meja Makan’ memulai cerita dengan persepsi yang berjarak dan skeptis terhadap memasak, “lalu, mengapa harus susah payah memasak segala?” sementara Yudhis dalam cerpen ‘Lidah Masakan Ibu’, justru sejak awal memiliki persepsi yang lekat, hangat, dan afektif terhadap dapur, “senang rasanya melihat itu. Aku senang pas tahu di dapur Mamak lagi mempersiapkan santapan.” Kedua persepsi ini, menurut Mureks, lahir dari posisi tubuh yang berbeda di dalam dunia, yaitu satu hidup dalam dunia serba instan, dan yang lain tumbuh dalam dunia dapur yang terus dihayati.
Persepsi awal tokoh “saya” dalam cerpen ‘Semangkuk Perpisahan di Meja Makan’ dibentuk oleh pengalaman tubuhnya di dunia modern yang serba praktis. Ia memandang dunia makan sebagai sesuatu yang bisa diakses tanpa keterlibatan tubuh, “Haus dan lapar tinggal buka ponsel. Hanya perlu satu jari untuk membuatnya ada di depan mata.” Persepsi ini memperlihatkan tubuh yang dijauhkan dari pengalaman langsung. Dunia hadir sebagai sesuatu yang siap pakai. Sebaliknya, Yudhis dalam ‘Lidah Masakan Ibu’ mengalami dunia dapur sebagai ruang yang hidup. Persepsinya tidak dibentuk oleh efisiensi, tetapi oleh kehadiran asap, bunyi minyak, dan aroma bumbu yang “berusaha memanggil dengan tenang kenangan masa lalu lewat indra penciuman.” Di sini, persepsi bekerja sebagaimana dimaksud Merleau-Ponty, yaitu dunia hadir melalui indra dan tubuh.
Perbedaan persepsi ini makin terlihat ketika kedua cerpen menampilkan momen belajar memasak. Dalam cerpen ‘Semangkuk Perpisahan di Meja Makan’, persepsi tokoh berubah perlahan melalui pengalaman langsung di dapur ibu. Awalnya ia menyanggah, “memang apa bedanya, Bu? Toh, sama-sama akan dihaluskan juga”, namun persepsi itu runtuh ketika ia menyaksikan cara ibu memecah kemiri. Gerakan ibu digambarkan sangat konkret, “gerakannya hati-hati sekali. Persis seperti menolong bayi memecah gelap rahim menuju bumi.” Persepsi tokoh tidak berubah karena argumen, melainkan karena penglihatan tubuh yang menyaksikan langsung cara kerja tangan ibu. Sementara itu, dalam cerpen ‘Lidah Masakan Ibu’, Yudhis kecil belajar melalui pengamatan yang berulang. “ketika Mamak masih hidup, Yudhis selalu suka memantau gerak-geriknya di dapur.” Persepsi Yudhis tumbuh dari kebersamaan tubuh di ruang yang sama, bukan dari penjelasan verbal.
Kedua cerpen juga sama-sama menunjukkan bahwa persepsi bersifat inderawi dan melekat pada pengalaman konkret. Dalam cerpen ‘Semangkuk Perpisahan di Meja Makan’, persepsi tokoh diasah melalui urutan kerja memasak yang harus disimak bersamaan, “tidak akan ada salinan materi dari file presentasi. Semua mesti disimak dan dicatat bersamaan.” Kalimat ini menandai pergeseran cara memahami dunia, yaitu dari dunia akademik yang reflektif ke dunia dapur yang menuntut perhatian tubuh secara langsung. Dalam cerpen ‘Lidah Masakan Ibu’, persepsi inderawi justru menjadi pintu masuk ingatan. Aroma bumbu membuat Yudhis “segera teringat ketika Mamak memasak setelah mereka sekeluarga menunaikan salat Magrib.” Persepsi penciuman menghadirkan kembali dunia yang pernah dialami.
Persepsi dalam kedua cerpen juga bekerja melampaui waktu. Pada cerpen ‘Semangkuk Perpisahan di Meja Makan’, pemahaman tentang kematian tidak hadir sebagai wacana, melainkan melalui pengalaman memasak dan makan bersama. Metafora sayur dalam gangan “semua sama akan lunak juga setelah dimasak” diterima tokoh sebagai sesuatu yang dialami di meja makan. Dalam cerpen ‘Lidah Masakan Ibu’, persepsi bahkan menembus batas hidup dan mati. Musa melihat “seseorang yang mirip ayah dengan badan yang lebih kecil… sedang memasak dengan seorang perempuan.” Persepsi ini menunjukkan bahwa dapur menjadi ruang tempat pengalaman masa lalu terus hadir, sebagai pengalaman yang masih dirasakan.
Jika dibaca melalui fenomenologi Merleau-Ponty, kedua cerpen ini sama-sama menempatkan persepsi sebagai fondasi makna, tetapi dengan arah yang berbeda. ‘Semangkuk Perpisahan di Meja Makan’ menampilkan perubahan persepsi dari jarak menuju keterlibatan, dari penolakan menuju pengalaman. Sementara ‘Lidah Masakan Ibu’ menampilkan kontinuitas persepsi, yaitu dapur yang sejak awal sudah bermakna dan terus dihidupi hingga dewasa. Keduanya menunjukkan bahwa dunia dalam sastra tidak hadir sebagai latar mati, melainkan sebagai sesuatu yang dialami, dirasakan, dan dihayati melalui tubuh. Inilah inti fenomenologi Merleau-Ponty bahwa sastra bukan sekadar menceritakan peristiwa, tetapi memperlihatkan bagaimana manusia mengalami dunia melalui persepsinya.
Tubuh dan Dunia
Dalam ‘Semangkuk Perpisahan di Meja Makan’ dan ‘Lidah Masakan Ibu’, dunia hadir sebagai ruang yang dialami langsung oleh tubuh tokoh. Inilah titik temu kedua cerpen jika dibaca melalui fenomenologi Maurice Merleau-Ponty, yaitu dunia tidak dipahami lewat pikiran terlebih dahulu, tetapi dihidupi melalui tubuh. Namun, arah relasi tubuh dan dunia dalam kedua cerpen ini berbeda. Cerpen ‘Semangkuk Perpisahan di Meja Makan’ menampilkan dunia dapur sebagai sesuatu yang awalnya asing bagi tubuh tokoh, sementara cerpen ‘Lidah Masakan Ibu’ justru menghadirkan dapur sebagai dunia yang sejak awal menyatu dengan tubuh tokohnya.
Dalam cerpen ‘Semangkuk Perpisahan di Meja Makan’, dunia modern mula-mula dihadirkan sebagai dunia yang menjauhkan tubuh dari pengalaman langsung. Tokoh “saya” merasakan dunia makan sebagai sesuatu yang instan dan tidak menuntut kehadiran tubuh sepenuhnya, “Haus dan lapar tinggal buka ponsel. Hanya perlu satu jari untuk membuatnya ada di depan mata.” Kutipan ini memperlihatkan tubuh yang direduksi menjadi jari, sementara dunia hadir sebagai layanan cepat. Tubuh tidak lagi berhadapan dengan api, wajan, atau bau bumbu, melainkan dengan layar. Dalam kerangka Merleau-Ponty, relasi tubuh dan dunia di sini menjadi renggang karena dunia tidak dialami, hanya diakses.
Sebaliknya, dalam ‘Lidah Masakan Ibu’, dunia sejak awal dihadirkan sebagai sesuatu yang menyapa tubuh secara penuh. Dapur digambarkan melalui asap, bunyi, dan aroma, “Sedang di dapur, asap mengepul. Yudhis mencincang bawang merah, bawang putih, cabai, juga tomat.” Dunia hadir sebagai ruang yang aktif, sementara tubuh Yudhis terlibat langsung di dalamnya. Tidak ada jarak antara tubuh dan dunia karena keduanya saling mengisi. Inilah yang dimaksud Merleau-Ponty ketika menyebut tubuh sebagai “jangkar” manusia di dunia, karena tanpa tubuh yang mencincang, mengaduk, dan mencium aroma, dunia dapur tidak bermakna.
Perubahan relasi tubuh dan dunia tampak jelas ketika tokoh “saya” dalam cerpen ‘Semangkuk Perpisahan di Meja Makan’ akhirnya benar-benar masuk ke dapur ibu. Dunia dapur menjadi ruang fisik dan medan pengalaman yang menuntut keterlibatan tubuh sepenuhnya, “Lantai dapur mendadak penuh oleh jagung, ubi kayu, kacang panjang, waluh, aneka bumbu, dan umbut kelapa.” Dunia dihadirkan melalui keberlimpahan benda yang harus disentuh, dipilah, dan diolah. Tubuh tokoh tidak bisa lagi menjaga jarak, ia harus ikut bergerak di dalam dunia tersebut. Dalam konteks ini, dunia tidak dipahami lewat konsep, tetapi lewat keberadaan fisik yang konkret.
Relasi tubuh dan dunia dalam cerpen ini makin dipertegas melalui adegan memecah kemiri. Ibu menegur cara anaknya bekerja dengan tubuh, “Bukan begitu cara memecah kemiri, nanti hancur!” Dunia kemiri tidak netral; ia menuntut perlakuan tertentu dari tubuh. Ketika ibu mempraktikkan caranya, “gerakannya hati-hati sekali” dunia dan tubuh saling menyesuaikan. Kemiri tidak ditaklukkan, tetapi dihadapi dengan perhatian. Inilah relasi tubuh-dunia yang ditekankan Merleau-Ponty bahwa dunia memberi resistensi, tubuh menanggapi, dan makna lahir dari pertemuan keduanya.
Sementara itu, dalam ‘Lidah Masakan Ibu’, relasi tubuh dan dunia tidak dibangun melalui proses belajar yang terlambat, melainkan melalui kebiasaan sejak kecil. Dunia dapur bahkan tetap hidup ketika tubuh Mamak telah tiada. Ketika Yudhis kecil masuk ke dapur dan mendapati ruang itu kosong, dunia terasa berubah secara fisik, “Ruangan yang hangat itu terasa dingin membeku.” Dunia tidak netral, kehadiran atau ketiadaan tubuh mengubah cara dunia dirasakan. Kehangatan dan dingin bukan sekadar suhu, melainkan pengalaman tubuh yang kehilangan relasi dengan tubuh lain.
Relasi tubuh dan dunia dalam cerpen ‘Lidah Masakan Ibu’, juga tampak pada cara ingatan bekerja melalui indra. Aroma bumbu bukan sekadar bau, melainkan pintu ke dunia masa lalu, “Aroma harum bumbu … berusaha memanggil dengan tenang kenangan masa lalu lewat indra penciuman.” Dunia hadir kembali bukan melalui ingatan abstrak, tetapi melalui tubuh yang mencium. Dunia masa lalu tidak dikenang, melainkan dialami ulang secara inderawi. Ini sejalan dengan gagasan Merleau-Ponty bahwa dunia selalu hadir sebagai dunia-yang-dihayati, bukan dunia-yang-dipikirkan.
Kedua cerpen juga sama-sama menempatkan meja makan sebagai titik pertemuan tubuh dan dunia. Dalam cerpen ‘Semangkuk Perpisahan di Meja Makan’, meja makan menjadi ruang terakhir perjumpaan sebelum kematian ibu, di mana dunia dipahami melalui sajian yang disantap bersama, “Mari kita makan.” Dunia tidak dijelaskan, tetapi dijalani melalui makan. Dalam cerpen ‘Lidah Masakan Ibu’, meja makan menjadi ruang lintas waktu, ketika Yudhis dewasa, Yudhis kecil, dan Mamak seolah hadir bersamaan, “Kini ia paham, di dapur hanya ada ia yang masih kanak dengan Mamak yang telah tiada.” Dunia dapur tidak berhenti ketika waktu berlalu, ia terus hidup selama tubuh masih mengulang pengalaman yang sama.
‘Semangkuk Perpisahan di Meja Makan’ memperlihatkan pergeseran relasi tubuh dan dunia, mulai dari dunia instan yang menjauhkan tubuh, menuju dunia dapur yang menuntut kehadiran penuh. Sementara ‘Lidah Masakan Ibu’ menampilkan kesinambungan relasi tubuh dan dunia, di mana dapur sejak awal menjadi dunia yang dihidupi dan terus dihadirkan kembali melalui tubuh. Keduanya sama-sama menegaskan bahwa dunia dalam sastra bukan sekadar latar, melainkan sesuatu yang hadir, bekerja, dan bermakna karena dialami oleh tubuh.
Tubuh dan Kesadaran
Dalam ‘Semangkuk Perpisahan di Meja Makan’ dan ‘Lidah Masakan Ibu’, pengalaman memasak tidak pernah dihadirkan sebagai aktivitas teknis semata. Kedua cerpen ini justru menempatkan tubuh sebagai pusat kesadaran, sebagaimana ditegaskan Merleau-Ponty bahwa kesadaran manusia tidak selalu bekerja lewat refleksi rasional, melainkan melalui keterlibatan tubuh yang hidup di dalam dunia. Namun, cara tubuh menyadari dan mengalami dunia dalam kedua cerpen ini bergerak dari arah yang berbeda. Pada cerpen Miranda Seftiana, kesadaran tubuh tokoh “saya” mula-mula terputus dari pengalaman langsung, sementara pada cerpen ‘Lidah Masakan Ibu’, kesadaran tubuh Yudhis sejak awal tumbuh dan bekerja melalui kebiasaan ragawi.
Pada bagian awal ‘Semangkuk Perpisahan di Meja Makan’, tubuh tokoh “saya” digambarkan nyaris tidak hadir dalam pengalaman makan dan memasak. Kesadaran bekerja secara praktis dan instan, sebagaimana tampak dalam kutipan, “Haus dan lapar tinggal buka ponsel. Hanya perlu satu jari untuk membuatnya ada di depan mata.” Tubuh direduksi menjadi satu jari, dan kesadaran tidak lagi berakar pada pengalaman inderawi. Dalam kerangka Merleau-Ponty, ini menunjukkan kesadaran yang tercerabut dari tubuh; dunia hadir bukan sebagai sesuatu yang dialami, melainkan sekadar diakses. Sebaliknya, dalam ‘Lidah Masakan Ibu’, sejak kalimat awal dapur sudah dihadirkan sebagai ruang tubuh yang aktif, “Sedang di dapur, asap mengepul. Yudhis mencincang bawang merah, bawang putih, cabai, juga tomat.” Kesadaran Yudhis tidak dijelaskan melalui pikiran atau niat abstrak, tetapi melalui gerak tangan, bunyi cincangan, dan asap. Tubuh bekerja lebih dulu, kesadaran menyusul di dalam gerak itu sendiri.
Perbedaan ini semakin jelas ketika kesadaran tubuh mulai terbentuk melalui kebiasaan. Dalam cerpen Miranda, tokoh “saya” mengakui bahwa dirinya bisa memasak, tetapi hanya sebatas bertahan hidup, “Saya pernah merebus mi instan, menggoreng telur, atau beberapa hal lain untuk bertahan hidup.” Kesadaran tubuh di sini bersifat minimal, sekadar fungsional. Ia belum memiliki kedalaman pengalaman ragawi. Sementara itu, Yudhis kecil dalam cerpen ‘Lidah Masakan Ibu’, justru menunjukkan kesadaran tubuh yang tumbuh dari kedekatan sehari-hari, “Aku senang pas tahu di dapur Mamak lagi mempersiapkan santapan untukku sama Abah.” Kesadaran ini tidak lahir dari perintah atau kewajiban, melainkan dari rasa senang yang dialami tubuh saat berada di dapur. Dalam istilah Merleau-Ponty, kesadaran ini bersifat pra-reflektif—tubuh sudah merasa dan memahami sebelum pikiran menjelaskannya.
Momen penting dalam ‘Semangkuk Perpisahan di Meja Makan’ terjadi ketika tubuh tokoh “saya” mulai benar-benar belajar melalui praktik langsung. Adegan memecah kemiri menjadi titik balik kesadaran tubuh. Ketika ibu berkata, “Bukan begitu. cara memecah kemiri, nanti hancur!” yang dikoreksi bukan pikiran, melainkan cara tubuh bekerja. Saat ibu memperagakan caranya, “Gerakannya hati-hati sekali” kesadaran tokoh “saya” tidak muncul lewat penjelasan teoretis, melainkan lewat pengamatan tubuh terhadap tubuh lain. Ia menyadari sesuatu bukan karena diberi definisi, tetapi karena melihat dan merasakan ketepatan gerak. Hal serupa telah lama dialami Yudhis dalam ‘Lidah Masakan Ibu’. Ia tidak pernah belajar memasak melalui instruksi formal, melainkan dengan “memantau gerak-geriknya di dapur.” Kesadaran tubuhnya terbentuk dari pengulangan, dari kebiasaan melihat, mencium, dan meniru.
Kesadaran tubuh juga tampak bekerja kuat melalui indra penciuman dalam kedua cerpen. Dalam cerpen Edwin, aroma menjadi pemicu hadirnya kesadaran masa lalu, “Aroma harum bumbu… berusaha memanggil dengan tenang kenangan masa lalu lewat indra penciuman.” Kesadaran tidak dipanggil oleh ingatan rasional, melainkan oleh tubuh yang mencium. Dunia masa lalu hadir kembali karena tubuh masih mampu merasakannya. Dalam cerpen ‘Semangkuk Perpisahan di Meja Makan’, kesadaran tubuh justru muncul melalui sentuhan dan gerak tangan, “Bagai sekolah lagi, saya dituntun melalui satu per satu proses memasak sayur ini.” Kata “sekolah” di sini bukan menunjuk ruang belajar formal, melainkan pengalaman tubuh yang kembali belajar merasakan dunia secara langsung.
Puncak relasi tubuh dan kesadaran dalam ‘Semangkuk Perpisahan di Meja Makan’ hadir ketika ibu berbicara tentang beras usang dan sayur dalam gangan. Meski tampak seperti perumpamaan, kesadaran tokoh “saya” tidak dibentuk oleh makna abstrak, melainkan oleh pengalaman makan bersama. Kesadaran akan kefanaan tubuh manusia hadir bersamaan dengan aktivitas menyendok nasi dan menyantap gangan. Dalam cerpen Edwin, kesadaran serupa hadir ketika Musa berkata, “Di dapur ini, aku cuma lihat seseorang yang mirip. ayah dengan badan yang lebih kecil.” Kesadaran anak itu tidak lahir dari penjelasan tentang kematian, melainkan dari apa yang dilihat tubuhnya di dapur. Tubuh kecil Yudhis dan tubuh Mamak yang telah tiada hadir bersamaan dalam satu pengalaman ragawi.
Akhir kedua cerpen menegaskan bahwa kesadaran tubuh tidak berhenti meski tubuh ibu telah tiada. Dalam cerpen Miranda, tokoh “saya” memilih memasak sendiri untuk prosesi kematian ibunya, “Saya hanya mau Ibu bahagia. karena putrinya bisa memasak.” Kesadaran tubuhnya kini bekerja mandiri, tetapi masih digerakkan oleh pengalaman ragawi bersama ibu. Dalam cerpen Edwin, Yudhis menyadari bahwa selama ini ia “hanya mengulang-ulang resep yang sama dari Mamak.” Kesadarannya tidak berisi penciptaan baru, melainkan keberlanjutan pengalaman tubuh yang diwariskan. Dalam pandangan Merleau-Ponty, inilah bentuk kesadaran ragawi yang hidup: kesadaran yang tidak sepenuhnya verbal, tetapi terus bergerak melalui tubuh yang mengulang, memasak, dan menyajikan.
Kedua cerpen ini sama-sama menunjukkan bahwa tubuh bukan sekadar alat pelaksana kehendak pikiran. Tubuh adalah tempat kesadaran bekerja, tumbuh, dan diwariskan. ‘Semangkuk Perpisahan di Meja Makan’ menampilkan kesadaran tubuh yang perlahan dibangunkan kembali, sementara ‘Lidah Masakan Ibu’ memperlihatkan kesadaran tubuh yang sejak kecil telah hidup dan terus berlanjut. Keduanya bertemu pada satu hal penting yaitu kesadaran manusia, sebagaimana ditegaskan Merleau-Ponty, tidak lahir dari pikiran yang berdiri sendiri, melainkan dari tubuh yang mengalami dunia secara langsung.
Tubuh, Diri, dan Orang Lain
Dalam ‘Semangkuk Perpisahan di Meja Makan’ karya Miranda Seftiana dan ‘Lidah Masakan Ibu’ karya Edwin, relasi antara ibu dan anak tidak dibangun melalui penjelasan batin atau pernyataan emosional yang berlebihan, melainkan melalui perjumpaan tubuh dengan tubuh lain dalam ruang dapur. Di sinilah gagasan Merleau-Ponty tentang tubuh, diri, dan orang lain bekerja secara nyata, yaitu orang lain tidak hadir sebagai objek yang dipikirkan, tetapi sebagai tubuh yang dialami secara langsung. Pada cerpen Miranda, relasi ini tampak ketika tokoh “saya” berhadapan dengan tubuh ibu yang mengajar lewat gerak, bukan lewat ceramah. Kutipan, “Tanpa menyanggah saya saksikan ibu memecah kemiri. Gerakannya. hati-hati sekali” menunjukkan bahwa pengenalan terhadap ibu tidak terjadi melalui nasihat verbal, melainkan melalui pengamatan tubuh terhadap tubuh lain. Tubuh ibu menjadi medium pemahaman, sementara tubuh anak belajar dengan cara menyaksikan dan meniru. Hal ini sejalan dengan Merleau-Ponty yang menegaskan bahwa relasi dengan orang lain bersifat pra-reflektif: tubuh terlebih dahulu memahami sebelum pikiran menafsirkan.
Relasi tubuh dan orang lain dalam cerpen ‘Lidah Masakan Ibu’, bahkan sudah bekerja sejak masa kanak-kanak. Yudhis kecil memahami kehadiran ibunya bukan melalui penjelasan tentang peran ibu, melainkan lewat pengalaman ragawi di dapur. Hal ini tampak dalam pengakuannya, “Aku senang pas tahu di dapur Mamak lagi mempersiapkan santapan untukku sama Abah.” Rasa senang ini bukan hasil refleksi rasional, melainkan pengalaman tubuh yang merasakan kehangatan ruang, aroma masakan, dan keberadaan tubuh ibu di dekatnya. Tubuh Mamak hadir sebagai “yang lain” yang tidak pernah berdiri di luar diri Yudhis, melainkan selalu sudah menyatu dalam pengalaman kesehariannya. Dalam pandangan Merleau-Ponty, inilah bentuk relasi intersubjektif yang paling dasar: diri dan orang lain berbagi dunia yang sama melalui tubuh.
Pada ‘Semangkuk Perpisahan di Meja Makan,’ relasi tubuh, diri, dan orang lain juga tampak jelas dalam adegan pelukan di ambang pintu: “Begitu membuka pintu, ia segera memeluk. dengan erat.” Tidak ada dialog panjang, tidak ada penjelasan perasaan, tetapi tubuh ibu langsung menyapa tubuh anak. Pelukan ini menjadi bentuk komunikasi yang mendahului bahasa. Diri tokoh “saya” dikenali melalui sentuhan tubuh orang lain, bukan melalui refleksi batin. Hal ini menegaskan pandangan Merleau-Ponty bahwa hubungan antarmanusia tidak bermula dari penilaian intelektual, melainkan dari perjumpaan tubuh dengan tubuh.
Relasi ini semakin kuat ketika ibu dalam cerpen ‘Semangkuk Perpisahan di Meja Makan’, mengaitkan pengalaman tubuhnya sebagai perempuan, ibu, dan manusia yang menua dengan tubuh anaknya. Ucapannya, “Kalau sudah tahu akan mati dan hancur, apa sembarangan juga perlakuanmu saat mengeluarkan bayi dari perut ibunya?” tidak berdiri sebagai nasihat moral, melainkan sebagai pengakuan tubuh kepada tubuh lain. Tubuh ibu yang pernah melahirkan berbicara kepada tubuh anak yang sehari-hari bekerja mengeluarkan bayi. Di sini, diri dan orang lain saling bertemu dalam pengalaman ragawi yang sama, meski berada pada posisi generasi yang berbeda. Dunia mereka bukan dunia konsep, melainkan dunia tubuh yang sama-sama rapuh dan fana.
Dalam ‘Lidah Masakan Ibu,’ relasi tubuh, diri, dan orang lain justru terus berlanjut meski tubuh ibu telah tiada. Hal ini tampak kuat dalam pengakuan Musa, “Di dapur ini, aku cuma lihat seseorang yang mirip. ayah dengan badan yang lebih kecil.” Persepsi Musa tidak memisahkan antara tubuh ayah dan tubuh Yudhis kecil. Ini menunjukkan bahwa kehadiran orang lain, bahkan yang telah tiada, dapat terus dirasakan dan dihayati melalui pengalaman tubuh di ruang yang sama. Dapur menjadi tempat di mana ikatan keluarga melampaui batas fisik dan waktu, terus hidup dalam memori ragawi.
Secara keseluruhan, analisis Alya Nuraini menegaskan bahwa kedua cerpen ini secara efektif menggambarkan bagaimana fenomenologi Merleau-Ponty dapat digunakan untuk memahami kedalaman pengalaman manusia. Melalui dapur, masakan, dan interaksi tubuh, cerpen-cerpen ini menunjukkan bahwa kehilangan dan ikatan keluarga bukanlah konsep abstrak, melainkan pengalaman yang dihayati secara konkret oleh tubuh dalam relasinya dengan dunia dan orang lain.