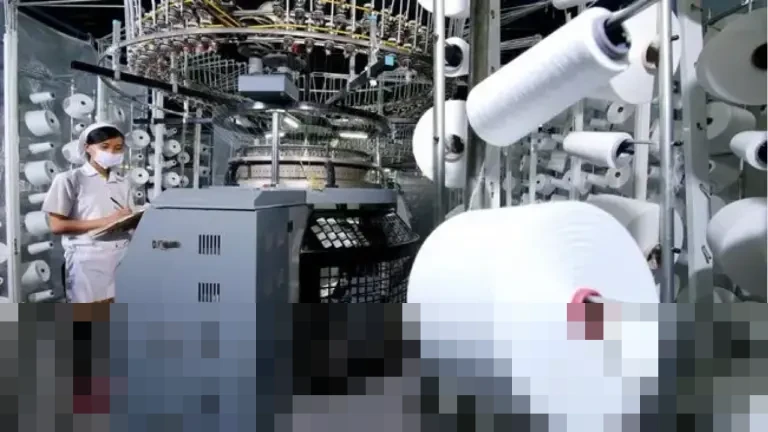Jakarta – Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyoroti kondisi ketergantungan Indonesia pada beras yang disebut sebagai “Perangkap Beras”. Kondisi ini, menurut studi terbaru mereka, menghambat ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan pedesaan.
Jargon swasembada pangan yang kini kerap digaungkan Presiden Prabowo Subianto bukanlah hal baru. Sejak era 1970-an, cita-cita swasembada pangan telah menjadi simbol kedaulatan nasional. Namun, LPEM FEB UI mencatat, sektor pertanian justru makin tak mampu menopang struktur perekonomian Indonesia.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Pangsa pertanian dalam produk domestik bruto (PDB) menyusut drastis dari sekitar 40% pada 1970-an menjadi hanya 12% pada tahun 2023. Penurunan serupa juga terjadi pada proporsi tenaga kerja di sektor ini, dari hampir dua pertiga angkatan kerja menjadi kurang dari sepertiga.
“Perlunya kebijakan yang mendorong pertumbuhan agroindustri pengolahan, diversifikasi, serta peningkatan standar mutu guna menyelaraskan produksi dengan tren konsumsi,” demikian kutipan dari LPEM-FEBUI Working Paper berjudul ‘Mengukur dan Mentransformasi Sistem Pangan-Pertanian Indonesia: Dari Ketergantungan pada Beras menuju Pertumbuhan yang Terdiversifikasi’, yang dirilis Senin (29/12/2025).
Dalam karya ilmiah yang ditulis oleh Mohamad Ikhsan, Hadyan Prabowo, dan Ibrahim Naufal tersebut, LPEM FEB UI mengidentifikasi beras sebagai produk pertanian dominan yang menyebabkan masyarakat Indonesia sangat bergantung padanya sebagai bahan pangan utama. Ketergantungan inilah yang menciptakan dilema kebijakan “Perangkap Beras”.
Perangkap beras terjadi karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah konsumen beras, baik di pedesaan maupun perkotaan. Akibatnya, perlindungan harga bagi konsumen menjadi isu yang sangat sensitif secara politik, membuat kebijakan perberasan cenderung kaku dan sulit diubah.
Di sisi lain, petani sebagai produsen beras justru tergolong kelompok miskin, baik buruh tani tak bertanah maupun petani kecil dengan lahan terfragmentasi. Kondisi ini mendorong mereka bermigrasi ke pekerjaan nonpertanian dengan upah lebih tinggi, yang pada gilirannya memicu penurunan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian dan menyusutnya kontribusi sektor ini terhadap PDB.
Dilema “Perangkap Beras” ini, menurut tim ekonom LPEM FEB UI, sebenarnya sudah pernah dikonsepkan solusinya oleh ayah Presiden Prabowo Subianto, Profesor Soemitro Djojohadikusumo. Pada awal periode 1970-an, Soemitro pernah mengusulkan pendirian pabrik pengolahan gandum di Indonesia.
Gagasan ini pada masanya sangat kontroversial karena gandum bukan bagian dari pola makan tradisional Indonesia. Hanya sedikit rumah tangga yang memiliki pengalaman mengonsumsinya sebagai bahan pangan pokok.
“Namun, pemikiran Soemitro didasarkan pada pandangan strategis jangka panjang. Ia memahami bahwa ketergantungan eksklusif pada beras sebagai pangan pokok utama Indonesia pada akhirnya akan membatasi ketahanan pangan dan menyulitkan pengendalian inflasi,” kata tim ekonom LPEM FEB UI dalam Working Paper 088, edisi November 2025 itu.
Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, tekanan terhadap luas lahan di Pulau Jawa yang meningkat, serta keterbatasan peningkatan produktivitas, beras saja tidak akan mampu menopang ketahanan pangan nasional. Meskipun Presiden Soeharto menyetujui konsep tersebut, pelaksanaannya kemudian diserahkan kepada operator lain.
“Jika ditinjau kembali, eksperimen kebijakan ini menunjukkan bagaimana imajinasi dan diversifikasi berperan penting dalam mencegah ketergantungan yang berlebihan pada beras,” tulis tim ekonom LPEM FEB UI.
Empat Alasan Indonesia Masih Terjebak ‘Perangkap Beras’
-
Sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan konsumen bersih beras, baik di perdesaan maupun perkotaan. Oleh karena itu, perlindungan harga bagi konsumen menjadi isu yang sangat sensitif secara politik, sehingga kebijakan perberasan cenderung kaku dan sulit diubah.
-
Rumah tangga produsen beras secara tidak proporsional merupakan kelompok miskin. Baik buruh tani tak bertanah maupun petani kecil dengan lahan yang terfragmentasi tetap terjebak di sekitar atau di bawah garis kemiskinan. Jalur utama untuk keluar dari kondisi tersebut adalah bermigrasi ke pekerjaan nonpertanian dengan upah yang lebih tinggi.
-
Meskipun mendapatkan subsidi input yang besar—seperti pupuk, irigasi, dan berbagai bentuk dukungan lainnya—petani padi Indonesia tidak mampu menandingi daya saing negara-negara tetangga di kawasan. Hal ini bukan karena lahannya kurang produktif, melainkan karena terlalu banyak tenaga kerja yang terlibat dalam usaha tani padi di lahan yang terlalu sempit, sehingga menciptakan inefisiensi struktural.
-
Beban fiskal untuk menopang sektor perberasan terus meningkat. Subsidi, operasi pengadaan, dan program stabilisasi menyerap porsi besar dari anggaran pertanian, sehingga mengurangi ruang fiskal untuk investasi dalam diversifikasi.
Implikasi dari masalah ini, menurut tim ekonom LPEM FEB UI, jelas: Indonesia tidak dapat mencapai ketahanan pangan jangka panjang maupun kesejahteraan perdesaan dengan terus menggandakan fokus pada beras. Solusinya terletak pada upaya bertahap untuk mengalihkan petani ke komoditas bernilai tambah lebih tinggi dan ke pekerjaan nonpertanian dengan pendapatan yang lebih baik.
Selain itu, subsidi perlu diarahkan kembali ke faktor-faktor pendukung seperti infrastruktur, keterampilan, teknologi, dan pembiayaan, yang mendorong kegiatan yang lebih beragam dan produktif.
“Pelajaran dari usulan gandum Soemitro karena itu sangat relevan hingga hari ini: melepaskan diri dari jebakan beras memerlukan cara berpikir di luar kebiasaan serta keberanian untuk menghadapi ketergantungan pada jalur kebijakan lama,” ucap mereka dalam karya ilmiahnya itu.
Tim ekonom LPEM FEB UI menekankan, ketahanan pangan masa depan Indonesia tidak bergantung pada mempertahankan beras dengan segala cara, melainkan pada penataan ulang strategi pangan dan pertanian menuju diversifikasi, daya saing, dan inklusivitas.