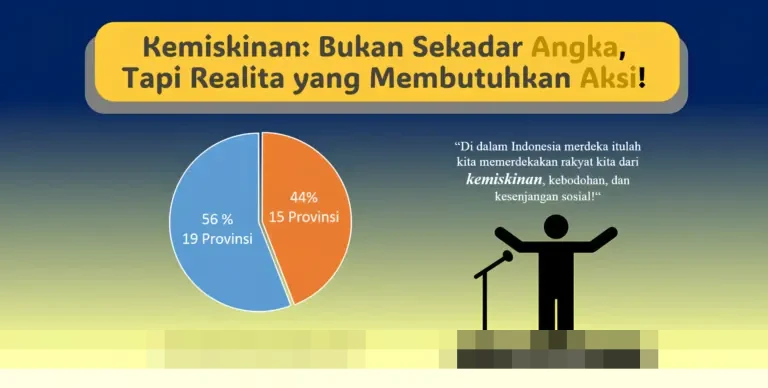Ketika grup musik legendaris Slank kembali melancarkan kritik terhadap kekuasaan melalui lagu “Republik Fufufafa”, publik tidak hanya menyimak liriknya. Lebih dari itu, muncul ingatan akan keheningan panjang yang menyelimuti band ini sebelum keberanian tersebut kembali bersuara. Kritik yang dilontarkan terhadap politik dinasti ini memicu pertanyaan mendasar tentang waktu dan posisi.
Tidak ada kritik yang sepenuhnya netral; setiap suara membawa sejarahnya sendiri. Slank, yang dulu dikenal sebagai penyanyi perlawanan dari “tribun rakyat”, pernah melangkah jauh hingga ke panggung kekuasaan. Menurut Antonio Gramsci, seniman dapat beralih peran menjadi intelektual organik yang menopang hegemoni kekuasaan melalui legitimasi kultural. Sementara itu, Jürgen Habermas menegaskan bahwa kritik publik kehilangan daya ketika jaraknya dengan kekuasaan menipis dan ruang otonomnya menghilang.
Ikuti artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Selama dua periode pemerintahan Joko Widodo, Slank tidak berada di luar orbit kekuasaan. Mereka tampil sebagai juru kampanye, menjadi simbol kultural pendukung rezim, bahkan sebagian personelnya masuk ke dalam struktur kekuasaan formal. Dalam kerangka Gramsci, posisi ini menempatkan Slank sebagai bagian dari proses pembentukan consent—persetujuan publik—yang menjadi fondasi utama hegemoni modern. Kekuasaan bekerja bukan semata melalui paksaan, melainkan melalui penerimaan sosial yang dibangun secara kultural.
Jarak Kritis dan Kehilangan Daya Korektif
Masalah muncul ketika aktor budaya telah sedekat itu dengan kekuasaan. Jarak kritis menjadi persoalan serius. Kritik yang datang dari posisi semacam ini hampir selalu dibaca dengan kecurigaan, bukan karena substansinya keliru, melainkan karena relasi kekuasaannya ambigu. Di sinilah relevansi Habermas menjadi penting: kritik publik hanya efektif ketika lahir dari ruang yang relatif otonom dari negara dan kepentingan kekuasaan. Tanpa jarak tersebut, kritik kehilangan fungsi korektifnya dan berisiko menjadi sekadar variasi wacana internal.
Persoalan utama lagu “Republik Fufufafa” bukan terletak pada apa yang dikritik, melainkan kapan kritik itu disuarakan. Kritik muncul bukan ketika kekuasaan berada pada fase konsolidasi paling kuat—saat pelemahan institusi demokrasi, pembungkaman kritik, dan konsentrasi kekuasaan berlangsung—melainkan ketika isu regenerasi dan pewarisan kekuasaan mulai memicu kegelisahan publik. Dalam konteks ini, kritik menjadi relatif aman secara politik.
Dari sudut pandang rational choice theory, aktor—termasuk aktor budaya—dipahami sebagai subjek yang mempertimbangkan biaya dan manfaat dari setiap tindakan. Kritik yang muncul ketika risiko politik rendah cenderung dibaca sebagai kritik yang telah melalui kalkulasi rasional. Keberanian semacam ini kerap dipersepsikan sebagai keberanian yang terlambat, bukan keberanian yang lahir dari taruhan moral.
Fenomena tersebut juga berkaitan dengan konsep co-optation dalam ilmu politik: proses ketika kekuasaan menyerap aktor-aktor kritis ke dalam sistem, meredam daya oposisi mereka, lalu menjadikan kritik sebagai ornamen demokrasi. Ketika aktor yang telah lama terkooptasi kembali bersuara kritis tanpa refleksi terbuka atas keterlibatan masa lalunya, kritik itu kehilangan daya subversifnya. Dari sisi etika politik, persoalan ini menyentuh wilayah virtue ethics. Legitimasi moral tidak ditentukan oleh satu tindakan simbolik, melainkan oleh konsistensi karakter dalam lintasan waktu. Keberanian yang tidak hadir ketika risiko paling tinggi akan selalu tampak timpang, betapapun relevan substansi kritik yang disampaikan.
Reputasi dan Akuntabilitas Demokratis
Dalam arena simbolik, sebagaimana dijelaskan Pierre Bourdieu, seniman juga mengelola modal simbolik berupa reputasi dan citra moral. Reputasi sebagai “suara perlawanan” adalah aset kultural yang bernilai tinggi. Namun aset ini hanya bertahan jika dijaga melalui koherensi antara karya, sikap politik, dan praktik hidup. Ketika koherensi itu melemah, publik akan membaca kritik bukan sebagai sikap etis, melainkan sebagai upaya mempertahankan citra lama.
Penting ditegaskan, kritik terhadap Slank bukanlah penolakan terhadap kritik atas politik dinasti. Justru sebaliknya, ini merupakan bagian dari akuntabilitas demokratis. Dalam demokrasi yang sehat, tidak hanya kekuasaan yang harus diuji, tetapi juga para pengkritiknya—terutama ketika mereka pernah menjadi bagian dari kekuasaan itu sendiri. Mureks mencatat bahwa kritik yang lahir tanpa refleksi atas keheningan masa lalu berisiko menjadi sekadar koreksi simbolik, bukan koreksi moral. Ketika kritik kehilangan dimensi moralnya, ia tak lagi berfungsi sebagai penyangga demokrasi, melainkan hanya sebagai gema yang terdengar setelah risiko menghilang.