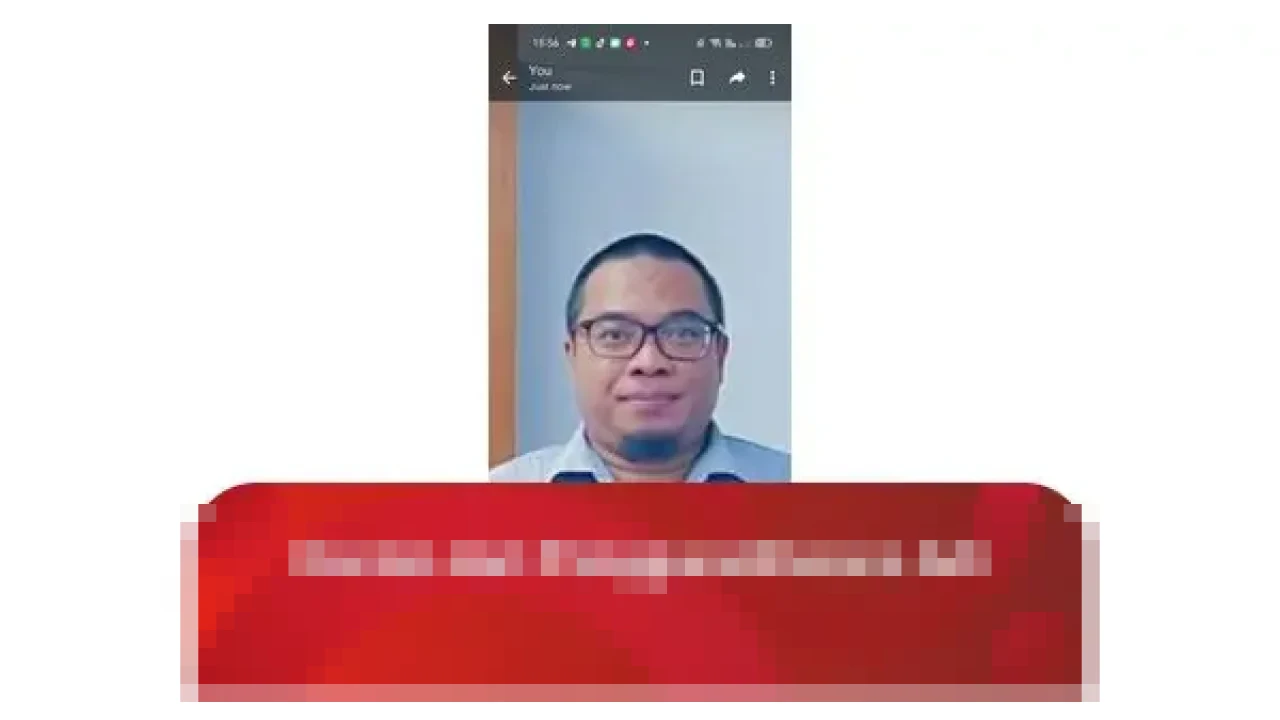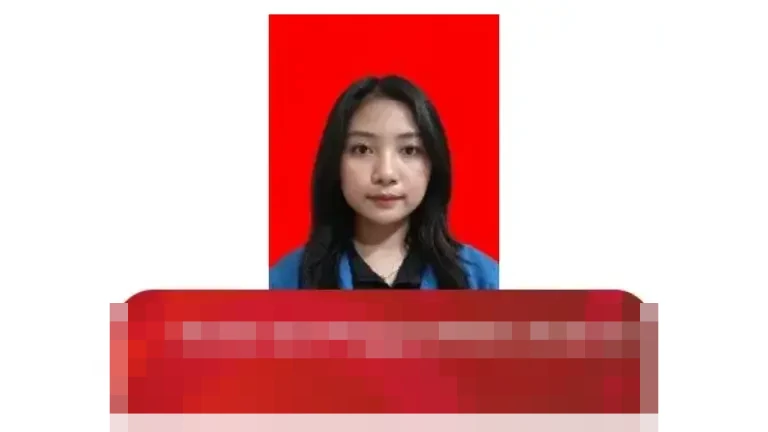Awal tahun 2026 dibuka dengan realitas yang kian sulit diabaikan: anomali cuaca ekstrem melanda berbagai wilayah Indonesia. Hujan lebat disertai kerusakan hutan yang menyebabkan banjir di Sumatera Utara dan Aceh pada Desember lalu, curah hujan yang tak menentu di berbagai kota, hingga cuaca panas ekstrem pada pertengahan hingga akhir Oktober 2025 di sebagian besar Nusa Tenggara, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta beberapa wilayah Papua—semuanya menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi isu masa depan, melainkan realitas hari ini.
Namun, di balik bencana ekologis ini, terdapat tantangan komunikasi yang tak kalah genting: bagaimana manusia memahami, membicarakan, dan bertindak terhadap perubahan iklim.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca melalui Mureks. mureks.co.id
Komunikasi Lingkungan sebagai Katalis Kesadaran
Dalam perspektif Ilmu Komunikasi, khususnya ranah Komunikasi Lingkungan, masalah perubahan iklim bukan hanya tentang sains atau kebijakan, melainkan juga tentang narasi, makna, dan cara pesan disampaikan. Komunikasi lingkungan berperan penting dalam membangun kesadaran publik, memengaruhi perilaku, serta menghubungkan pengetahuan ilmiah dengan tindakan sosial.
Sayangnya, di Indonesia maupun secara global, komunikasi tentang iklim masih sering terjebak dalam “jargon ilmiah” yang jauh dari pemahaman masyarakat luas. Profesor Robert Cox, salah satu pionir dalam kajian komunikasi lingkungan, dalam bukunya Environment Communication and The Public Sphere, pernah mengatakan, “Environmental communication is not simply about information transfer, but about shared meaning and collective action.” Komunikasi lingkungan, dengan kata lain, bukan sekadar menyampaikan data tentang suhu, emisi karbon, atau deforestasi, tetapi juga bagaimana pesan-pesan itu menggerakkan orang untuk peduli dan bertindak bersama.
Dampak Ekonomi dan Sosial di Bawah Bayang-Bayang Iklim
Dampak perubahan iklim tidak hanya menyentuh aspek ekologis, tetapi juga struktur sosial dan ekonomi. Kenaikan harga pangan, terganggunya rantai pasok akibat cuaca ekstrem, hingga meningkatnya migrasi ekologis adalah fenomena yang kini semakin sering muncul. Komunikasi lingkungan pada hakikatnya harus berfungsi sebagai bridging discourse—menjembatani pemahaman antara sains, kebijakan publik, dan kepentingan ekonomi masyarakat.
Sebagaimana dijelaskan oleh ahli komunikasi lingkungan Phaedra Pezzullo, komunikasi iklim yang efektif harus mampu “membingkai ulang isu lingkungan sebagai isu keadilan sosial.” Dalam konteks Indonesia, ini berarti mengangkat suara kelompok rentan—petani, nelayan, pekerja, dan masyarakat adat—yang sering menjadi korban pertama dari krisis iklim, namun suaranya jarang terdengar di ruang publik.
Tantangan Komunikasi Lingkungan di Era Modern
Kenyataan saat ini, narasi media arus utama masih kerap menyajikan isu ini secara sporadis dan reaktif—hanya ramai ketika bencana terjadi, seperti yang terjadi baru-baru ini di Sumatera Utara dan Aceh. Menurut Mureks, padahal komunikasi lingkungan menuntut konsistensi dan keberlanjutan pesan, agar publik membangun kesadaran ekologis yang mendalam, bukan sekadar simpati sesaat.
Dalam konteks Indonesia, tantangan lain adalah bagaimana pesan-pesan tentang krisis iklim disesuaikan dengan konteks budaya dan sosial lokal. Komunikasi yang efektif tidak bisa hanya meniru gaya kampanye global seperti “Net Zero” atau “Green Economy” tanpa menyentuh nilai-nilai lokal, seperti gotong royong, kearifan ekologi adat, dan solidaritas komunitas. Inilah mengapa pendekatan partisipatif dan narasi berbasis komunitas menjadi krusial.
Media Sosial: Ruang Ekologis Baru dan Tantangannya
Era digital menghadirkan peluang baru bagi komunikasi lingkungan, sekaligus tantangan baru pula. Di satu sisi, media sosial memungkinkan aktivisme digital tumbuh pesat: dari gerakan #SaveOurEarth, #BersihkanIndonesia, hingga kampanye lokal seperti #LestariPapua. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube kini menjadi sarana efektif menyebarkan pesan lingkungan secara visual dan emosional.
Namun, di sisi lain, media sosial juga menjadi ruang di mana disinformasi tentang iklim beredar luas. Banyak narasi yang meminimalkan atau menyangkal dampak perubahan iklim, kadang dibalut dengan teori konspirasi atau kepentingan ekonomi. Inilah tantangan komunikasi lingkungan era digital: bagaimana melawan climate denial dengan strategi komunikasi yang tidak menggurui, tetapi mengedukasi dan menginspirasi.
Dalam konteks ini, pendekatan komunikasi yang empatik dan naratif menjadi penting. Daripada sekadar menyampaikan data ilmiah yang kering, pesan harus diolah menjadi cerita yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya, menjelaskan bahwa kebiasaan membuang sampah sembarangan di sungai berkontribusi pada banjir yang kini semakin sering terjadi—atau bagaimana konsumsi energi rumah tangga memengaruhi emisi karbon secara global.
Dari Kesadaran Menuju Aksi Kolektif
Perubahan iklim adalah tantangan global yang membutuhkan tindakan lokal. Komunikasi lingkungan tidak boleh berhenti pada penyadaran, tetapi harus mendorong aksi kolektif. Pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat sipil perlu membangun ekosistem komunikasi yang inklusif: kampanye berkelanjutan, pendidikan publik, dan pelibatan komunitas dalam praktik hijau sehari-hari.
Dalam bahasa komunikasi lingkungan, ini disebut participatory environmental communication—pendekatan di mana masyarakat bukan hanya objek penerima pesan, melainkan subjek yang ikut merumuskan, menyampaikan, dan mengawal narasi lingkungan. Tanpa partisipasi publik, komunikasi iklim hanya akan menjadi retorika tanpa makna.
Kini, ketika tahun baru 2026 dibuka dengan cuaca ekstrem dan ketidakpastian ekologis, kita dihadapkan pada pilihan moral sekaligus komunikatif: apakah akan terus membiarkan krisis ini menjadi sekadar wacana, atau menjadikannya momentum untuk membangun budaya komunikasi lingkungan yang hidup dan berdaya? Krisis iklim sejatinya adalah juga krisis makna—dan komunikasi adalah kuncinya. Jika kita mampu mengubah cara kita berbicara tentang alam, mungkin kita juga akan mengubah cara kita memperlakukannya.