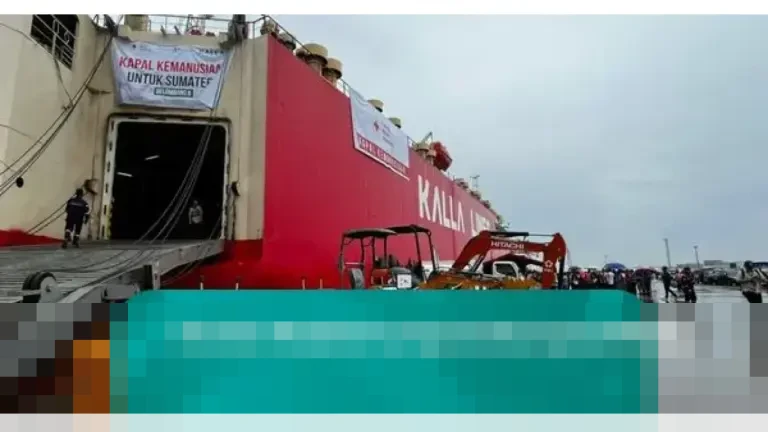Pengalaman diasingkan di lingkungan sendiri bukan sekadar tentang kesepian, melainkan luka mendalam akibat perasaan tidak diterima dan tidak dihargai secara berulang. Demikian salah satu kisah pilu yang didengarkan Septian Wahyu Rahmanto, Dosen Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, dari seorang kliennya di ruang konseling.
Klien tersebut kerap dipersepsikan sebagai beban dan dianggap kurang mampu oleh orang-orang di sekitarnya. Setiap kali ia berupaya membantu, respons yang diterimanya justru berupa penolakan atau ucapan yang meremehkan. Situasi ini, menurut Septian, secara perlahan membentuk pengalaman psikologis yang menyakitkan, yang kemudian dikenal sebagai luka psikologis atau trauma. Kehadirannya seolah tidak diakui dan kontribusinya tidak pernah dianggap berarti.
Mureks menghadirkan beragam artikel informatif untuk pembaca. mureks.co.id
Ketika Penolakan Berulang Menjadi Trauma
Pada akhirnya, klien menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan mengalah. Sikap mengalah ini dapat dipahami sebagai upaya klien untuk bersabar terhadap kondisi yang ia alami. Ia memilih tetap berada dalam lingkungan tersebut, menahan diri untuk tidak membalas perlakuan yang melukai, terutama karena ia merasa tidak memiliki daya atau ruang untuk melawan. Harga dirinya telah terluka, dan bertahan menjadi pilihan yang terasa paling mungkin saat itu.
Namun, seiring berjalannya waktu, posisi sebagai pihak yang terus mengalah justru menimbulkan kelelahan emosional. Meskipun secara lahiriah klien tampak baik-baik saja, pada kenyataannya ia menyimpan perasaan murung, sedih, dan kehilangan semangat. Hidup di tengah lingkungan yang minim penerimaan dan empati bukanlah pengalaman yang mudah untuk dijalani. Bagi klien ini, luka terdalam bukan semata-mata karena kehilangan pertemanan, melainkan kesadaran bahwa ia tidak pernah benar-benar diterima apa adanya.
Jalan Panjang Menuju Pemulihan
Kesadaran tersebut memang menyakitkan, tetapi sekaligus dapat menjadi titik awal untuk proses pemulihan. Septian Wahyu Rahmanto menjelaskan bahwa pemulihan bukanlah proses yang instan. Klien mungkin telah berusaha bersabar, menahan diri, dan bertahan sejauh yang ia mampu. Namun, memaafkan—terutama setelah luka harga diri—adalah proses yang memerlukan waktu. Tidak semua individu dapat langsung sampai pada tahap tersebut.
Mureks mencatat bahwa tantangan dalam memaafkan ini sejalan dengan ajaran agama, yang menggarisbawahi beratnya proses tersebut. Allah SWT berfirman:
وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ
“Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang utama (mulia).”
(QS. Asy-Syura: 43)
Kata ‘azm (عَزْمِ) mengandung makna kekuatan tekad, kesungguhan, dan keteguhan hati. Istilah ‘azmi al-umūr merujuk pada perkara-perkara yang dimuliakan dan diutamakan, yang tidak dapat dilakukan kecuali oleh mereka yang memiliki keteguhan dan kemauan yang kuat. Hal ini mengisyaratkan bahwa bersabar dan memaafkan adalah sesuatu yang berat dan menantang, sehingga balasannya pun berupa keutamaan dan kemuliaan.
Dengan demikian, wajar apabila seseorang yang memiliki luka psikologis membutuhkan waktu untuk mampu bersabar dan memaafkan. Proses tersebut tidak menandakan kelemahan, melainkan perjuangan batin yang nyata. Bagi sebagian orang, jalan ini terasa lebih ringan ketika Allah memberikan pertolongan dan ketika individu tersebut bersungguh-sungguh melawan dorongan emosionalnya serta memohon kekuatan kepada-Nya.
Memaafkan bukan berarti melupakan apa yang telah terjadi, juga tidak mengubah masa lalu. Namun, memaafkan dapat menjadi arah bagi jiwa untuk bergerak menuju ketenangan, agar seseorang dapat kembali menemukan dirinya sebagai pribadi yang utuh, pulih, dan mencapai kesehatan mental.