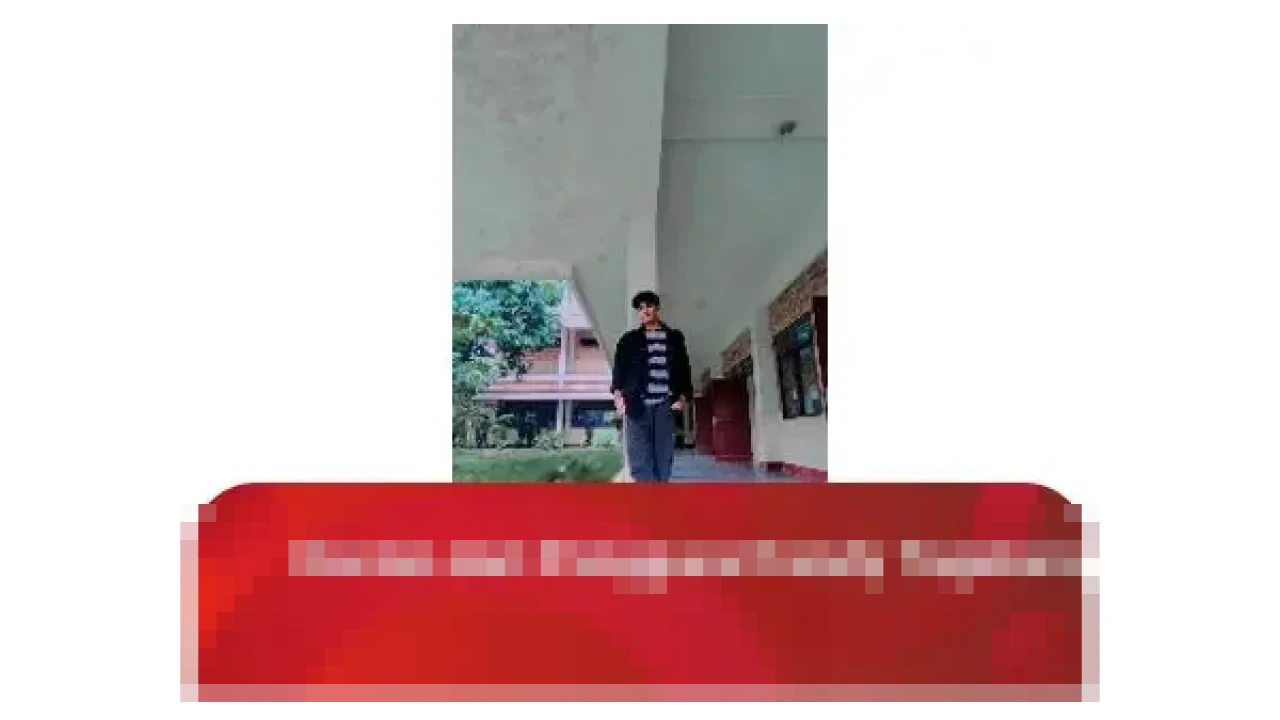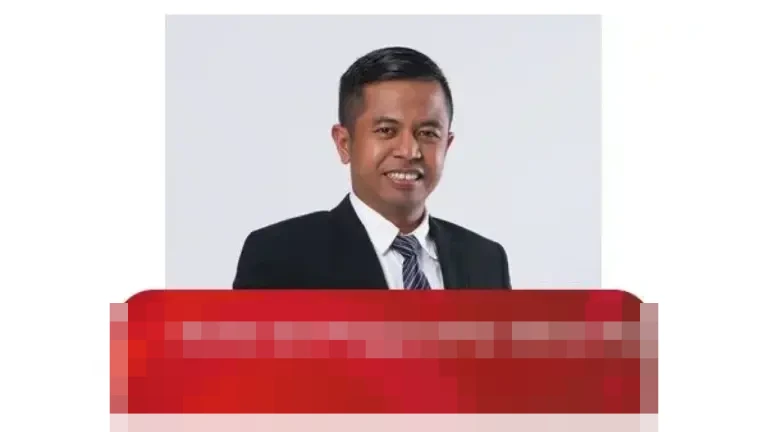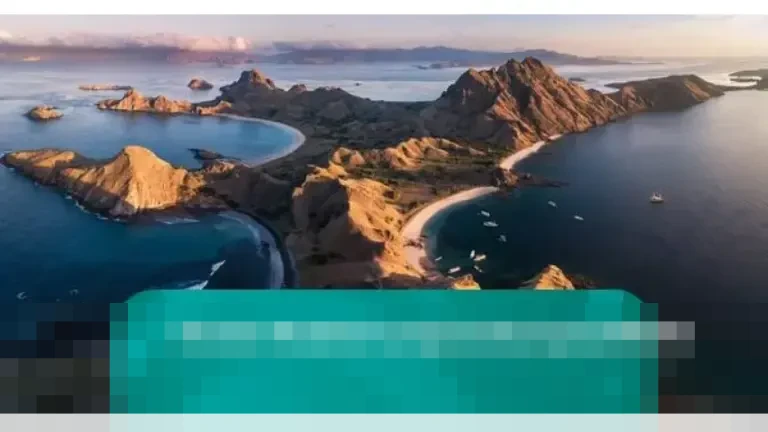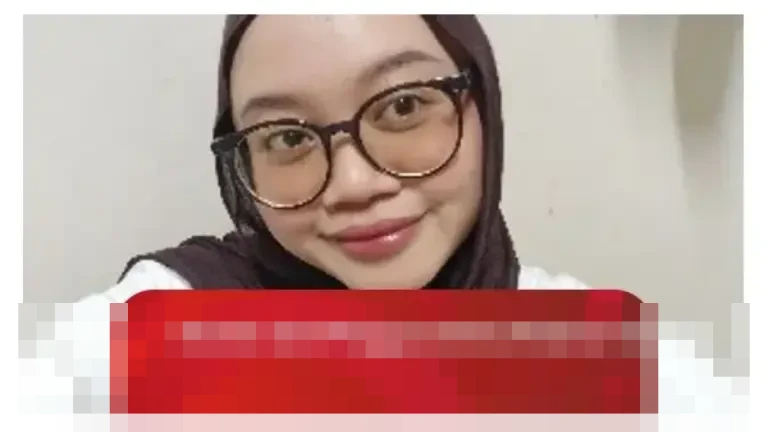Sistem pendidikan di Indonesia dinilai terlalu berorientasi pada pencapaian nilai akademis, sehingga mengesampingkan pengembangan nalar kritis siswa. Fenomena ini menyebabkan lulusan kerap menghadapi kesulitan dalam menerapkan pemikiran kritis di kehidupan nyata, memicu desakan untuk mengubah paradigma belajar secara fundamental.
Sejak bangku sekolah, keyakinan bahwa nilai adalah tolok ukur utama kecerdasan telah mengakar kuat. Rapor, peringkat kelas, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), hingga berbagai sertifikat menjadi validasi tunggal keberhasilan belajar. Kondisi ini secara bertahap telah mengubah esensi pendidikan menjadi sekadar perlombaan angka.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca melalui Mureks. mureks.co.id
Akibatnya, proses belajar lebih sering diarahkan untuk menghadapi ujian semata, bukan untuk mencapai pemahaman mendalam. Siswa cenderung menghafal jawaban daripada merumuskan pertanyaan kritis. Ironisnya, setelah ujian usai, banyak pengetahuan yang telah dihafalkan menguap begitu saja, seolah tugas belajar telah tuntas dengan perolehan nilai.
Lingkungan kelas pun kerap tidak kondusif untuk menumbuhkan nalar. Bertanya sering dianggap menghambat laju materi, sementara perbedaan pendapat terasa berisiko. Diskusi mendalam acapkali dipersingkat demi mengejar target kurikulum. Hal ini membentuk kebiasaan patuh pada kunci jawaban, bukan melatih kemandirian berpikir. Nalar hanya digunakan sebatas untuk memastikan nilai aman.
Kebiasaan ini, menurut pantauan Mureks, terbawa hingga ke kehidupan di luar lingkungan sekolah. Masyarakat cenderung mudah menerima informasi tanpa proses verifikasi kritis dan cepat percaya pada narasi yang terdengar meyakinkan. Kondisi ini tidak mengherankan jika kemudian hoaks mudah menyebar, perdebatan publik menjadi dangkal, dan diskusi seringkali berujung pada adu emosi alih-alih adu argumen berbasis data.
Pendidikan yang terlalu berfokus pada angka dan nilai berpotensi melahirkan generasi yang cakap secara administratif, namun rapuh dalam kemampuan nalar. Padahal, di dunia nyata, tantangan tidak datang dalam bentuk soal pilihan ganda. Kehidupan menuntut kemampuan berpikir kritis, membaca konteks secara komprehensif, serta mengambil keputusan di tengah ketidakpastian—kompetensi yang jarang diasah secara mendalam di bangku sekolah.
Ironisnya, kegagalan dalam menumbuhkan nalar ini seringkali dibebankan kepada individu, dengan anggapan siswa kurang berusaha atau guru kurang kreatif. Padahal, akar masalahnya bersifat sistemik. Kurikulum yang padat, sistem evaluasi yang sangat berbasis angka, serta tekanan tinggi untuk kelulusan, secara kolektif mempersempit ruang bagi pengembangan pemikiran kritis. Seluruh elemen terlibat dalam logika ‘kejar target’ ini.
Orang tua juga tidak luput dari tekanan serupa. Nilai tinggi seringkali dianggap sebagai jaminan masa depan yang cerah. Ketika anak menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi, banyak bertanya, atau memilih jalur yang berbeda, kekhawatiran seringkali muncul. Rasa ingin tahu yang seharusnya dipelihara justru kerap dipangkas demi menciptakan rasa aman dan kepatuhan pada sistem.
Bukan berarti nilai akademis tidak penting. Angka tetap berfungsi sebagai salah satu alat ukur kemajuan. Namun, ketika nilai menjadi tujuan utama, esensi pendidikan akan kehilangan rohnya. Pendidikan seharusnya berorientasi pada penumbuhan nalar, bukan sekadar melatih kepatuhan. Ini berarti membiasakan siswa untuk bertanya, bukan hanya menjawab; serta memberi ruang untuk berbuat salah, bukan hanya menuntut kebenaran mutlak.
Oleh karena itu, jika pendidikan ingin benar-benar mempersiapkan generasi untuk menghadapi masa depan yang kompleks, orientasinya perlu dirombak. Pergeseran fokus dari ‘berapa nilaimu’ menjadi ‘apa yang kamu pahami’ dan dari mengejar peringkat menjadi melatih cara berpikir, adalah sebuah keniscayaan.
Sebab, nilai mungkin hanya membantu seseorang lulus dari ujian formal. Namun, nalar yang terlatih dan terasah adalah kunci utama untuk bertahan serta berpikir jernih dalam menghadapi kompleksitas kehidupan yang terus berubah.