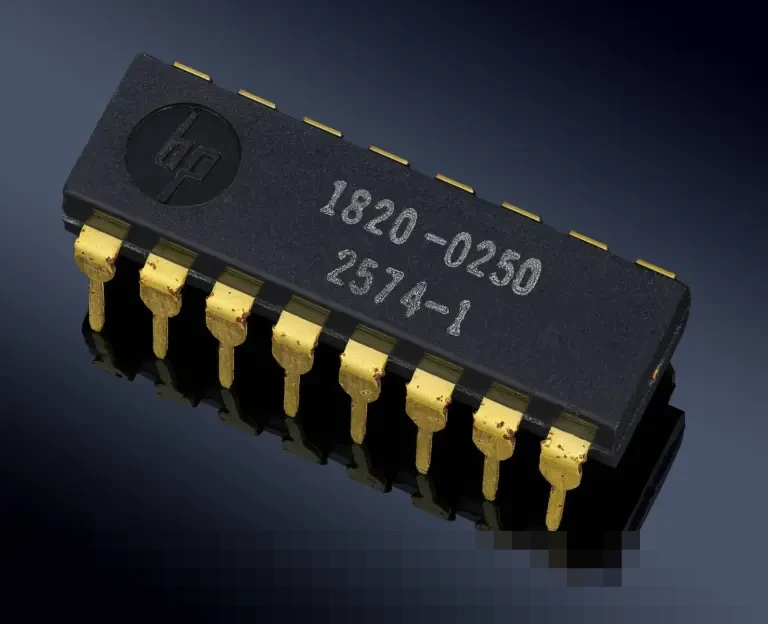Ruang-ruang kelas di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Papan tulis dan kapur, yang dulunya menjadi ikon pembelajaran, kini berbagi tempat dengan layar digital, aplikasi interaktif, dan tombol ‘klik’. Pergeseran ini menuntut guru untuk lebih adaptif, inovatif, dan, ironisnya, diminta untuk tidak terlalu banyak berbicara.
Narasi pendidikan modern kerap menganggap ceramah sebagai kebiasaan lama yang harus ditinggalkan. Konon, semakin minim guru bertutur, semakin modern dan efektiflah proses pembelajaran. Paradigma ini menyederhanakan masalah pendidikan: jika murid bosan, metodenya yang keliru; jika hasil belajar rendah, guru dianggap kurang kreatif. Solusi yang ditawarkan pun seragam: ganti metode, perbanyak aplikasi, dan tingkatkan interaksi digital, seolah persoalan pendidikan dapat diselesaikan layaknya pembaruan perangkat lunak.
Liputan informatif lainnya tersedia di Mureks. mureks.co.id
Namun, di tengah gegap gempita digitalisasi sekolah, catatan Mureks menunjukkan data PISA 2022 yang kurang menggembirakan. Kemampuan literasi dan numerasi peserta didik Indonesia masih tertinggal dari rata-rata OECD. Kehadiran teknologi belum serta-merta mendongkrak mutu pendidikan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan krusial: mungkin yang kurang bukan sinyal internet, melainkan ‘sinyal makna’ dalam proses belajar.
Ceramah, dalam banyak diskusi, sering diposisikan sebagai biang keladi kebosanan, monolog, bahkan kemalasan pedagogik. Padahal, ceramah yang hidup adalah sebuah seni bertutur. Ia merupakan kemampuan merangkai pengetahuan dengan pengalaman, menyelipkan nilai di sela-sela konsep, dan memberikan arah di tengah kegamangan remaja. Sayangnya, seni semacam ini sulit diukur dengan indikator ‘klik’ dan tidak dapat diunggah sebagai laporan inovasi. Dalam sistem yang terobsesi pada pengukuran, hal yang tak terukur sering kali dianggap tidak penting, bahkan dicurigai tidak produktif.
Di era banjir informasi ini, murid dapat menemukan penjelasan apa pun dalam hitungan detik melalui video singkat yang menjanjikan pemahaman instan. Namun, di tengah limpahan data tersebut, pertanyaan ‘mengapa’ sering kali tercecer. Banyak murid tahu jawabannya, tetapi tidak yakin apa artinya. Mereka terbiasa memilih jawaban, bukan memaknai persoalan. Di sinilah suara guru seharusnya hadir, bukan sebagai mesin informasi yang kalah cepat, melainkan sebagai penunjuk makna. Ironisnya, suara ini kerap dianggap gangguan dalam kelas yang terlalu sibuk mengejar target metode dan laporan administratif.
Keberhasilan belajar kini lebih sering diukur dari keterisian formulir, unggahan tugas, dan kelengkapan instrumen penilaian. Proses menjadi sekunder, refleksi dianggap memperlambat, dan percakapan bermakna dipangkas demi efisiensi. Pendidikan tampak rapi di atas kertas, tetapi sering terasa kosong dalam pengalaman. Dalam situasi ini, ceramah yang hidup justru terasa asing karena menuntut waktu, perhatian, dan keberanian untuk tidak selalu serba instan.
Kritik terhadap ceramah yang kaku, panjang, dan menutup dialog memang layak ditinggalkan. Namun, menjadikan ceramah sebagai musuh bersama adalah bentuk kemalasan berpikir yang lain. Kita terlalu sibuk memilih antara ceramah atau klik, seolah pendidikan adalah pertandingan metode. Padahal, yang seharusnya dipertanyakan adalah: apa yang ditinggalkan guru pada murid setelah kelas usai? Apakah hanya jejak tugas yang dikumpulkan, atau nilai yang diam-diam membentuk cara mereka melihat dunia?
Berbagai survei pendidikan menunjukkan fakta psikologis yang jarang disorot: murid lebih mudah mengingat sikap guru daripada isi pelajaran. Nada bicara, cara menegur, dan keberanian bersikap adil sering melekat lebih lama daripada rumus atau definisi. Nilai tidak tumbuh dari menu pilihan ganda, melainkan dari contoh yang diulang. Dan contoh paling dekat di sekolah adalah guru itu sendiri, bukan aplikasi, bukan modul, apalagi template pembelajaran yang seragam.
Di titik inilah wajah pendidikan kita terasa pahit. Kita berharap sekolah membentuk karakter, tetapi alergi pada proses yang memungkinkan karakter itu ditanamkan. Kita ingin murid beretika, kritis, dan empatik, tetapi mencurigai guru yang berbicara dengan hati. Kita memuja istilah “student-centered learning”, tetapi gelisah jika guru terlalu tampak sebagai manusia yang punya suara, pendirian, dan nilai.
Menatap tahun 2026, pengharapan pendidikan seharusnya lebih dewasa. Ini bukan soal kembali ke romantisme masa lalu, tetapi juga tidak mabuk teknologi. Guru perlu diberi ruang untuk berbicara, bukan sekadar mengklik. Teknologi perlu ditempatkan sebagai alat, bukan sebagai tujuan moral baru. Dan kelas perlu kembali menjadi ruang perjumpaan, bukan sekadar ruang transaksi informasi. Pergeseran dari ceramah ke klik seharusnya bukan soal perpindahan ekstrem, melainkan keseimbangan. Karena pada akhirnya, murid mungkin lupa aplikasi apa yang dipakai, tetapi mereka akan selalu ingat siapa guru yang pernah berbicara kepada mereka—bukan hanya dengan suara, melainkan juga dengan hati.