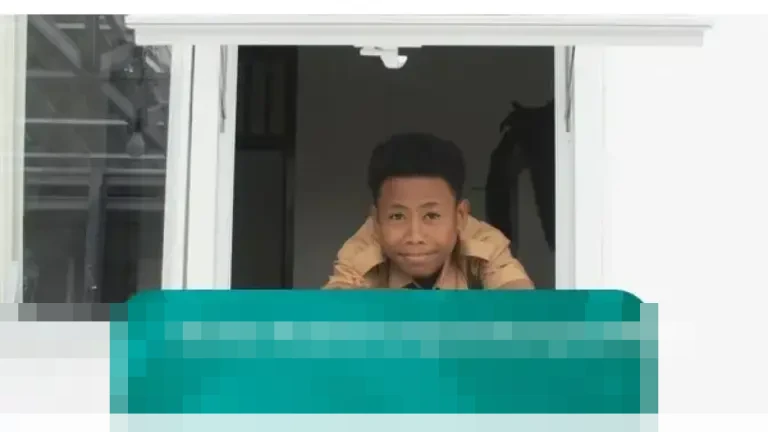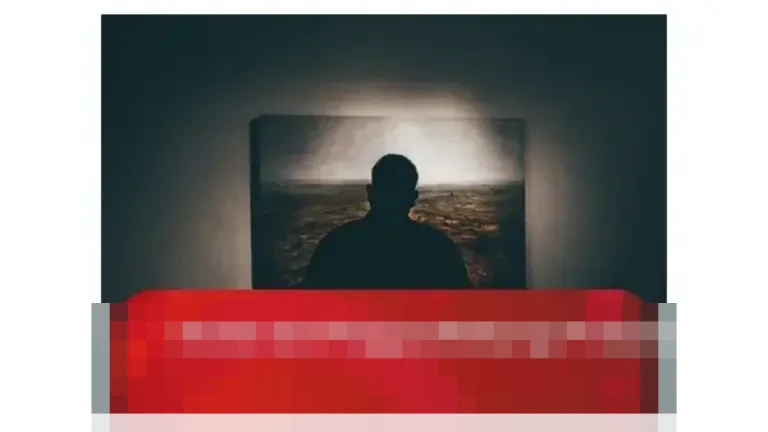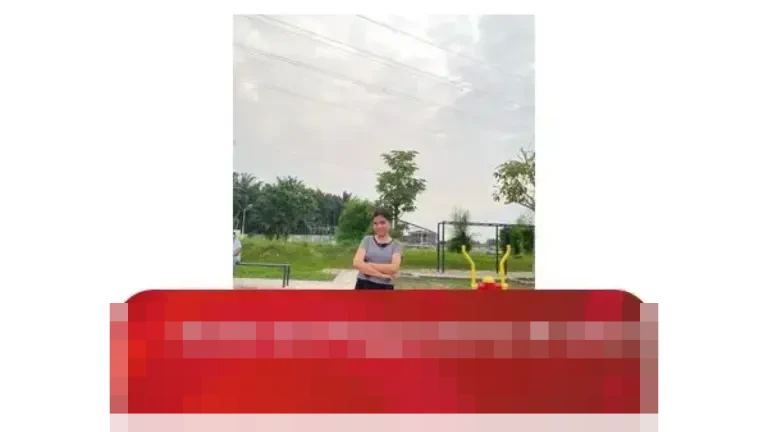Fenomena gig economy atau ekonomi berbasis aplikasi terus berkembang pesat secara global, termasuk di Indonesia. Model kerja yang menawarkan fleksibilitas waktu dan peluang pendapatan harian ini, sejalan dengan ekspansi kapitalisme platform yang diulas oleh Srnicek (2017), telah mengubah hakikat pekerjaan dan cara jutaan orang mencari nafkah.
Di Indonesia, aplikasi digital seperti Gojek, Grab, Maxim, ShopeeFood, hingga berbagai marketplace dan platform freelance kini menjadi tumpuan hidup bagi banyak individu. Daya tarik utama terletak pada fleksibilitas yang ditawarkan, memungkinkan siapa pun untuk bekerja kapan saja. Namun, di balik janji kebebasan ini, muncul persoalan serius terkait status hukum, perlindungan sosial, dan masa depan para pekerja gig.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Pergeseran Definisi Pekerjaan dan Kesenjangan Perlindungan
Perubahan ini sangat kontras dengan struktur kerja di era sebelum digital. Dahulu, pekerjaan didefinisikan melalui hubungan kerja formal yang mencakup kontrak, jam kerja jelas, upah minimum, hak cuti, jaminan sosial, dan perlindungan keselamatan kerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Identitas jabatan pun dipetakan secara sistematis melalui Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan ISCO, untuk mengelompokkan pekerjaan berdasarkan keterampilan dan fungsi.
Namun, realitas hari ini telah berubah drastis. Gig economy membuat batas pekerjaan menjadi cair. Sopir ojek digital kini disebut “mitra”, bukan pekerja. Kurir aplikasi didefinisikan sebagai “pekerja mandiri”. Bahkan, banyak jenis pekerjaan digital belum tercatat dalam KBJI, menyebabkan posisi hukum mereka kabur dan sulit diakui secara kelembagaan.
Sebelumnya, sopir angkutan umum, buruh pabrik, dan guru sekolah berada dalam sistem kerja formal dengan perlindungan negara. Kini, pekerja platform hanya mengandalkan rating aplikasi, insentif harian, dan algoritma yang menentukan hidup mereka, sesuai kajian manajemen algoritmik oleh Meijerink & Bondarouk (2023). Transformasi ini bukan sekadar perubahan alat kerja, melainkan juga perubahan mendasar atas definisi pekerjaan itu sendiri.
Tekanan Ekonomi dan Dominasi Algoritma
Alasan banyak orang masuk ke gig economy beragam, mulai dari kesulitan mengakses pasar kerja formal, tekanan ekonomi, tingginya biaya hidup, hingga kebutuhan akan pekerjaan cepat berpendapatan harian. Ironisnya, banyak pekerja gig justru bekerja 10 hingga 14 jam per hari, seperti diuraikan dalam laporan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengenai work platform.
Survei Universitas Indonesia pada 2023 memperkirakan lebih dari 7,2 juta orang bekerja di sektor gig di Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa gig economy tidak lagi sekadar ruang kerja alternatif, melainkan telah menjadi fondasi penting ekonomi digital nasional.
Meskipun demikian, status pekerja masih didefinisikan sebagai “mitra”, bukan pekerja. Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki hak atas upah minimum, perlindungan keselamatan kerja, jaminan sosial, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Banyak pihak masih menyamakan gig worker dengan pekerja informal, padahal relasi kerjanya berbeda: seluruh proses kerja dimediasi oleh algoritma.
Aplikasi menentukan pesanan, tarif, rute penugasan, hingga penalti otomatis, sebagaimana ditekankan Pilatti et al. (2024). Bahkan, platform dapat memutus akun pekerja tanpa mekanisme pembelaan yang adil.
Langkah Negara Lain dan Harapan untuk Indonesia
Negara sebenarnya telah berupaya hadir melalui skema BPJS Ketenagakerjaan bagi pengemudi ojek online. Namun, karena sifatnya sukarela, beban iuran justru ditanggung pekerja sendiri, bukan perusahaan digital, seperti diungkap Wibowo (2023). Akibatnya, pekerja gig tidak memiliki hak cuti, Tunjangan Hari Raya (THR), libur resmi, dan jam kerja terbatas, sebagaimana buruh dalam rezim Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Sementara itu, di negara lain, paradigma hukum mulai bergeser. Putusan Mahkamah Agung Inggris tahun 2021 dalam kasus Uber BV v Aslam, misalnya, menetapkan pengemudi Uber sebagai pekerja resmi yang berhak atas upah minimum dan jaminan sosial. Spanyol juga mewajibkan perusahaan mendaftarkan pekerja gig sebagai karyawan, dan Amerika Serikat melalui model AB5 mendorong perlindungan serupa, menurut Rogers (2021).
Indonesia masih tertinggal dalam reformasi ini. Selama status pekerja gig terus ditempatkan dalam kategori “mitra”, posisi tawar mereka akan tetap lemah. Perusahaan digital akan terus mengatur tarif, menentukan pendapatan, hingga memutus akses kerja. Pekerja tampak bebas, tetapi pada kenyataannya hidup mereka dikendalikan oleh algoritma yang tidak transparan.
Ekonomi digital memang menjadi masa depan kerja nasional. Namun, masa depan itu tidak boleh dibangun di atas kerentanan tenaga kerja. Negara perlu menetapkan standar upah minimum bagi pekerja platform, mewajibkan jaminan sosial, membuka ruang serikat, menjamin keadilan algoritmik, dan menyediakan mekanisme keberatan terhadap pemutusan akun sepihak.
Mereka yang bekerja mengantar penumpang di tengah panas, menjelajahi kota membawa kiriman, dan menopang kenyamanan digital kita setiap hari bukan hanya “mitra aplikasi”, melainkan juga pekerja Indonesia—manusia yang berhak atas martabat, jaminan keamanan, dan perlindungan hukum.