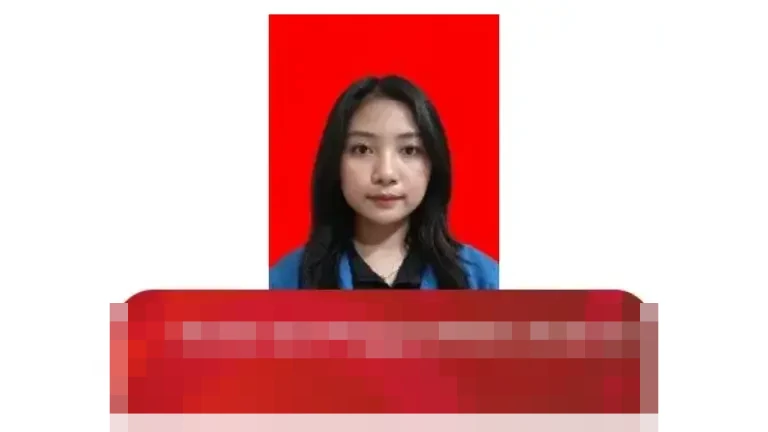Setelah berakhirnya Perang Dingin, Samuel Huntington dalam bukunya The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order yang terbit tahun 1996, menggambarkan masa depan dunia. Ia berpendapat, “Benturan Peradaban tidak lagi melibatkan Barat (Amerika Serikat) dan Timur (Uni Soviet) namun melibatkan Barat dan berbagai peradaban non-Barat (Islam, Konfusian, Hindu dsb).”
Karya Huntington ini muncul sebagai kritik terhadap pandangan Francis Fukuyama dalam The End of History and the Last Man. Fukuyama menyimpulkan bahwa keruntuhan Uni Soviet menandai kemenangan peradaban Barat, dengan demokrasi liberal dan kapitalisme pasar bebas sebagai puncak evolusi ideologis manusia. Namun, pandangan Fukuyama banyak menuai kritik karena mengabaikan kekuatan baru seperti Tiongkok dan berbagai konflik budaya di wilayah Selatan.
Baca artikel informatif lainnya di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Islam sebagai Titik Panas Benturan Peradaban
Huntington awalnya menulis artikel berjudul “The Clash of Civilizations?” di jurnal Foreign Affairs pada 1993, yang kemudian dikembangkan menjadi buku. Meski membahas berbagai peradaban, Huntington secara khusus menyoroti Islam sebagai masalah utama bagi peradaban Barat di masa depan. Ia menyebutnya sebagai “Islam has bloody borders” – sebuah generalisasi yang dinilai bias dan mengabaikan faktor kolonialisme, intervensi Barat, serta kompleksitas konflik internal di dunia Islam.
Tesis Huntington, yang menggambarkan benturan peradaban sebagai sesuatu yang niscaya, secara langsung atau tidak, telah memengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Pasca tragedi 11 September 2001, tesis ini sering digunakan untuk membenarkan kebijakan luar negeri agresif Barat.
Salah satu contoh paling nyata adalah invasi Amerika Serikat ke Irak pada Maret 2003. Presiden George W. Bush melancarkan operasi militer dengan dalih melucuti Senjata Pemusnah Massal (WMDs) dan melabeli tindakannya sebagai “Perang Melawan Teror”. Ia mengaitkan rezim Saddam Hussein dengan terorisme global, meskipun belakangan diketahui Irak tidak terlibat langsung dalam tragedi 9/11 dan tidak pernah terbukti memiliki WMDs.
Amerika Serikat akhirnya meninggalkan Irak pada 2011 dalam kondisi porak-poranda, menyisakan residu konflik lokal berbasis sektarian antara komunitas Sunni dan Syiah yang masih berlangsung hingga kini. Mureks mencatat bahwa tesis Huntington, alih-alih sekadar menjelaskan realitas, justru membentuk realitas politik itu sendiri, seolah merealisasikan “nubuat akademik” yang lebih bernada konfrontatif.
Negara sebagai Aktor Utama, Bukan Peradaban
Meskipun Huntington menekankan peradaban sebagai penyebab utama konflik masa depan, dalam praktiknya, konflik pasca-Perang Dingin lebih banyak melibatkan antarnegara. Teori Huntington kurang konsisten karena negara-bangsa tetap menjadi aktor utama, bukan peradaban yang tidak memiliki struktur politik tunggal untuk bertindak kolektif.
Beberapa konflik besar di abad ke-21, seperti invasi Amerika Serikat ke Irak, Arab Springs, eskalasi fraksi Houthi di Yaman, Perang Palestina-Israel, ISIS di Irak dan Suriah, genosida Rohingya, aneksasi Krimea oleh Rusia, invasi Rusia terhadap Ukraina, persekusi minoritas Muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok, serta konflik di Sudan dan Afrika, semuanya melibatkan negara terhadap negara atau negara terhadap organisasi.
Klaim Osama bin Laden pada tragedi 9/11, misalnya, mewakili Al-Qaeda sebagai organisasi teroris, bukan Islam sebagai perwakilan peradaban Muslim internasional. Banyak kelompok Islam ortodoks tidak membenarkan tindakan Osama bin Laden, menilai ideologinya sebagai penyimpangan ekstrem dari prinsip-prinsip Islam yang damai.
Media dan Konstruksi Stereotip Muslim
Caroline Mala Corbin, Profesor Hukum University of Miami School of Law, dalam tulisannya “Terrorist Are Always Muslim but Never White: At the Intersection of Critical Race Theory and Propaganda”, mengkritik bias media terhadap Muslim. Corbin menyebutkan narasi keliru yang beredar di televisi, film, dan pemberitaan, yang kemudian tercermin dalam kebijakan pemerintah.
Narasi pertama adalah “teroris selalu dikonstruksikan sebagai Muslim (yang berkulit coklat).” Narasi kedua ialah “orang kulit putih tidak pernah menjadi teroris.” Narasi-narasi ini memengaruhi gambaran publik Amerika ketika mendengar kata ‘teroris’. Stereotip “teroris adalah Muslim” dan “orang kulit putih tidak pernah dilabeli sebagai teroris” (white privilege) terus diindoktrinasi melalui media.
Narasi keliru ini berperan penting dalam propaganda pemerintah, yang bergantung pada ideologi rasis dan mitos kepolosan serta superioritas orang kulit putih. Corbin menegaskan bahwa kedua narasi tersebut justru merusak keamanan, bukan meningkatkannya.
Kritikan Corbin selaras dengan Mahmood Mamdani dalam bukunya Good Muslim Bad Muslim: America, the Cold War, and the Roots of Terror. Tesis utama Mamdani menyebutkan, “Masalah utama bukan Islam sebagai agama, melainkan cara kekuasaan global-terutama Amerika Serikat-mengkonstruksi Muslim secara politik.” Mamdani mendekonstruksi bagaimana wacana Barat (media, negara, dan akademik) mendikotomi Muslim menjadi dua kategori: Good Muslim dan Bad Muslim.
Good Muslim digambarkan sebagai kelompok moderat, sekuler, pro-Barat, dan tidak mempolitisasi Islam. Sementara itu, Bad Muslim adalah kelompok radikal, anti-Barat, dan dilabeli sebagai teroris. Penilaian ini tidak didasarkan pada karakter moral, melainkan pada kepatuhan politik terhadap kepentingan Amerika. Dikotomi ini diciptakan sebagai alat politik dan keamanan, bukan analisis ilmiah, yang secara tidak langsung membongkar analisis wacana ala Huntington dan kebijakan publik Amerika Serikat.
Siapa Produsen ‘Bad Muslim’?
Jika teroris adalah Bad Muslim dalam terminologi Mamdani, pertanyaan selanjutnya adalah: siapa yang memproduksi teroris tersebut? Apakah ia terlahir secara organik dari Islam itu sendiri, atau merupakan warisan konflik masa lalu?
Berbeda dengan Huntington yang melihat Islam sebagai entitas konflik di masa depan, Mamdani menelusuri sejarah di mana bibit radikalisme disemai. Ia berargumen bahwa Islam radikal yang disaksikan dunia hari ini bukanlah fenomena Abad Pertengahan, melainkan hasil intervensi Amerika Serikat selama Perang Dingin. Amerika secara terang-terangan mendukung, mendanai, dan melatih kelompok ekstremis seperti Mujahidin di Afghanistan untuk melawan Uni Soviet.
Bantuan tersebut murni karena konflik kepentingan selama Perang Dingin, bukan kepedulian terhadap dunia Muslim. Proyek CIA yang aktif mendukung gerakan-gerakan ini, di kemudian hari, justru menjadi senjata yang melawan balik Amerika sendiri. Saat Perang Dingin usai dan tragedi 9/11 menjadi isu global, media membingkai narasi untuk melawan teror, mendorong legislasi keamanan, dan memberitakan intervensi militer, sehingga Islam berubah menjadi agama yang dilabeli sebagai antitesis peradaban Barat. Ini persis seperti “nubuat” Huntington yang kemudian dibuktikan oleh praktik politik dan media.
Perbedaan mendasar antara tesis Huntington dan Mamdani ialah: Huntington menganggap konflik (di masa depan) tak terelakkan, sedangkan Mamdani menunjukkan konflik diciptakan secara historis dan politis. Dengan kata lain, Huntington berkata “Islam berbenturan dengan (peradaban) Barat” dan Mamdani menjawab bahwa “Justru (peradaban) Barat yang menciptakan Muslim sebagai musuh.”
Relevansi Hari Ini dan Amnesia Kolektif
Melihat kebijakan publik Amerika Serikat selama seperempat abad terakhir, termasuk wacana kebijakan Donald Trump yang hendak mendeportasi mahasiswa internasional pro-Palestina, menunjukkan bahwa Islamofobia masih dan akan terus berlanjut. Pantauan Mureks menunjukkan bahwa Islamofobia bukan sekadar residu masa lalu, melainkan instrumen politik aktif.
Bagaimana media dan otoritas politik membingkai wacana terhadap Muslim telah menciptakan reduksionisme sejarah yang berbahaya. Islam kini dipahami hanya melalui lensa keamanan, sebuah proses sistemik yang membuat Islam menjadi agama yang paling disalahpahami, bahkan oleh penganutnya sendiri.
Penyempitan sudut pandang ini melahirkan amnesia kolektif. Fiksasi dunia terhadap dikotomi “Good Muslim vs Bad Muslim” telah menihilkan narasi besar tentang Islam sebagai peradaban intelektual. Akibatnya, sejarah seolah mengalami lompatan janggal: menghapus rentang abad ke-8 hingga ke-13 Masehi dari ingatan manusia, lalu meloncat langsung ke abad ke-20 dengan narasi konflik yang pekat.
Padahal, pada periode itulah Islam berfungsi sebagai jembatan emas yang menyelamatkan warisan intelektual Yunani dan menyuplainya bagi kebangkitan Renaisans di Eropa. Dengan mereduksi Islam hanya sebagai ancaman geopolitik, dunia tidak hanya kehilangan pemahaman tentang sebuah agama, tetapi juga kehilangan pengakuan atas fondasi ilmu pengetahuan modern. Melawan narasi “Benturan Peradaban” Huntington, pada akhirnya, bukan hanya soal membela identitas, melainkan soal memulihkan kebenaran sejarah yang telah lama dikaburkan.