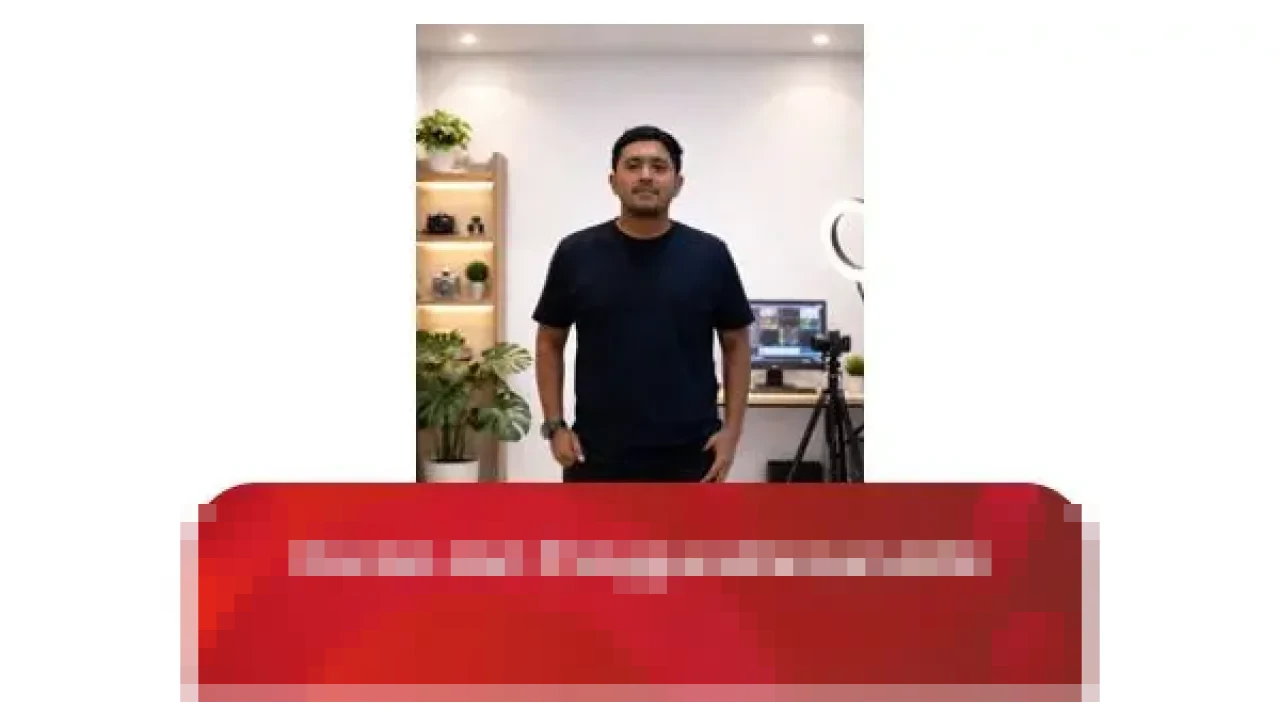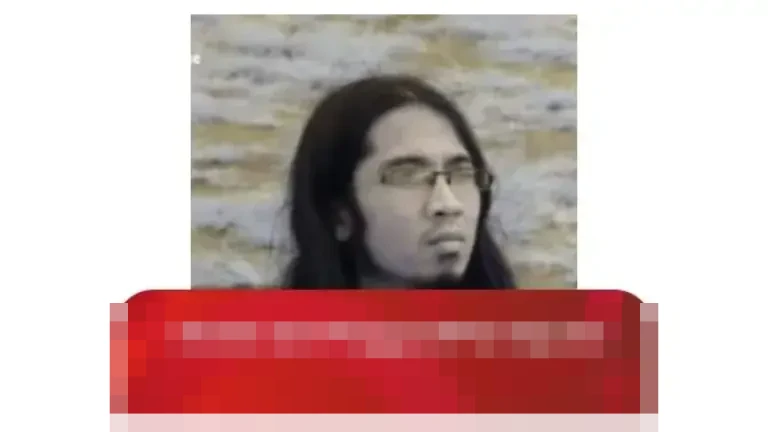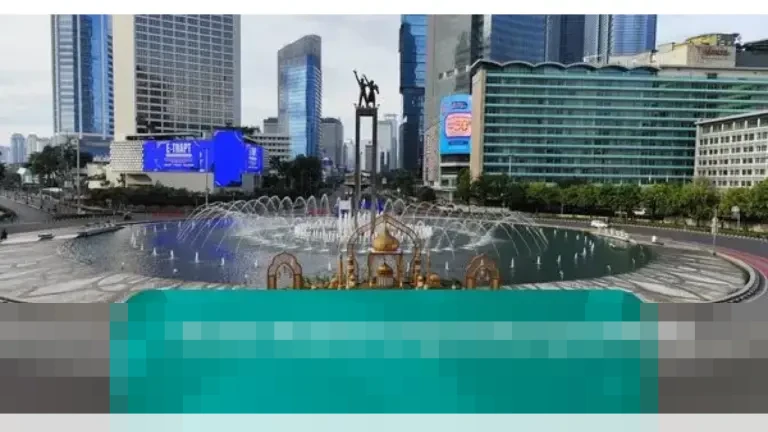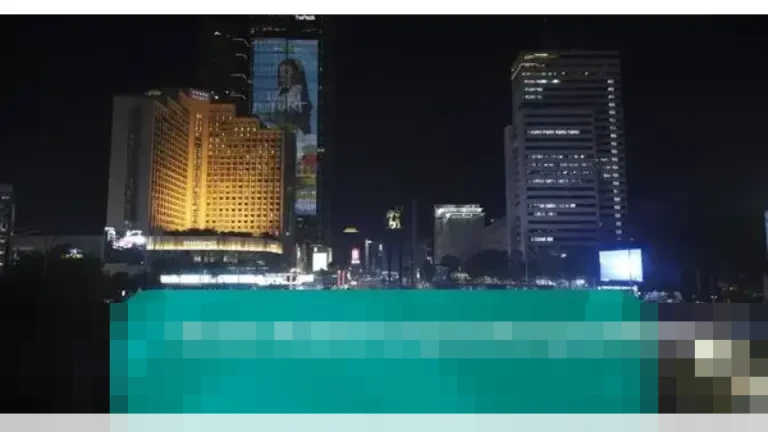Pagi itu, suasana Natal menyelimuti Gereja Katolik Hati Kudus di Banda Aceh. Saya tiba sangat awal, mendapati pintu gereja masih tertutup rapat, seolah menanti fajar yang lebih terang untuk memulai perayaan. Saya yakin seseorang sudah bangun di dalam, namun pintu gereja masih enggan terbuka. Saya berdiri di depan pintu, menunggu seseorang membukakannya dari dalam.
Seorang lelaki muda berbadan gempal, bermata sipit, berambut cepak, dan sedikit bungkuk akhirnya membuka pintu. Di lehernya terselip sebuah salib kecil. Dari penampilannya, ia tampak seperti Generasi Z, mengenakan kaos polos putih dan celana panjang kargo hitam.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
“Saya ingin bertemu Hironimus Radjutuga,” kata saya, memperkenalkan diri sebagai Ahmad dari kantor redaksi. Lelaki muda itu membalas, “Saya, Kevin Leonardo.” Ia kemudian mempersilakan saya menunggu seraya memanggil Hironimus yang sedang sibuk menghias bunga dan menata gereja di dalam.
Dari ambang pintu yang terbuka, pandangan saya menembus ke dalam gereja. Patung Tuhan Yesus tergantung di dinding, menyambut dari kejauhan. Ruangan yang memanjang dengan kursi jemaat tersusun rapi itu tak banyak cahaya, hanya satu-dua lampu kuning redup menyala.
Tak lama, seorang lelaki tua berambut putih, berkacamata, bertubuh ceking, dan sedikit bungkuk berjalan perlahan ke arah saya. Ia mengenakan kaos dengan sablon yang telah memudar dan celana kain cokelat yang warnanya hampir pudar pula. Setelah memperhatikan saya sejenak, ia melemparkan senyum.
“Hironimus Radjutuga,” ucapnya sambil menjulurkan tangan. Saya pun menjelaskan maksud kedatangan saya untuk mewawancarainya. Hironimus menatap saya sebentar, lalu mengajak saya ke halaman depan gereja, di bawah sebuah tenda bertiang.
“Ini pos pengamanan,” tunjuknya. “Setiap Natal selalu ada pos pengamanan di sini,” lanjutnya. Saya memandang sekeliling, melihat sebuah meja dan beberapa kursi yang mungkin akan menjadi tempat petugas berjaga nanti. Dari halaman gereja, menara dan kubah Masjid Raya tampak jelas, hanya terpisah oleh sebuah jembatan dengan jarak sekitar seratus meter.
Kami duduk berhadapan. Saya menghadap pintu gereja, di sisi kiri sebuah pohon Natal berdiri tegak. Sementara Hironimus duduk menghadap masjid raya. Sedikit ke arah barat, dua orang tentara berjaga di dekat pagar gereja, tepat di pos pengamanan pintu keluar kodam tentara republik Indonesia. Selain berseberangan dengan masjid raya, Gereja Hati Kudus juga berdampingan langsung dengan kompleks militer.
Menjelang Natal, kehidupan kota berjalan seperti biasa. Tidak ada perayaan megah sebagaimana di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Kaum minoritas merayakan hari besar mereka dengan sederhana, di rumah, dan di tempat ibadah.
“Tidak apa-apa, biar saya duduk menghadap Masjid Raya,” ujar Hironimus. “Saya selalu suka duduk mengarah ke sana. Selain melihat lalu lintas pengendara, saya juga bisa melihat saudara-saudara beda agama di masjid raya.”
Wajah lelah terlihat dari keringat yang menetes di dahinya. Ia memperbaiki posisi duduk, juga kacamatanya, lalu menatap saya. “Tuhan telah memberkati saya. Ini tahun ketiga saya bertugas di sini,” katanya memulai percakapan. Saya melihat ketulusan di matanya, sorot yang mencintai kedamaian, yang menghargai tamu dari agama lain. Tak ada sedikit pun rasa curiga.
Dari caranya duduk, dari kesantunannya, dan dari pilihannya menghadap masjid raya, saya paham mengapa ia dipercaya menjadi pastor kepala di tempat ini. Hironimus bercerita bahwa ia berasal dari Flores dan kini berusia 53 tahun. “Saya baru tiga tahun menjadi pastor kepala di gereja ini. Sebelumnya di Timur, bukan sebagai kepala, melainkan pembina,” tuturnya. Setiap kali berbicara, ia jarang menatap mata lawan bicara. Pandangannya selalu melewati saya, menuju masjid raya di belakang.
Ia mengaku selama hidup berdampingan dengan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, semuanya berjalan dengan aman. Tidak ada gangguan sama sekali. Tak lama kemudian, Kevin Leonardo muncul membawa dua botol air mineral. Ia menyerahkan satu kepada Hironimus dan satu kepada saya, lalu kembali masuk. Salib kecil itu masih bergantung di lehernya.
Kami meneguk air masing-masing, satu-dua tegukan, sebelum Hironimus melanjutkan cerita. “Selama tiga kali Natal di Banda Aceh, semuanya berjalan aman. Tidak ada gangguan sama sekali. Pos pengamanan ini hanya formalitas,” katanya tegas. “Orang-orang di sini baik-baik. Saya mengakuinya.”
Sebelum pindah ke Aceh, Hironimus sempat mendengar kabar bahwa daerah ini tidak aman bagi kaum minoritas. Namun, semua kabar itu runtuh setelah ia tinggal dan bergaul langsung dengan masyarakat. “Bagi saya, cara terbaik mengenal suatu wilayah adalah dengan berada langsung di sana. Apa yang dikatakan orang luar atau diberitakan media tidak selalu sama dengan kenyataan,” ujarnya. “Faktanya, kami aman.”
Selama tiga tahun bertugas, ia mengalami banyak hal menyenangkan. Salah satunya adalah kedekatannya dengan tokoh-tokoh agama mayoritas, yang selalu memastikan keamanan umat Katolik. “Mereka sering bertanya, ‘Bapak aman di sini?’ Saya selalu menjawab, ‘Saya sangat aman,’” katanya.
Pandangan Hironimus tak pernah lepas dari masjid raya. Hingga saya pun memberanikan diri bertanya, “Apa yang Bapak lihat di belakang saya?”
“Saya melihat masjid raya,” jawabnya pelan. “Setiap keluar gereja, saya selalu melihat ke sana. Dan saya selalu teringat kisah Paus Yohanes Paulus II, ketika ia untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Masjid Umayyah di Damaskus, dalam misi mencari perdamaian.”
Awal tahun 2000-an, Paus Yohanes Paulus II tiba di Asia Barat, Suriah. Dua motor pengawal di depan dan empat di belakang mengiringi mobil Paus memasuki pekarangan Masjid Umayyah. Peristiwa itu kemudian tercatat dalam sejarah: untuk pertama kalinya seorang Paus menginjakkan kaki di masjid umat Islam.
Di hadapan para hadirin, Paus berpidato tentang konflik berabad-abad di Timur Tengah antara Kristen dan Muslim. “Yang paling saya ingat dari pidato itu adalah penekanannya bahwa kaum muda harus diajari cara menghormati dan memahami satu sama lain agar agama tidak disalahgunakan untuk membenarkan kebencian dan kekerasan,” cerita Hironimus dengan mata berkaca-kaca.
“Tapi bagaimana dengan kemarahan umat Muslim saat itu?” tanya saya. “Saya pernah mendengar tentang kunjungan Paus ke masjid, tapi yang saya ingat justru kemarahan di berbagai tempat.”
Hironimus membenarkan posisi duduknya. “Ternyata Anda mengetahui cerita itu,” ucapnya datar. “Benar, tapi samar-samar,” jawab saya lagi.
Usai kunjungan tersebut, kemarahan memang muncul di berbagai penjuru dunia Muslim. Paus dituduh membawa simbol Kristen secara diam-diam ke salah satu situs suci Islam terpenting. Sebagian umat menuntut agar Paus melepaskan salibnya karena dianggap sebagai penghinaan terhadap Islam. Ratusan ribu warga Suriah memadati Jalan Lurus (Straight Street) di Damaskus—tempat Santo Paulus memeluk agama Kristen—untuk menyaksikan mobil Paus melintas menuju Masjid Umayyah. Kendati demikian, otoritas Suriah melarang protes publik berdasarkan hukum darurat militer yang telah berlaku hampir empat puluh tahun.
“Saya ingat, saat itu viral di berita-berita, seorang pemuka masjid di Damaskus, Sheikh al-Hout, mengeluarkan pernyataan keras. ‘Jika Paus boleh masuk ke masjid, apakah kami diizinkan mengumandangkan azan di Basilika Santo Petrus?’ ujar al-Hout.
Namun, kata Hironimus, pandangan berbeda datang dari Michael Fitzgerald, seorang ahli Islam dari Vatikan. Ia menyatakan bahwa langkah Paus justru dapat dilihat sebagai titik awal pengakuan Katolik atas kesucian Islam. Sebagai catatan, sekitar tiga puluh tahun sebelumnya, Paus Yohanes Paulus II juga menjadi Paus pertama yang memasuki sebuah sinagoga Yahudi.
Di sesi terakhir wawancara, Hironimus menutup pembicaraan dengan sebuah kalimat yang mendalam. “Jika masjid raya dan gereja kudus diberi nyawa, siapa yang bisa menjamin mereka tidak mencintai toleransi?” Ia melanjutkan, “Toleransi, akan tumbuh dengan sendirinya, terlebih bila dua nyawa telah hidup berdampingan begitu lama,” katanya pelan, sepelan hari itu berlalu di negeri syariat di ujung barat pulau Sumatra.