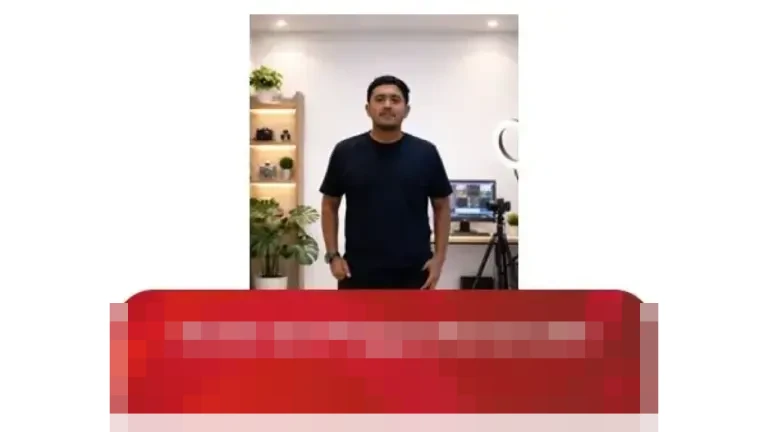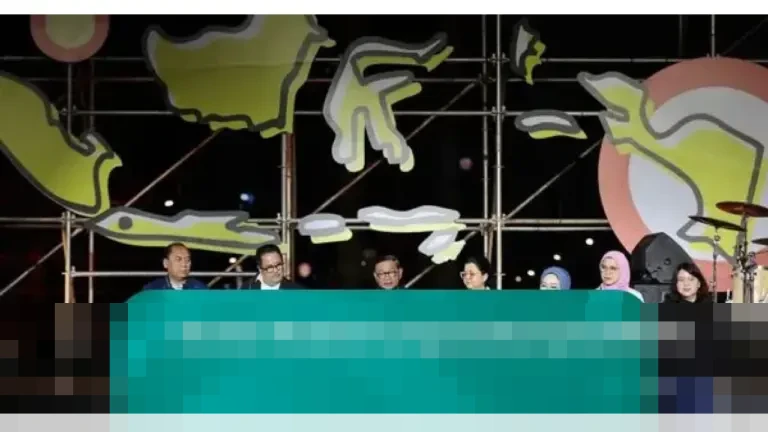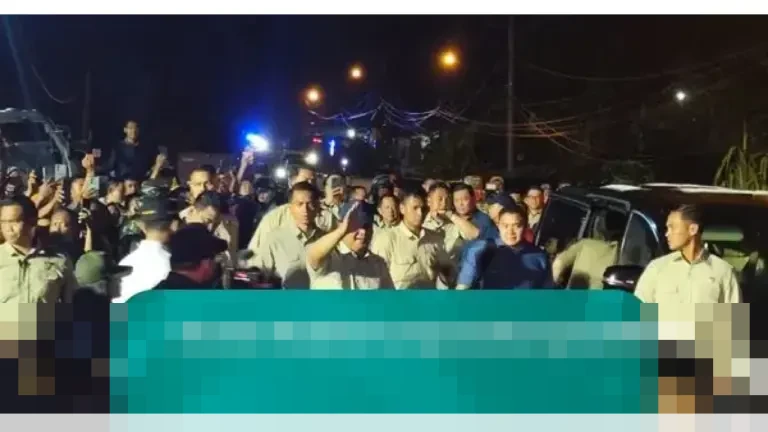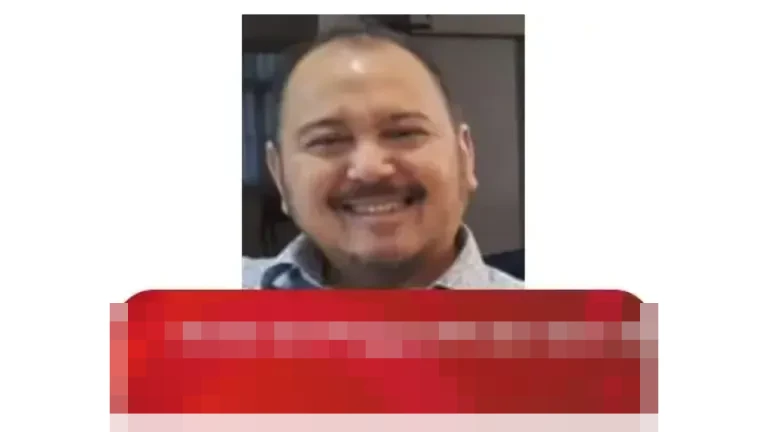Kawasan Asia Tenggara, yang dihimpun dalam The Association of Southeast Asian Nation (ASEAN), kini dipuji sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi paling dinamis di dunia. Proyeksi menempatkan ASEAN sebagai kekuatan ekonomi terbesar kelima secara global pada tahun 2030. Namun, di balik gemerlap pertumbuhan ini, pertanyaan besar muncul: seberapa seriuskah ASEAN dalam mewujudkan kesetaraan gender, ataukah ini hanya sekadar retorika regional?
ASEAN, yang didirikan pada 8 Agustus 1967, beranggotakan 11 negara dan berlandaskan prinsip non-interference. Organisasi ini berupaya mewujudkan stabilitas, perdamaian, serta kemajuan bersama melalui dialog dan kolaborasi. Sementara itu, kesetaraan gender, menurut UN Women, adalah kesamaan hak, tanggung jawab, dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki, tanpa bergantung pada jenis kelamin saat lahir. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menambahkan bahwa kesetaraan gender berarti kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki keadaan yang setara untuk mewujudkan hak asasi manusia mereka secara penuh, serta berkontribusi dan menerima manfaat dari pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Kesetaraan Gender: Fondasi Pembangunan Berkelanjutan
Seorang filsuf politik dan etika asal Amerika Serikat, Martha C. Nussbaum, mendefinisikan kesetaraan gender sebagai kemampuan nyata perempuan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat melalui akses yang setara terhadap peluang, hak, dan kapasitas dasar, bukan sekadar kesetaraan formal di hadapan hukum. Kesetaraan gender bukan hanya isu perempuan, melainkan isu hak asasi manusia yang fundamental dan fondasi utama bagi terciptanya dunia yang sejahtera, damai, dan berkelanjutan.
Dalam Sustainable Development Goals (SDGs), kesetaraan gender berada di poin ke-5, yang bertujuan mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta anak perempuan di seluruh dunia. Pencapaian target ini krusial sebagai komitmen global untuk mengakhiri kemiskinan dan melindungi hak asasi manusia pada tahun 2030.
Paradoks Ekonomi dan Kesenjangan Gender di Asia Tenggara
Ekonomi ASEAN memiliki ciri khas dualitas. Di satu sisi, kawasan ini menjadi lumbung pangan dunia dan produsen utama komoditas global seperti karet dan minyak sawit. Di sisi lain, kawasan ini sangat bergantung pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor UMKM menyumbang sekitar 97 hingga 99% dari seluruh unit usaha dan menyerap lebih dari 80% tenaga kerja, di mana perempuan mengelola lebih dari setengahnya, yaitu sebanyak 67% menurut ASEAN Stats. Mureks mencatat bahwa kontribusi ekonomi perempuan yang besar ini tidak selalu selaras dengan perlindungan dan pengakuan yang mereka terima.
Laporan ASEAN Gender Outlook tahun 2024 justru mengungkapkan realitas yang bertentangan. Perempuan masih menghadapi kesenjangan upah hingga 20% dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang setara, terutama di sektor manufaktur dan pertanian informal. Partisipasi mereka di sektor formal juga terhambat oleh beban kerja domestik yang tidak proporsional. Rata-rata kursi parlemen di kawasan hanya menyentuh angka 22%, jauh dari target ideal untuk mencapai keseimbangan suara dalam arah pembangunan regional.
Ancaman kekerasan berbasis gender juga masih signifikan. Di beberapa negara seperti Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, dan Vietnam, perempuan dilaporkan lebih sering mengalami kekerasan seksual, terutama bagi pekerja migran atau yang berstatus pekerja informal. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, ancaman kekerasan masih membutuhkan perhatian serius.
Komitmen ASEAN: Antara Kerangka Strategis dan Implementasi
ASEAN telah menunjukkan komitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui berbagai kerangka strategis dan institusional yang terpadu dalam tiga pilar utama: politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya. Kesetaraan gender masuk ke dalam pilar sosial-budaya.
Komitmen ini diwujudkan melalui pembentukan:
- ASEAN Committee on Women (ACW)
- ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC)
Kedua lembaga ini menjadi pelopor dalam perumusan kebijakan menyeluruh di tingkat kawasan. Salah satu yang paling penting adalah ASEAN Gender Mainstreaming Strategic Framework (AGMSF) 2021–2025, yang dirancang untuk memastikan perspektif gender terintegrasi ke dalam kebijakan keamanan, ekonomi, dan transformasi digital. Selain itu, ASEAN juga meluncurkan Regional Plan of Action on Women, Peace, and Security (RPA-WPS) untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan perdamaian dan pencegahan konflik, serta mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui ASEAN Women Entrepreneurs Network (AWEN).
Melalui instrumen-instrumen ini, ASEAN menegaskan niatnya untuk menyeragamkan perlindungan hukum terhadap kekerasan berbasis gender sekaligus memperluas akses perempuan terhadap literasi dan inklusi keuangan di seluruh negara anggota.
Realitas di Lapangan: Kesenjangan yang Bertahan
Dibalik banyaknya dokumen kebijakan dan seremoni penandatanganan deklarasi, kenyataan yang dihadapi perempuan di tingkat regional maupun nasional masih menunjukkan kesenjangan. Angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang cenderung pasif, dan kesenjangan upah di sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan ekonomi formal terus bertahan. Fakta-fakta ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas komitmen regional yang telah direncanakan.
Pertanyaan pun muncul: apakah komitmen ASEAN terhadap kesetaraan gender benar-benar ditujukan untuk mendorong perubahan struktural yang dirasakan langsung oleh perempuan dalam kehidupan sehari-hari, ataukah ia berhenti sebagai narasi normatif yang memperindah citra diplomatik ASEAN di mata dunia?
Akar Masalah Struktural dan Budaya
Kesetaraan gender di kawasan Asia Tenggara masih terikat dengan nilai-nilai sosial dan norma yang berkembang di masyarakat. Banyak negara di kawasan ini masih dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal yang memposisikan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan perempuan sebagai pengelola rumah tangga. Norma ini, meskipun tidak tertulis dalam hukum, hidup kuat dalam praktik sosial sehari-hari, mulai dari pembagian peran kerja domestik hingga representasi kepemimpinan di ruang publik. Akibatnya, perempuan sering menghadapi batasan terhadap pilihan hidup mereka.
Budaya di Asia Tenggara yang sangat beragam, dengan banyaknya tradisi lokal, agama, dan nilai komunitas, membentuk pandangan masyarakat mengenai relasi gender. Dalam banyak hal, keharmonisan dan kepatuhan lebih penting dibandingkan kebebasan individual, membuat isu kesetaraan gender sering dianggap sebagai ancaman terhadap nilai tradisional. Praktik pernikahan anak, misalnya, masih ditemukan di beberapa negara, terutama di wilayah pedesaan atau pedalaman yang memiliki keterbatasan ekonomi dan pendidikan, sering dilegitimasi atas dasar tradisi atau alasan ekonomi.
Data Menegaskan Ketimpangan
Global Gender Gap Report 2025 mencatat bahwa skor kesetaraan gender negara-negara ASEAN berkisar antara 0,68 hingga 0,78, masih jauh dari skor 1 yang menandakan kesetaraan penuh. Filipina memang menempati posisi teratas di kawasan, namun capaian tersebut tidak menentukan kondisi regional secara keseluruhan, mengingat banyak negara anggota lainnya masih tertinggal terutama dalam aspek kesempatan ekonomi dan pemberdayaan politik.
Laporan Social Institutions and Gender Index (SIGI) 2024 dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menegaskan bahwa hambatan terhadap kesetaraan gender di Asia Tenggara tidak hanya bersumber dari pasar tenaga kerja, melainkan berakar pada diskriminasi yang tertanam dalam institusi sosial. Norma budaya, struktur keluarga, dan aturan hukum masih membatasi kemandirian perempuan.
World Bank mencatat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan secara konsisten berada jauh di bawah laki-laki di hampir seluruh negara ASEAN. Ketimpangan ini bukan hanya menggambarkan pilihan individu, tetapi hasil dari struktur pasar kerja yang tidak ramah gender, kurangnya kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi perawatan, serta norma sosial yang masih menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama kerja domestik.
Ketimpangan struktural ini semakin diperparah oleh terbatasnya adopsi gender budgeting di kawasan. OECD mendapati bahwa hanya beberapa negara yang telah memasukkan perspektif gender ke dalam kebijakan fiskal secara sistematis. Tidak adanya kebijakan fiskal yang responsif gender menunjukkan bahwa komitmen negara terhadap kesetaraan gender masih bersifat normatif dan belum menyentuh aspek paling mendasar, yaitu pembagian sumber daya negara.
Keterbatasan Kelembagaan ASEAN
Untuk memahami mengapa kesenjangan gender tetap tinggi meskipun kerangka kebijakan regional telah tersedia, kita harus menelaah karakter kelembagaan ASEAN itu sendiri. Sejak awal berdiri, ASEAN dibangun di atas prinsip non-interference, konsensus, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Prinsip-prinsip ini, meskipun penting untuk menjaga stabilitas kawasan, menjadi pedang bermata dua bagi kesetaraan gender.
Sebagian besar instrumen gender ASEAN merupakan soft law, tanpa mekanisme penegakan yang mengikat. Artinya, ASEAN tidak memiliki hak atau kekuatan untuk memaksa negara-negara anggotanya mengubah undang-undang nasional mereka, menetapkan kuota representasi perempuan, atau mengalokasikan anggaran khusus untuk kebijakan gender. Implementasi sepenuhnya menjadi urusan kewenangan dan kemauan politik setiap negara. Akibatnya, ada kesenjangan signifikan antara negara-negara yang relatif progresif dan negara-negara yang melihat kesetaraan gender sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional atau stabilitas sosial. Menurut Mureks, inilah mengapa ASEAN sering disebut sebagai Soft Institutionalism, karena tidak mengikat, tidak memberlakukan mekanisme sanksi, dan hanya bergantung pada norma, persuasi, konsensus, serta penghindaran konflik.
Isu gender di ASEAN sering dipisahkan dari agenda strategis utama seperti ekonomi, perdagangan, dan keamanan, karena kesetaraan gender dimasukkan dalam pilar sosial-budaya, yang secara historis memiliki “harga” lebih rendah dibandingkan pilar ekonomi dan politik-keamanan. Pendekatan sektoral ini menyebabkan gender mainstreaming gagal menyentuh kebijakan makro yang justru menentukan distribusi sumber daya dan kekuasaan. Kebijakan gender ASEAN hanya berfungsi sebagai penyesuaian sementara dan belum mampu mengubah struktur ketimpangan yang ada.
Selain itu, banyak inisiatif gender ASEAN masih menempatkan perempuan sebagai aktor ekonomi produktif, bukan sebagai subjek politik yang berhak menantang relasi kuasa. Pemberdayaan terfokus pada individu perempuan, tanpa secara serius menantang struktur patriarki yang mengakar dalam institusi negara, pasar tenaga kerja, dan norma sosial. Dalam hal ini, kesetaraan gender direduksi menjadi peningkatan partisipasi, bukan redistribusi kekuasaan. Dengan keterbatasan kelembagaan dan kebijakan tersebut, tidak heran jika komitmen gender ASEAN sering gagal menghasilkan perubahan yang substantif.
Menilai Keseriusan ASEAN: Antara Simbol dan Substansi
Menilai keseriusan ASEAN dalam mewujudkan kesetaraan gender membutuhkan pendekatan yang seimbang. ASEAN tidak bisa disamakan dengan organisasi regional yang sepenuhnya abai terhadap isu gender. Produksi kebijakan, laporan, kampanye, kerangka kerja, dan forum dialog ASEAN menunjukkan adanya kesadaran yang relatif konsisten. Dalam konteks politik internasional, komitmen ini juga berfungsi sebagai alat diplomasi normatif, yang memperkuat citra ASEAN sebagai kawasan yang progresif dan selaras dengan agenda global.
Namun, banyak kebijakan gender ASEAN berfungsi sebagai simbol kepatuhan terhadap norma internasional atau symbolic compliance, tanpa upaya sistematis untuk mengatasi akar ketimpangan. Fenomena ini disebut sebagai bentuk regional rhetoric, di mana kesetaraan gender menjadi bahasa bersama dalam dokumen resmi, tetapi kehilangan daya kritisnya ketika berhadapan dengan kepentingan politik domestik.
Dalam konteks ini, pertanyaan “apakah ASEAN serius?” tidak bisa dijawab secara hitam-putih. ASEAN menunjukkan keseriusan dalam membangun kerangka normatif, tetapi masih berhati-hati dalam mendorong perubahan struktural. Hal ini disebabkan oleh ketegangan antara upaya menjaga stabilitas regional dan tuntutan keadilan gender, yang pada akhirnya membatasi ruang gerak kebijakan ASEAN. Selama kesetaraan gender masih dipandang sebagai isu sekunder yang berpotensi mengganggu harmoni politik, komitmen ASEAN akan tetap berada pada tataran retorika.
Tanggung Jawab Kolektif untuk Perubahan Struktural
Kawasan Asia Tenggara memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan masif. Meskipun ASEAN mungkin belum mampu mewadahi kebutuhan dan kepentingan masyarakat regionalnya dalam hal kesetaraan gender, sebagai masyarakat global, kita tidak memiliki batasan untuk selalu mempromosikannya. Edukasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi yang berkembang pesat dapat menjadi sarana penting.
Perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sama pentingnya, sama besarnya, dan sama berartinya. Jika masyarakat membatasi kebebasan dan ruang gerak perempuan, hal ini justru membuat kapasitas sosial dan ekonomi mereka menjadi lemah, yang akhirnya menghambat pembangunan manusia. Kesadaran diperlukan sedini mungkin, karena apa yang sedang dihadapi bukan hanya soal kebijakan regional atau komitmen negara, tetapi tanggung jawab kolektif sebagai bagian dari masyarakat global.
Simone de Beauvoir dalam bukunya The Second Sex tahun 1949 memberikan gambaran bahwa perempuan tidak dilahirkan dalam posisi yang rendah, tetapi dibentuk oleh konstruksi sosial. Kesadaran ini penting, karena perubahan struktural selalu berawal dari perubahan cara berpikir masyarakat terhadap relasi kuasa gender. Ketimpangan gender yang dibiarkan berlarut-larut tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas sosial dan politik. Francis Fukuyama dalam The Origins of Political Order tahun 2011 menekankan bahwa institusi yang gagal menjamin keadilan dan inklusivitas akan menghadapi krisis legitimasi. Ketika separuh populasi terus dimarjinalkan dari pengambilan keputusan, institusi negara kehilangan basis moral dan sosialnya.
Oleh karena itu, partisipasi masyarakat global dalam mengawasi, mengkritisi, dan mendorong kebijakan yang adil gender adalah salah satu tanggung jawab bersama. Mendorong kesetaraan gender harus bisa melewati retorika dan simbolisme, hal ini membutuhkan keberanian untuk mengkritik struktur sosial, ekonomi, dan politik yang memelihara ketimpangan. Tantangan sesungguhnya bukan terletak pada kurangnya bahasa kesetaraan atau kampanye yang dilakukan, tetapi absennya kemauan politik untuk mendistribusikan kekuasaan dan kesempatan. Dengan memberikan akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta keterwakilan dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi, dunia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta memperkuat ketahanan sosial secara menyeluruh. Seperti yang dituliskan pada Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, hak-hak perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja migran, serta kelompok rentan dan terpinggirkan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang melekat, menyatu, dan tidak terpisahkan.