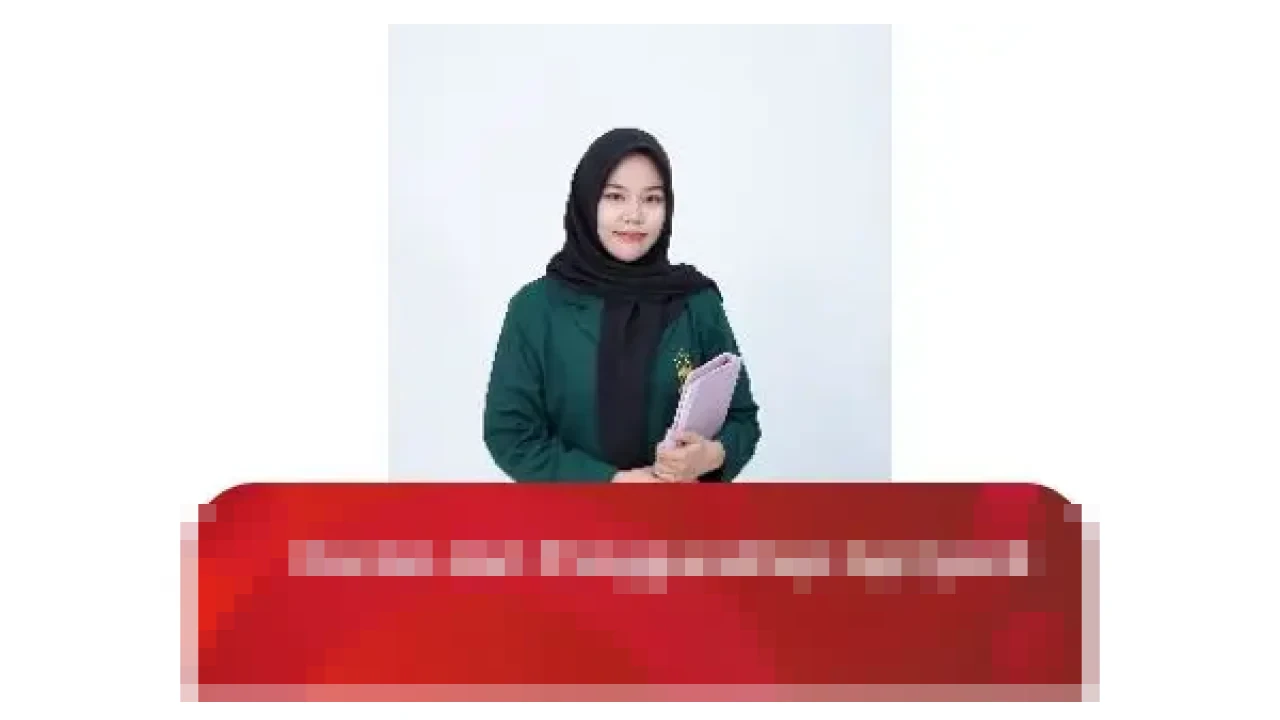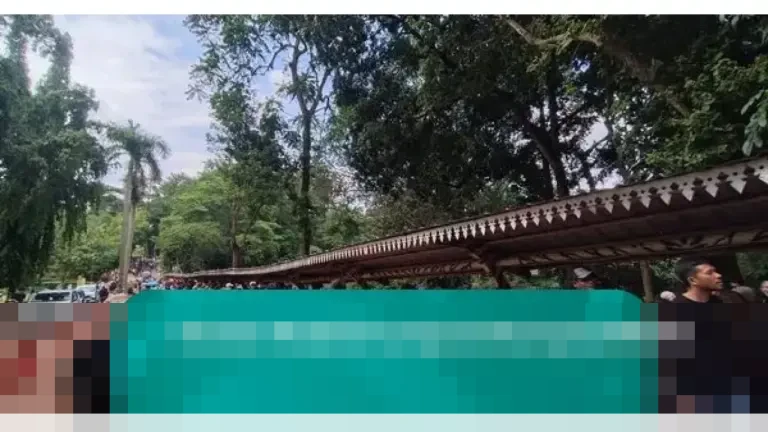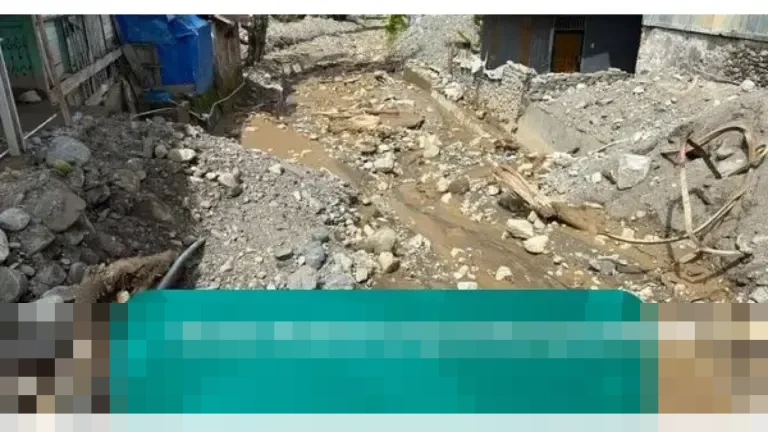Kemampuan berbahasa Inggris kini bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan telah menjelma menjadi prasyarat yang nyaris wajib dalam dunia kerja. Di tengah arus globalisasi yang kian masif, TOEFL (Test of English as a Foreign Language) menjadi simbol kelayakan profesional bagi banyak perusahaan.
Namun, di saat yang sama, TOEFL juga kerap dipersepsikan sebagai hambatan struktural yang tak semua pencari kerja mampu lewati dengan mudah. Fenomena ini semakin terasa ketika menelusuri berbagai platform lowongan kerja. Banyak perusahaan, baik multinasional maupun nasional, mencantumkan skor TOEFL minimum sebagai syarat administratif. Persyaratan ini seolah menegaskan bahwa penguasaan bahasa Inggris dianggap sejalan dengan kompetensi, profesionalisme, dan kesiapan menghadapi tantangan kerja lintas negara. Mureks mencatat bahwa tren ini terus meningkat seiring dengan kebutuhan kolaborasi global.
Mureks menghadirkan beragam artikel informatif untuk pembaca. mureks.co.id
TOEFL sebagai Identitas Profesional
Tidak dapat dimungkiri, bahasa Inggris memang memainkan peran penting dalam dunia kerja modern. Komunikasi lintas budaya, akses literatur internasional, hingga kolaborasi global membutuhkan kemampuan bahasa yang memadai. Sertifikat TOEFL kemudian hadir sebagai tolak ukur standar yang dianggap objektif dan kredibel. Bahkan, menurut akademisi UI, Irwan Santoso, “penguasaan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat resmi seperti TOEFL menjadi identitas profesional.” Di mata calon pemberi kerja, TOEFL memudahkan proses seleksi dan memberi jaminan dasar atas kemampuan bahasa calon karyawan.
Ketika Standar Global Berbenturan dengan Realitas Lokal
Persoalan muncul ketika standar ini diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan latar belakang dan akses setiap pencari kerja. Sebagai mahasiswa yang sedang bersiap memasuki dunia kerja, Depi Apriyanti, mahasiswi Jurusan Bahasa Inggris semester 3 di Universitas Nurul Huda Blitang (UNUHA), kerap merasakan kegelisahan yang sama dengan banyak teman sebaya. Ada lulusan dengan kemampuan teknis yang mumpuni, portofolio kuat, serta pengalaman organisasi yang relevan, tetapi gagal melangkah lebih jauh hanya karena skor TOEFL tidak memenuhi ambang batas.
apakah skor TOEFL benar-benar mempresentasikan keseluruhan kompetensi seseorang?
Perdebatan mengenai syarat TOEFL semakin mencuat ketika muncul gugatan dari seorang pengacara bernama Hanter Oriko Siregar terhadap kebijakan Undang-undang Ketenagakerjaan dan Undang-undang ASN ke Mahkamah Konstitusi (MK). Isi gugatannya adalah untuk menghapuskan TOEFL sebagai syarat melamar kerja di Indonesia, baik untuk CPNS maupun melamar ke perusahaan swasta.
Gugatan ini berangkat dari pandangan bahwa TOEFL telah berubah dari alat ukur kompetensi menjadi bentuk penyaringan yang berpotensi timpang, terutama bagi pencari kerja dari latar belakang ekonomi dan pendidikan yang terbatas. Bagi sebagian mahasiswa, TOEFL bukan sekadar tes, melainkan beban tambahan. Biaya les yang relatif mahal, waktu persiapan yang panjang, serta tekanan psikologis saat ujian menjadi tantangan nyata. Tidak semua kampus menyediakan fasilitas pelatihan bahasa Inggris yang memadai, dan tidak semua mahasiswa memiliki akses kursus privat atau sumber belajar berkualitas.
Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa syarat TOEFL tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi. Pemberlakuan syarat semacam itu justru untuk meningkatkan kompetensi diri dan kesiapan menghadapi tuntutan global. TOEFL penting di era saat ini karena kemampuan bahasa Inggris membuka banyak peluang kerja.
Tekanan Psikologis di Balik Skor TOEFL
Dalam praktiknya, TOEFL sering kali menjadi momok. Bagian listening, reading, dan writing menuntut konsentrasi tinggi serta penguasaan kosakata akademik yang luas. Bagi mahasiswa non-jurusan bahasa Inggris, materi ini terasa jauh dari konteks pembelajaran sehari-hari. Akibatnya, TOEFL dipersepsikan sebagai tes yang “asing” dan tidak relevan dengan keahlian mereka.
Tekanan ini berdampak pada kondisi mental mahasiswa. Rasa cemas, minder, hingga kehilangan motivasi belajar bukanlah hal yang jarang terjadi. Ketika masa depan kerja seolah ditentukan oleh satu angka skor, kegagalan dalam TOEFL dapat memunculkan rasa tidak berdaya dan ketidakpastian arah hidup.
apakah sistem pendidikan kita telah benar-benar mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tuntutan tersebut, atau justru melempar beban ke pundak individu tanpa bekal yang memadai?
Mencari Jalan Tengah: Peran Kampus dan Pemerintah
Alih-alih meniadakan TOEFL sepenuhnya, pendekatan yang lebih manusiawi dan kontekstual perlu dipertimbangkan. TOEFL seharusnya diposisikan sebagai alat pengembangan diri, bukan sekadar penghalang administratif. Kampus memiliki peran strategis untuk menjembatani kebutuhan ini melalui kurikulum bahasa Inggris yang aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan tiap jurusan.
Pembelajaran bahasa Inggris tidak cukup jika hanya berfokus pada tata bahasa dan latihan soal. Mahasiswa perlu dibekali kemampuan komunikasi nyata: membaca dokumen profesional, memahami instruksi kerja, menulis laporan sederhana, dan melakukan presentasi dasar. Dengan pendekatan ini, TOEFL tidak terasa sebagai beban tambahan, melainkan bagian alami dari proses akademik.
Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memperluas akses. Subsidi biaya tes, penyediaan fasilitas tes gratis atau murah, serta kerja sama dengan platform pembelajaran digital dapat menjadi langkah konkret. Ketika akses diperluas, TOEFL tidak lagi menjadi simbol ketimpangan, melainkan peluang yang dapat diraih lebih merata.
Strategi Adaptif Mahasiswa Menghadapi TOEFL
Di tengah realitas yang ada, mahasiswa tetap perlu bersikap adaptif. Menetapkan target skor yang realistis, menyesuaikan materi belajar dengan bidang pekerjaan yang dituju, serta memanfaatkan sumber belajar daring menjadi strategi yang relevan. TOEFL sebaiknya tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam berbahasa Inggris.
Membangun portofolio bahasa juga penting. Presentasi singkat, tulisan opini, atau proyek kolaboratif berbahasa Inggris dapat menjadi bukti nyata kemampuan komunikasi, melampaui sekadar angka skor.
Kesimpulan
TOEFL memang bukan sistem yang sempurna. Namun, di tengah persaingan kerja yang semakin ketat, kemampuan bahasa Inggris tetap menjadi modal penting. Tantangan sesungguhnya bukan pada ada atau tidaknya TOEFL, melainkan pada bagaimana negara, institusi pendidikan, dan dunia kerja memastikan bahwa setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang adil untuk mencapainya.
Dalam dunia yang mengaku inklusif, gerbang menuju masa depan seharusnya tidak hanya terbuka bagi mereka yang mampu sejak awal, tetapi juga bagi mereka yang mau belajar, berjuang, dan diberi jalan. TOEFL seharusnya menjadi jembatan menuju dunia kerja, bukan menjadi batas tak kasatmata yang membatasi langkah generasi muda.