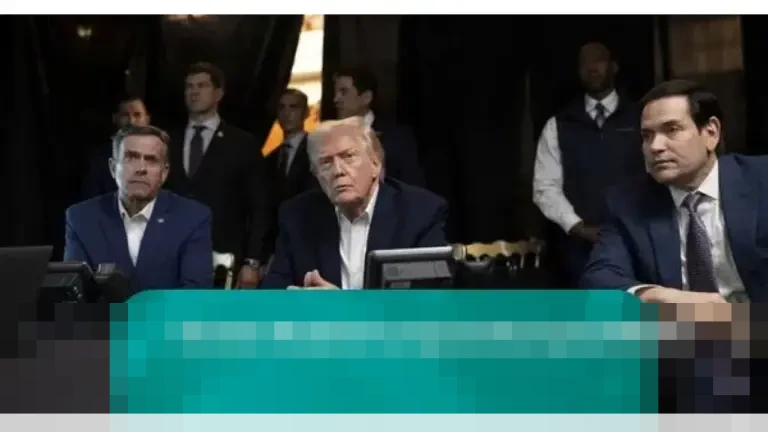Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah, dinilai sebagai upaya krusial untuk memperbaiki kualitas demokrasi elektoral di Indonesia. Namun, di balik prospek penyederhanaan, muncul persoalan mendasar terkait masa jeda kekuasaan di daerah.
Menurut Firman Nugraha, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Galuh, Ciamis, pemisahan rezim pemilu ini menawarkan penyelenggaraan yang lebih sederhana, kampanye yang lebih fokus, pemilih yang lebih rasional, serta pemerintahan yang lebih solid. Kendati demikian, ia menyoroti potensi kekosongan jabatan kepala daerah dan DPRD selama periode transisi.
Artikel informatif lainnya dapat ditemukan dalam liputan Mureks. mureks.co.id
Jika pemilu nasional diselenggarakan pada 2029, sementara pemilu daerah baru dilaksanakan sekitar dua hingga dua setengah tahun kemudian, yakni pada 2031, akan ada periode transisi yang berpotensi menimbulkan kekosongan jabatan. Dalam negara demokrasi konstitusional, kekosongan kekuasaan bukan sekadar masalah teknis, melainkan persoalan serius yang menyentuh jantung konstitusi.
Konstitusi Tidak Menghendaki Kekosongan Kekuasaan
UUD 1945 dibangun di atas dua prinsip fundamental yang harus berjalan beriringan: kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui pemilu, dan kesinambungan pemerintahan (continuity of government). Kekosongan jabatan kepala daerah akan melumpuhkan fungsi eksekutif di daerah, sementara kekosongan DPRD akan menghilangkan fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.
Firman Nugraha menegaskan, daerah tanpa DPRD berarti kehilangan salah satu pilar demokrasi lokal. Oleh karena itu, masa transisi pemilu terpisah tidak boleh dibiarkan tanpa desain konstitusional yang jelas.
Penjabat Kepala Daerah sebagai Solusi Transisi
Untuk jabatan kepala daerah, praktik ketatanegaraan Indonesia telah memiliki jawaban. Pengisian oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah telah lama dikenal dan dipraktikkan, termasuk pada periode 2022–2024.
Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai putusannya, pada prinsipnya membenarkan pengangkatan penjabat. Syaratnya, pengangkatan tersebut bersifat sementara, memiliki dasar undang-undang, dan disertai pembatasan kewenangan. Dalam konteks ini, Pj Kepala Daerah berfungsi sebagai pemerintah sementara (government caretaker), bukan pemegang mandat politik penuh.
Dengan pembatasan ketat, seperti larangan mutasi pejabat dan kebijakan strategis jangka panjang, penunjukan Pj masih dapat diterima secara konstitusional sebagai solusi transisi.
Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD: Opsi Paling Rasional
Persoalan menjadi jauh lebih kompleks ketika menyangkut DPRD. DPRD bukan jabatan tunggal, melainkan lembaga kolektif perwakilan rakyat. Pasal 22E UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa anggota DPRD dipilih melalui pemilu.
Artinya, DPRD tidak bisa diisi dengan “penjabat” sebagaimana kepala daerah. Namun, membiarkan DPRD kosong juga bukan pilihan, karena hal itu berarti menanggalkan prinsip representasi rakyat di tingkat lokal. Mureks mencatat bahwa di sinilah perlunya mengusung sebuah “mekanisme khusus” pengisian DPRD pada masa transisi.
Penerapan mekanisme khusus ini bukan upaya untuk melawan konstitusi, melainkan bentuk rekayasa konstitusional sementara untuk menghadapi masa transisi, yaitu sebagai situasi luar biasa akibat perubahan desain pemilu.
Beberapa opsi sempat mengemuka dalam diskursus publik, antara lain pengangkatan anggota DPRD tanpa pemilu, pembekuan DPRD, atau perpanjangan masa jabatan. Dari ketiganya, perpanjangan terbatas masa jabatan DPRD dinilai sebagai opsi yang paling rasional dan setidaknya paling sedikit menimbulkan masalah konstitusional.
Firman Nugraha mengakui bahwa perpanjangan jabatan menyimpang dari prinsip periodisasi lima tahunan. Namun, dalam situasi transisi yang tidak ideal, “penyimpangan terbatas” dapat dibenarkan sepanjang didesain dengan memenuhi syarat ketat:
- Perpanjangan harus bersifat satu kali dan tidak menjadi preseden permanen.
- Harus dibatasi waktu secara tegas, maksimal dua hingga dua setengah tahun.
- Kewenangan DPRD perlu dibatasi, misalnya hanya menjalankan fungsi anggaran rutin dan pengawasan layanan publik, tanpa membuat kebijakan strategis jangka panjang.
- Pengaturan ini harus dituangkan secara eksplisit dalam undang-undang, bukan kebijakan administratif.
DPRD tidak menjalankan kekuasaan eksekutif, sehingga risiko penyalahgunaan kekuasaan relatif lebih kecil dibanding kepala daerah. Dengan pembatasan yang jelas, perpanjangan ini dapat dipandang sebagai jalan tengah yang masih dapat diterima oleh konstitusi.
Model Hibrida: Solusi Proporsional
Dari perspektif hukum tata negara, solusi paling proporsional adalah model hibrida. Dalam model ini, jabatan kepala daerah diisi oleh penjabat dengan kewenangan terbatas, sementara DPRD diperpanjang masa jabatannya secara terbatas dengan pembatasan fungsi.
Model ini menghindari dua ekstrem yang sama-sama bermasalah: perpanjangan penuh kekuasaan eksekutif tanpa pemilu, atau kekosongan lembaga perwakilan rakyat di daerah. Dalam teori konstitusi, ini dikenal sebagai prinsip “least constitutional harm”, yaitu memilih solusi yang paling sedikit merugikan prinsip dasar konstitusi dalam situasi yang serba terbatas.
Pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah merupakan langkah penting guna menata dan mengonsolidasi sistem pemilu di Indonesia. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh bagaimana masa transisinya diatur. Tanpa desain transisi yang cermat, pemilu yang dimaksudkan memperkuat demokrasi justru berisiko melahirkan defisit legitimasi di tingkat lokal.
Konstitusi tidak menuntut solusi yang sempurna, tetapi menuntut solusi yang proporsional dan akuntabel di hadapan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi. Penjabat kepala daerah dan perpanjangan terbatas DPRD—jika dirancang secara ketat dan transparan melalui undang-undang—adalah pilihan paling masuk akal untuk memastikan negara tetap berjalan tanpa mengorbankan prinsip demokrasi.