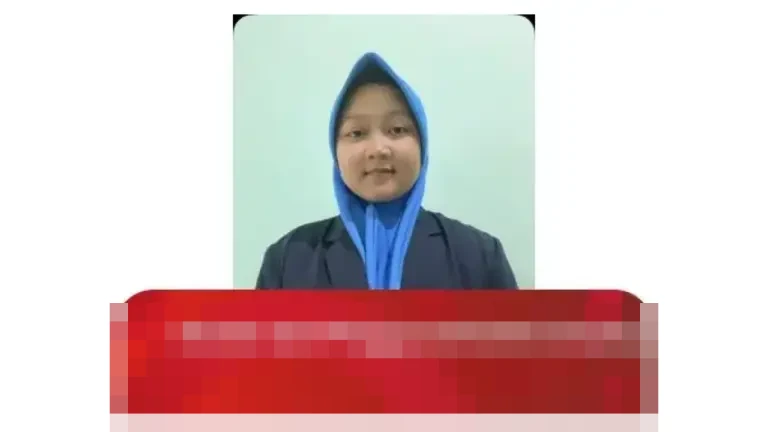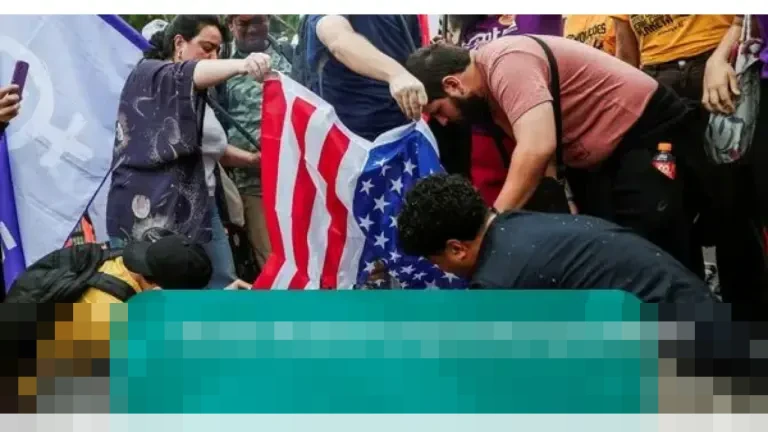Di tengah kembali menguatnya perdebatan antara rasio, sains, dan iman di era modern, nama Imam Al-Ghazali kembali relevan untuk dibicarakan. Mureks mencatat bahwa jauh sebelum perdebatan serupa muncul dalam filsafat Barat modern, dunia Islam abad ke-11 telah lebih dulu bergulat dengan persoalan serupa. Saat itu, filsafat Yunani, melalui karya Aristoteles dan Plato, mendominasi lanskap intelektual Islam dan menantang posisi wahyu sebagai sumber kebenaran tertinggi.
Pada masa Zaman Keemasan Islam, Baghdad menjelma sebagai pusat peradaban Abbasiyah sekaligus arena pertarungan gagasan. Warisan filsafat Yunani diterjemahkan, dikaji, dan dikembangkan secara sistematis oleh para pemikir Muslim. Tokoh seperti Al-Farabi dan Ibn Sina berupaya mengharmonikan rasio filsafat dengan wahyu Al-Qur’an melalui sistem metafisika yang rumit dan mengagumkan.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks melalui mureks.co.id.
Namun, keberhasilan para filsuf ini justru memunculkan kegelisahan di kalangan teolog dan ahli fikih. Filsafat, dengan klaim kebenaran yang dibangun melalui demonstrasi logis, mulai dipandang berpotensi menggeser otoritas wahyu. Di sinilah sejarah mencatat kehadiran seorang figur yang kelak mengubah arah pemikiran Islam secara mendasar, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, yang dikenal sebagai Hujjatul Islam.
Kisah Al-Ghazali bukanlah kisah penolakan mentah-mentah terhadap filsafat. Sebaliknya, ia merupakan kisah penaklukan intelektual. Al-Ghazali menundukkan filsafat Yunani bukan dengan menafikan akal, melainkan dengan menggunakan perangkat filsafat itu sendiri untuk menunjukkan batas-batas klaim rasio. Ia menegaskan bahwa akal memiliki peran penting, tetapi tidak berdaulat absolut di atas wahyu.
Krisis Epistemologis Sang Hujjatul Islam
Al-Ghazali lahir di Tus, wilayah Khurasan, pada 1058 M. Sejak usia muda, ia dikenal sebagai ulama brilian yang menguasai fikih mazhab Syafi’i dan teologi Asy’ariyah. Karier akademiknya mencapai puncak ketika ia diangkat menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah Baghdad, institusi pendidikan paling prestisius di dunia Islam kala itu.
Namun, di puncak kejayaan intelektualnya, Al-Ghazali justru dilanda krisis mendalam. Ia mulai meragukan kepastian pengetahuan yang selama ini ia kuasai. Dalam otobiografinya Al-Munqidz min al-Dalal, ia mempertanyakan apakah pengetahuan yang diperoleh melalui pengajaran, perdebatan, dan reputasi akademik benar-benar melahirkan keyakinan sejati.
Ia menguji berbagai jalan pencarian kebenaran. Ilmu kalam ia nilai hanya mampu mempertahankan dogma, bukan mengantarkan pada kepastian. Kelompok Batiniyyah ia tolak karena bertumpu pada otoritas tersembunyi yang tidak dapat diverifikasi. Filsafat kemudian menjadi fokus kajiannya.
Selama hampir dua tahun, Al-Ghazali mempelajari secara mendalam pemikiran Al-Farabi dan Ibn Sina. Ia menguasai logika, fisika, dan metafisika Aristotelian dengan sangat baik, bahkan menuliskannya secara sistematis dalam Maqashid al-Falasifah. Ironisnya, karya ini sempat disalahpahami di Eropa abad pertengahan sebagai pembelaan terhadap filsafat Yunani, padahal sejatinya merupakan langkah awal menuju kritik yang lebih tajam.
Tahafut al-Falasifah: Kritik dari Dalam
Puncak respons Al-Ghazali terhadap dominasi filsafat Yunani tertuang dalam karya monumental Tahafut al-Falasifah. Buku ini bukan serangan emosional terhadap filsafat, melainkan kritik metodologis yang dibangun dengan logika Aristotelian itu sendiri.
Al-Ghazali membedakan cabang-cabang filsafat, seperti matematika, logika, dan ilmu alam, yang ia anggap relatif netral. Kritik utamanya diarahkan pada metafisika, wilayah di mana para filsuf mengajukan klaim tentang Tuhan, alam, dan akhirat berdasarkan spekulasi rasional.
Dalam Tahafut, ia mengidentifikasi dua puluh titik kesalahan para filsuf, terutama Ibn Sina. Tiga di antaranya ia anggap membawa pada kekufuran:
- Keyakinan tentang keabadian alam semesta. Para filsuf berpendapat bahwa alam bersifat azali bersama Tuhan. Bagi Al-Ghazali, pandangan ini bertentangan dengan prinsip penciptaan dari ketiadaan sebagaimana ditegaskan dalam wahyu.
- Pandangan bahwa Tuhan hanya mengetahui hal-hal partikular secara universal. Al-Ghazali menolak keras gagasan ini karena menafikan kemahatahuan Tuhan sebagaimana ditegaskan Al-Qur’an.
- Penolakan terhadap kebangkitan jasmani. Menurut Al-Ghazali, pengingkaran ini bertentangan langsung dengan konsensus umat Islam dan janji eksplisit tentang kehidupan akhirat.
Menundukkan Kausalitas dan Mengembalikan Kehendak Tuhan
Argumen paling revolusioner Al-Ghazali adalah kritiknya terhadap konsep kausalitas niscaya. Para filsuf meyakini hubungan sebab-akibat bersifat pasti dan inheren. Api, karena kodratnya, pasti membakar kapas.
Al-Ghazali membantah asumsi ini. Menurutnya, yang kita saksikan hanyalah kebiasaan empiris, bukan hubungan niscaya. Api tidak membakar dengan sendirinya. Tuhanlah yang setiap saat menciptakan peristiwa terbakar ketika api bersentuhan dengan kapas.
Pandangan ini menempatkan Tuhan sebagai pelaku aktif dalam setiap kejadian alam. Mukjizat, seperti kisah Nabi Ibrahim yang tidak terbakar api, menjadi bukti bahwa hukum alam bukan keniscayaan mutlak, melainkan tunduk pada kehendak ilahi. Dengan demikian, Al-Ghazali menghancurkan fondasi metafisika filsafat Yunani yang bertumpu pada rantai kausalitas rasional yang kaku.
Dari Dekonstruksi Menuju Sintesis
Setelah mematahkan klaim absolut rasio, Al-Ghazali belum menemukan kepastian yang ia cari. Ia kemudian meninggalkan Baghdad dan menjalani kehidupan asketis selama lebih dari satu dekade. Dalam pengembaraan inilah ia menemukan tasawuf sebagai jalan menuju keyakinan sejati.
Baginya, kepastian tertinggi tidak dicapai melalui debat intelektual, melainkan melalui pengalaman batin. Hasil dari perjalanan ini tertuang dalam karya agung Ihya Ulum al-Din, sebuah sintesis besar antara fikih, kalam, dan tasawuf.
Ironisnya, dalam proses “menundukkan” filsafat, Al-Ghazali justru mengadopsi alat terpentingnya, yakni logika. Ia membersihkan logika dari muatan metafisika spekulatif dan menjadikannya sebagai metodologi berpikir yang netral. Logika kemudian ia masukkan ke dalam disiplin ushul fikih, menandai integrasi rasio ke dalam ortodoksi Islam.
Warisan yang Terus Diperdebatkan
Selama berabad-abad, Al-Ghazali kerap dituduh sebagai tokoh yang mematikan filsafat dan sains dalam Islam. Tuduhan ini terlalu menyederhanakan persoalan. Yang ia hancurkan bukanlah rasio, melainkan klaim absolut rasio atas realitas.
Al-Ghazali menundukkan filsafat Yunani dengan menunjukkan batas arogansinya sekaligus menjinakkan kekuatannya untuk melayani wahyu. Warisannya bukanlah anti-intelektualisme, melainkan sintesis yang menyeimbangkan syariat, rasionalitas teologis, dan kedalaman spiritual. Di tengah dunia modern yang kembali mempertentangkan iman dan akal, pemikiran Al-Ghazali mengingatkan bahwa rasio adalah alat yang kuat, tetapi bukan penguasa tunggal atas kebenaran.