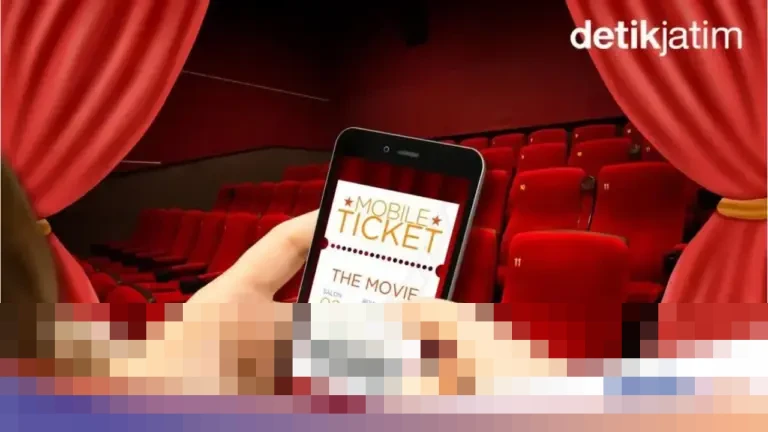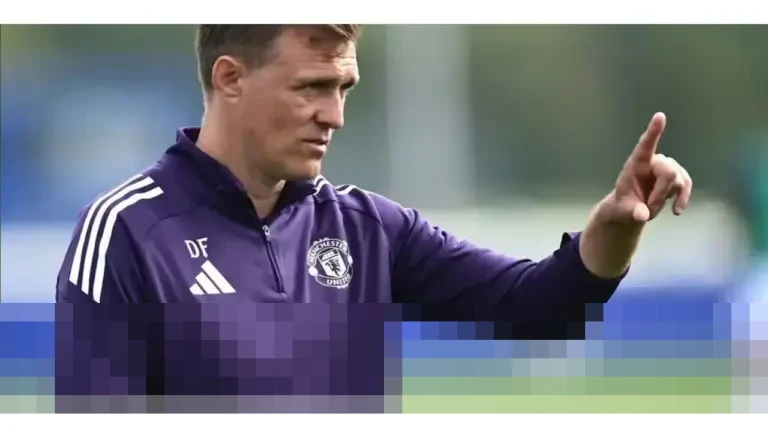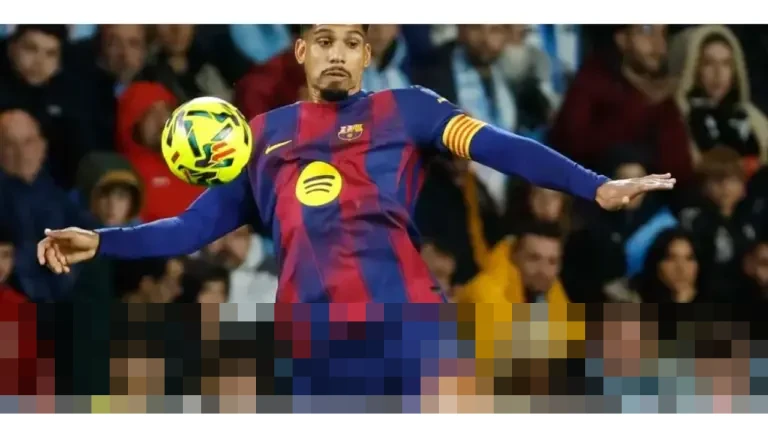Wacana mobil nasional kembali mencuat ke permukaan, kali ini melalui proyek kendaraan listrik yang diberi nama i2C atau Indigenous Indonesian Car. Digagas oleh PT Teknologi Militer Indonesia (PT TMI), kehadiran i2C segera memantik perdebatan sengit di kalangan publik, antara harapan besar akan kemandirian industri otomotif dan skeptisisme yang tak terhindarkan mengingat sejarah panjang proyek serupa yang kerap kandas di tengah jalan.
i2C sendiri merupakan akronim dari Indigenous Indonesian Car, yang secara harfiah berarti mobil asli buatan Indonesia. Proyek ini berada di bawah naungan PT TMI, sebuah entitas yang berafiliasi dengan Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan, sehingga secara struktural memiliki kaitan erat dengan Kementerian Pertahanan. Posisi ini menempatkan i2C dalam kerangka yang berbeda dari proyek mobil nasional sebelumnya; ia tidak dibingkai sebagai “karya anak sekolah” atau inisiatif populis semata, melainkan sebagai bagian dari pengembangan industri strategis yang berawal dari sektor pertahanan dan kini diperluas ke pasar sipil.
Artikel informatif lainnya dapat ditemukan dalam liputan Mureks. mureks.co.id
Klaim “Bukan Re-badge” dan Keterlibatan Italdesign
Pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, i2C memamerkan konsep kendaraan listriknya dan secara tegas menepis anggapan bahwa ia hanyalah mobil re-badge dari Tiongkok. Pihak pengembang mengklaim bahwa hak kekayaan intelektual untuk desain eksterior, interior, hingga struktur bodi sepenuhnya berada di tangan Indonesia. Fakta menarik lainnya adalah keterlibatan Italdesign, rumah desain otomotif legendaris asal Italia yang telah menorehkan jejaknya pada model-model ikonik BMW, Lamborghini, hingga Maserati. Kolaborasi ini memperkuat narasi bahwa i2C bukan sekadar mengganti logo pada mobil jadi.
Meski demikian, PT TMI mengakui bahwa komponen utama seperti baterai, motor listrik, dan platform sasis berasal dari mitra global, yang besar kemungkinan dari Tiongkok. Hal ini memunculkan kembali istilah “re-badge” di ruang publik. Namun, secara teknis, pendekatan i2C lebih tepat disebut platform sharing atau coachbuilding. Berbeda dengan praktik re-badge murni—di mana kendaraan, mesin, dan interior identik lalu hanya berganti emblem—i2C menggunakan platform global yang telah teruji, kemudian dikembangkan dengan desain dan integrasi sistem sendiri. Strategi ini bukanlah hal baru di industri otomotif global; banyak produsen besar memulai langkah serupa untuk menekan biaya riset dan mempercepat waktu masuk pasar, seperti yang dilakukan VinFast di Vietnam yang menggunakan platform lama BMW untuk produk awalnya.
Nuansa Politik dan Jangka Waktu Produksi
Pendekatan i2C yang lebih rapi tidak lantas membuatnya terlepas dari nuansa politik. Kemunculannya yang berdekatan dengan masa transisi pemerintahan dan keterkaitannya dengan institusi negara memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan proyek ini setelah momentum politik berlalu. Selain itu, kendaraan yang dipamerkan di GIIAS 2025 masih berupa clay model—model visual tanpa fungsi jalan. Dalam industri otomotif, jarak antara clay model dan produksi massal bisa memakan waktu 3 hingga 5 tahun. PT TMI sendiri menargetkan produksi sekitar tahun 2027–2028, sebuah rentang waktu yang bagi publik terasa panjang dan penuh ketidakpastian.
Tantangan Berat di Depan Mata
Mureks mencatat bahwa tantangan terbesar i2C bukan hanya pada konsep, melainkan pada eksekusi bisnis yang harus bersaing dengan pemain global. Industri kendaraan listrik di Indonesia saat ini telah diisi oleh raksasa seperti BYD, Wuling, hingga Hyundai, yang memiliki skala produksi masif dan rantai pasok yang kuat. Jika i2C masih mengandalkan impor komponen utama dengan volume produksi terbatas, harga jualnya berpotensi kurang kompetitif. Di sisi lain, membangun kepercayaan konsumen membutuhkan jaringan purnajual yang solid, ketersediaan suku cadang, serta kualitas produksi yang konsisten—aspek-aspek yang kerap menjadi “neraka” bagi produsen baru.
Contoh dari kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa mobil nasional tidak pernah lahir secara instan. Proton di Malaysia, misalnya, bertahan berkat dukungan negara selama puluhan tahun sebelum akhirnya bermitra dengan Tiongkok. Sementara itu, VinFast di Vietnam berkembang agresif dengan investasi besar, perekrutan talenta global, dan keberanian untuk masuk ke pasar internasional. Dari sini, keberhasilan i2C sangat bergantung pada konsistensi strategi jangka panjang, bukan sekadar narasi nasionalisme sesaat.
Pada akhirnya, i2C bukan sekadar proyek re-badge, namun juga belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian industri otomotif nasional. Ia berada di wilayah abu-abu: sebuah upaya jump-start industri dengan pendekatan global. Publik kini menanti pembuktian nyata—bukan sekadar render, pameran, atau jargon. Jika i2C mampu transparan soal teknologi, fokus pada ceruk pasar strategis, dan menghadirkan produk yang kompetitif secara harga dan kualitas, proyek ini berpeluang menjadi fondasi baru industri otomotif Indonesia. Namun, jika kembali terhenti di tengah jalan, sejarah akan mencatatnya sebagai satu lagi mimpi besar yang tak sempat diwujudkan. Waktu akan menjawab: i2C, mobil listrik nasional masa depan, atau sekadar proyek sesaat?