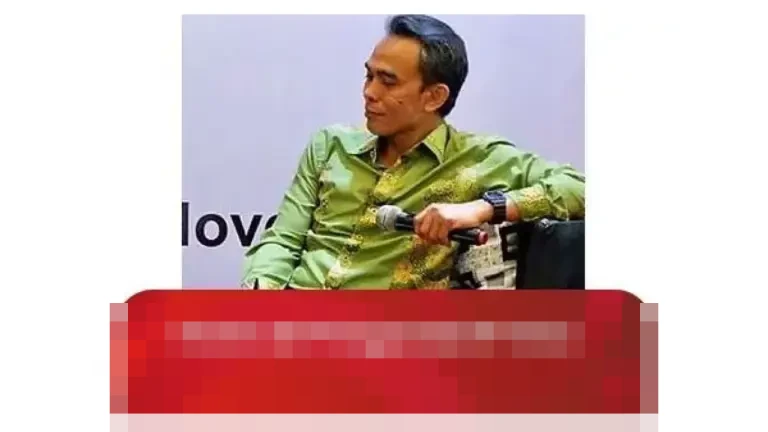Fenomena ironis kerap terjadi di kalangan pemelajar bahasa Arab, baik santri maupun mahasiswa. Mereka mungkin memiliki nilai sempurna dalam mata kuliah Bahasa Arab, bahkan hafal di luar kepala kitab Alfiyah Ibnu Malik, namun mendadak kesulitan saat diajak berkomunikasi oleh penutur asli. Kondisi yang sering disebut ‘jago kandang’ ini bukan disebabkan oleh kurangnya kecerdasan, melainkan adanya kekeliruan dalam proses otak dan mental dalam mengolah bahasa.
Ketika seorang guru berbicara menggunakan bahasa Arab di kelas, seringkali seluruh siswa terdiam. Mereka memahami maksud guru, tetapi belum tentu mampu merespons dengan bahasa Arab yang lancar. Padahal, banyak di antara mereka yang menguasai ribuan kosakata dan meraih nilai sempurna dalam ujian tata bahasa (qawaid). Namun, semua pengetahuan itu seolah runtuh ketika dihadapkan pada percakapan sehari-hari. Skor tes profisiensi yang tinggi seringkali hanya menjadi angka di atas kertas, tanpa jaminan praktik di dunia nyata.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Menelisik Akar Gagap Berbahasa
Dalam kacamata psikolinguistik, “musuh” utama di balik kegagapan berbahasa bukanlah kebodohan. Ada fenomena yang dikenal sebagai language anxiety atau kecemasan berbahasa. Kondisi ini menyebabkan working memory (memori kerja) otak kewalahan, seolah ‘nge-lag’, karena harus memikirkan rumus tata bahasa, ketakutan akan kesalahan, dan kebingungan dalam menyusun kalimat. Akibatnya, produksi ujaran terhambat, meskipun materi bahasa sebenarnya sudah tersimpan di kepala.
Lantas, mengapa pemelajar bahasa Arab begitu takut membuat kesalahan? Apakah ini terkait dengan doktrin bahwa “Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran” sehingga kesalahan dalam berbicara dianggap dosa besar? Bandingkan dengan pemelajar bahasa Inggris yang mungkin hanya akan ditertawakan jika salah tata bahasa. Dalam bahasa Arab, kesalahan i’rab (perubahan harakat akhir) dapat mengubah makna secara fundamental. Ketakutan akan “kesakralan” inilah yang mungkin memperparah kecemasan.
Selain itu, campur aduk antara bahasa ibu (First Language/L1) dengan bahasa kedua yang sedang dipelajari juga membingungkan otak. Misalnya, struktur kalimat bahasa ibu yang berbeda mendasar dengan bahasa Arab, bahkan dengan bahasa Indonesia. Pola Subjek-Predikat-Objek-Keterangan (S-P-O-K) dalam bahasa Indonesia berbeda dengan pola Jumlah Fi’liyah (kata kerja di awal) dalam bahasa Arab. Perbedaan sintaksis ini memaksa otak bekerja dua kali lebih keras. Minimnya contoh percakapan alami juga menjadi faktor. Ibarat seorang koki yang tahu resep soto ayam enak, namun belum bisa langsung memasak tanpa keterampilan meracik yang lihai.
Kompetensi dan Performansi: Dikotomi ala Noam Chomsky
Fenomena ini sempat menggemparkan dunia linguistik: kompetensi telah mapan, namun praktiknya nihil. Hingga akhirnya, Noam Chomsky mengemukakan pendapatnya bahwa kompetensi tidak sama dengan performansi. Menghafal kosakata asing tidak serta-merta berarti mampu berbicara. Chomsky membedakan antara apa yang kita ketahui (kompetensi) dengan apa yang kita lakukan (performansi). Dikotomi ini mengubah arah pandang linguistik secara signifikan.
Kompetensi dianggap bersemayam di dalam pikiran saja, sementara performansi tercermin dalam aktivitas berbahasa yang dilakukan oleh penutur. Sayangnya, pembelajaran bahasa Arab di Indonesia, khususnya di madrasah dari tingkat rendah hingga tinggi, masih sangat mengandalkan qawaid sebagai satu-satunya pelajaran wajib yang harus dikuasai.
Melihat tantangan dunia saat ini, pelajaran qawaid saja tentu tidak lagi memadai. Globalisasi menuntut setiap individu memiliki kecakapan berbahasa asing agar dapat berkomunikasi lintas negara. Namun, kurikulum bahasa Arab nasional masih berfokus pada teori semata, meskipun klaimnya adalah mencetak lulusan yang terampil. Dalam praktiknya, performansi diukur pada level rendah, seperti hafalan dan pilihan ganda yang kurang berbobot. Pembelajaran lebih menitikberatkan pada “pengetahuan” dibandingkan “aktivitas”. Singkatnya, masalah kurikulum kita adalah terlalu memuja kompetensi (teori) dan melupakan performansi (praktik). Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh penggunaan metode klasik yang terus dipertahankan, padahal metode pembelajaran terbaru lebih mengutamakan praktik. Metode qawaid wa tarjamah (tata bahasa terjemah) adalah warisan lama yang tujuan akhirnya adalah membaca, bukan berbicara. Seperti yang telah disinggung, qawaid tidak lagi cukup menghadapi realitas zaman sekarang.
Dari Kitab Kuning ke Kelas Percakapan: Pergeseran Paradigma yang Terhambat
Jika ditelusuri akar masalahnya, dominasi qawaid (kompetensi) tidak terlepas dari sejarah pendidikan Islam di Nusantara. Bahasa Arab dipelajari selama berabad-abad semata-mata sebagai alat untuk membedah teks. Tujuannya mulia, yaitu agar santri mampu membaca dan memahami Kitab Kuning atau literatur turats tanpa harakat. Dalam konteks ini, kesalahan i’rab dianggap aib besar karena dapat membelokkan makna teologis.
Tidak heran jika pola pikir “haram hukumnya salah gramatikal” ini terbawa hingga ke kelas-kelas percakapan (muhadatsah). Guru, yang juga merupakan produk dari sistem lama, secara tidak sadar menjadi “polisi bahasa”. Setiap kali murid mencoba berbicara, misalnya mengucap “Fatimah yadzhabu”, guru langsung memotong, “Salah! Harusnya Fatimah tadzhabu!”. Koreksi prematur semacam ini justru membunuh performansi murid sebelum sempat berkembang. Padahal, Chomsky mengingatkan bahwa performansi membutuhkan ruang toleransi untuk tumbuh.
Mendesak: Reorientasi Kurikulum dan Lingkungan Belajar
Bayangkan jika kondisi ini terus berlanjut tanpa perbaikan. Bahasa Arab akan terus dianggap momok menakutkan, dan lulusan madrasah justru gagap berbicara. Lantas, apa yang akan mereka tampilkan di masyarakat? Kurikulum seolah tidak memberi ruang bagi performansi di kelas. Ujian praktik pun tidak termasuk dalam ujian resmi. Namun, hal ini wajar terjadi manakala murid jarang atau bahkan tidak pernah dilatih untuk berbicara di kelas.
Dengan afirmasi positif dari lingkungan, seperti guru dan teman-teman, tentu murid akan lebih senang hati untuk berpraktik. Oleh karena itu, Bi’ah Lughawiyah (Lingkungan Bahasa) yang ramah kesalahan dan mendukung sangat diperlukan. Lingkungan ini harus memfasilitasi aktivitas bahasa Arab yang alami, seperti role play dan dialog. Ujian praktik juga dapat dilakukan melalui video speaking. Yang tak kalah penting adalah materi nahwu sharaf yang dikontekstualisasikan. Murid tidak kekurangan pengetahuan; mereka hanya kekurangan kesempatan untuk menggunakannya.