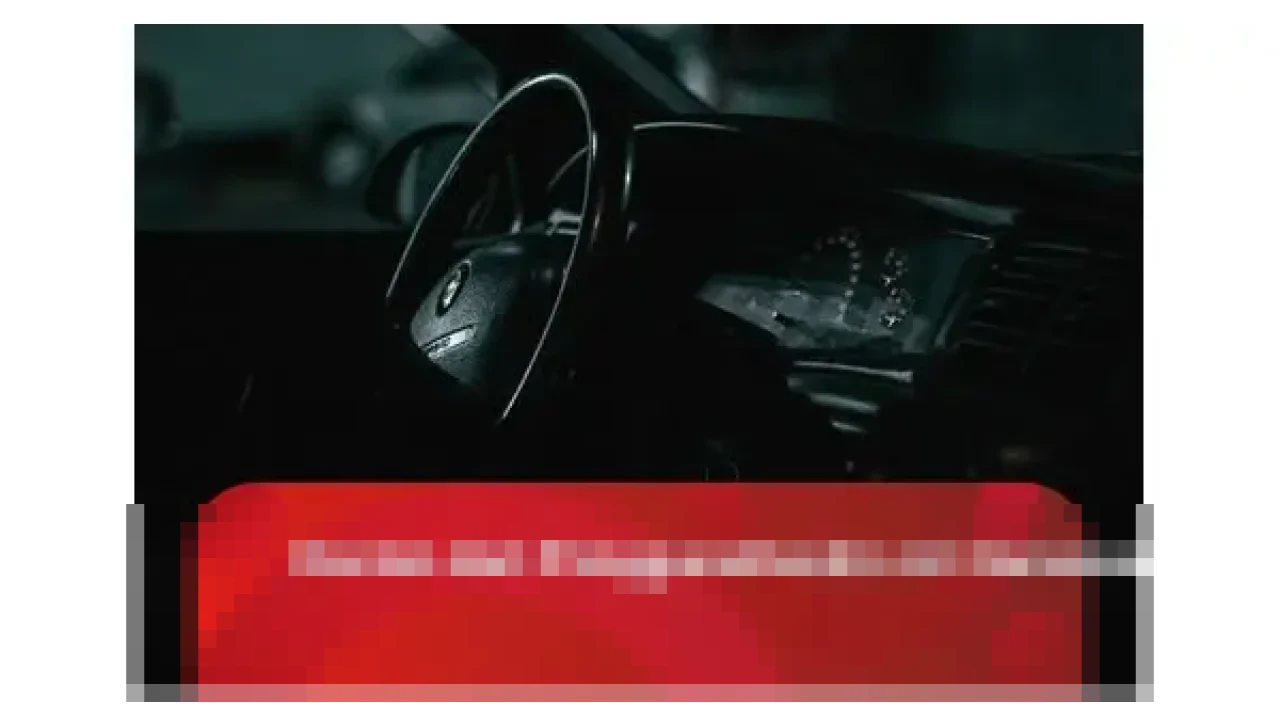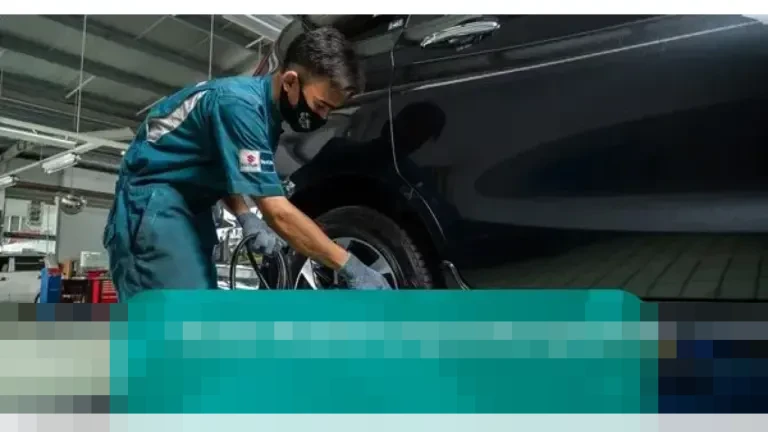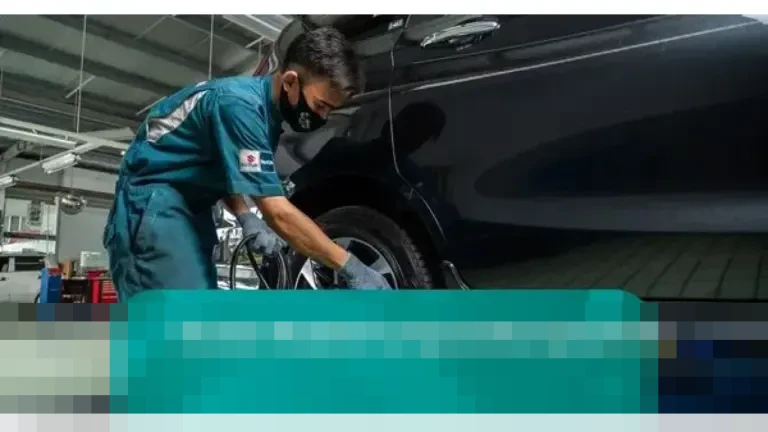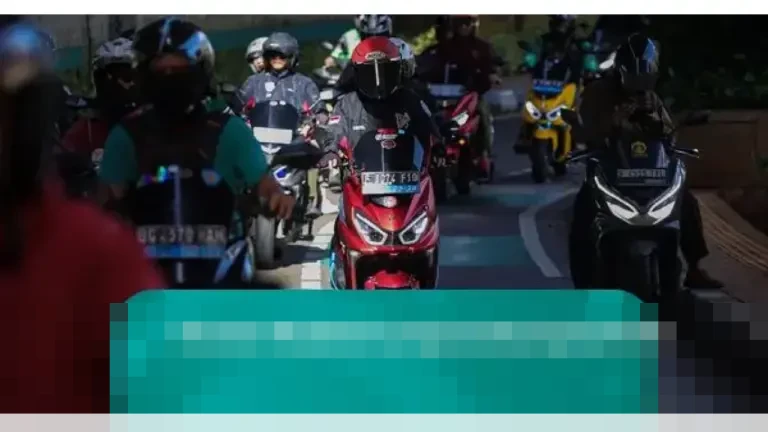Pada abad ke-20, becak, kendaraan roda tiga yang digerakkan dengan kayuhan, menjelma menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat perkotaan di Indonesia. Masuk sekitar tahun 1930-an melalui Singapura, alat transportasi sederhana ini dengan cepat merebut hati rakyat biasa dan menjadi pilihan utama.
Mengapa Becak Begitu Populer?
Popularitas becak tidak lepas dari sejumlah keunggulan yang ditawarkannya. Menurut Purnawan Basundoro dalam buku Pengantar Kajian Sejarah Ekonomi Perkotaan, becak banyak dipilih masyarakat karena murah, fleksibel untuk masuk ke gang-gang sempit, serta tidak membutuhkan bahan bakar seperti delman kuda.
Baca artikel informatif lainnya di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Selain itu, becak dinilai lebih bersih dibandingkan delman kuda yang meninggalkan kotoran di jalan. Kendaraan besar juga sulit menjangkau area permukiman padat, sementara becak sangat lincah. Buku Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan terbitan KITLV-Jakarta menyoroti bahwa biaya operasional becak rendah, tidak membutuhkan modal besar, serta cocok bagi buruh miskin di kota.
Fleksibilitas sistem tarif melalui tawar-menawar juga menjadikan becak semakin ramah bagi masyarakat kelas bawah. Tak hanya mengangkut penumpang, becak juga mampu membawa barang-barang kecil, menambah nilai fungsionalnya.
Perjalanan Becak di Ibu Kota
Becak pertama kali masuk ke Indonesia pada 1930-an, dibawa oleh pedagang Tionghoa dari Singapura, Hong Kong, dan Makassar. Desainnya kemudian mengalami adaptasi lokal, seperti penggunaan ban angin dan roda tiga yang lebih stabil di jalan rusak.
Mureks mencatat bahwa data DPRD DKI Jakarta pada tahun 1936 menunjukkan jumlah becak di Jakarta mencapai 3.900 unit. Angka ini meningkat pesat hingga sekitar 92.650 unit pada 1970, seiring dengan pertumbuhan urbanisasi yang masif.
Pada era 1950-an, becak bahkan dijuluki sebagai “raja” jalanan Jakarta. Jumlahnya mencapai sekitar 25.000 unit dan beroperasi hampir sepanjang hari dalam tiga shift. Memasuki tahun 1970-an, diperkirakan jumlah becak di Jakarta mencapai 100.000 unit, dengan sekitar 200.000 orang menggantungkan hidupnya sebagai tukang becak.
Era Larangan dan Dampak Sosial
Namun, kejayaan becak mulai meredup pada tahun 1970-an. Pemerintah Jakarta menerapkan kebijakan pelarangan becak dengan alasan mengurangi kemacetan dan menata lalu lintas kota. Purnawan Basundoro dalam bukunya menjelaskan bahwa kebijakan ini disertai sistem daerah bebas becak serta razia di jalan-jalan utama.
Akibatnya, banyak tukang becak kehilangan mata pencarian, memicu gejolak sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Meski demikian, pada masanya, becak mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat kota yang padat dan berpenghasilan rendah.
Lebih dari sekadar alat angkut, becak juga membentuk relasi sosial yang unik antara penarik dan penumpang. Proses tawar-menawar, percakapan singkat, hingga saling mengenal menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.
Oleh karena itu, meskipun perannya kini telah menurun drastis, becak tetap memiliki tempat penting dalam sejarah perkotaan Indonesia. Keberadaannya menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan transportasi ideal perlu mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat secara komprehensif.