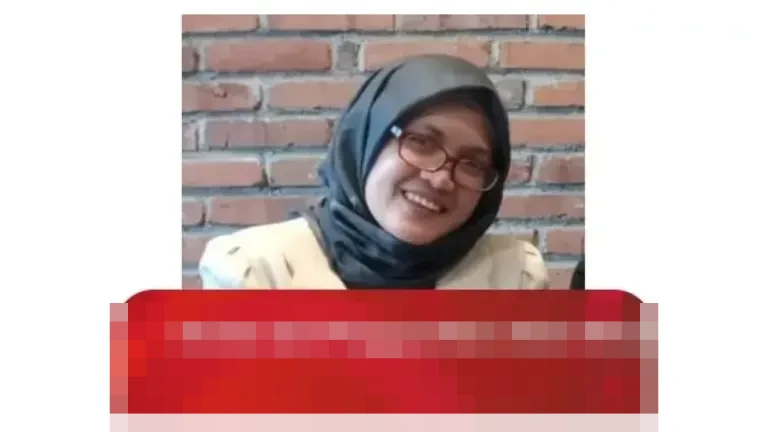Di tengah deru kecepatan zaman modern, kesibukan seringkali dianggap sebagai lambang dedikasi dan relevansi. Kalender yang padat, notifikasi yang tak henti, hingga rasa lelah yang kerap dijadikan identitas, seolah menjadi penanda bahwa seseorang itu penting. Terlebih pascapandemi, kemajuan teknologi seperti rapat daring dan kecerdasan buatan (AI) kian mendorong kita untuk merasa mampu mengerjakan segala sesuatu secara paralel, bahkan khawatir tertinggal jika tidak melakukan multitasking.
Namun, di balik hiruk-pikuk tersebut, tersimpan kegelisahan yang jarang terungkap. Banyak individu merasa kelelahan bukan semata karena beban pekerjaan yang berat, melainkan karena hidup yang tak lagi menyisakan ruang untuk bernapas. Hari-hari terasa penuh, namun hampa. Aktivitas melimpah, tetapi kehadiran diri minim. Banyak capaian kecil, namun kehilangan arah yang jelas.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Fenomena ini, yang disebut overmultitasking, lahir dari budaya yang menuntut kita untuk terus bergerak tanpa memberi kesempatan untuk menuntaskan satu hal sebelum beralih ke hal lain. Ini bukan sekadar kebiasaan kerja, melainkan cerminan budaya yang mengagungkan kecepatan di atas proses dan kesejahteraan individu.
Dari Multitasking Menuju Overmultitasking: Saat Otak Dipaksa Melampaui Batas
Dahulu, multitasking kerap dipromosikan sebagai keterampilan unggulan, bahkan menjadi nilai tambah dalam resume. Namun, sains membuktikan sebaliknya. Otak manusia tidak dirancang untuk fokus pada banyak hal secara bersamaan. Yang terjadi bukanlah multitasking sejati, melainkan continuous partial attention, yakni perhatian yang terpecah dan tidak pernah utuh.
Penelitian dari University of California Irvine menunjukkan bahwa rata-rata dibutuhkan 23 menit untuk kembali fokus setelah satu distraksi. Bayangkan, jika distraksi datang puluhan kali dalam sehari, fokus kita tidak akan pernah benar-benar pulih. Data dari Microsoft Work Trend Index (2024) semakin memperkuat fakta ini, mencatat bahwa pekerja modern menerima lebih dari 250 notifikasi per hari dan berpindah konteks kerja setiap 2–4 menit.
Inilah titik krusial ketika multitasking berubah menjadi overmultitasking: kondisi di mana otak dipaksa bekerja tanpa henti, tanpa kesempatan menyelesaikan satu siklus berpikir secara mendalam. Konsekuensinya tidak hanya penurunan produktivitas, tetapi juga kualitas keputusan, empati, dan kreativitas.
Overmultitasking: Gejala Krisis Personal yang Tersembunyi
Jika ditelusuri lebih jauh, overmultitasking bukan sekadar masalah manajemen waktu, melainkan sebuah krisis personal. Kesibukan seringkali menjadi cara manusia menghindari pertanyaan-pertanyaan besar tentang tujuan hidup. Ketika kita berhenti sejenak, kita dipaksa berhadapan dengan kelelahan, ketidakpastian, dan mungkin kekecewaan terhadap diri sendiri.
Maka, kita terus bergerak, terus mengisi waktu, terus menunda keheningan. Padahal, keheningan seringkali bukanlah musuh, melainkan cermin yang merefleksikan kondisi batin. Dunia modern memang mengajarkan kita untuk terus berlari, tetapi jarang mengajarkan ke mana sebenarnya arah tujuan kita.
Tren Dunia Kerja: Ketika Kesibukan Tak Lagi Identik dengan Nilai
Secara global, dunia kerja menghadapi paradoks. Di satu sisi, teknologi menjanjikan efisiensi. Di sisi lain, justru menciptakan tuntutan kehadiran konstan. Aplikasi seperti Slack, Teams, WhatsApp, dan email hadir bersamaan, tanpa jeda yang jelas.
Namun, tren mulai bergeser. Perusahaan-perusahaan progresif mulai menyadari bahwa produktivitas sejati lahir dari kejelasan, bukan sekadar kesibukan. Pendekatan seperti deep work culture, asynchronous collaboration, dan pembatasan rapat mulai diterapkan. Google, misalnya, sedang menguji kebijakan kerja yang memberi ruang fokus tanpa gangguan.
Meskipun demikian, realitas di banyak organisasi masih tertinggal. Budaya “selalu online” masih sering dianggap sebagai bentuk loyalitas. Padahal, semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar kebutuhan untuk berpikir strategis, dan semakin berbahaya jika ia terjebak dalam overmultitasking.
Dampak Nyata Overmultitasking: Dari Burnout hingga Decision Fatigue
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengidentifikasi burnout sebagai fenomena pekerjaan global. Namun, akar penyebabnya sering luput dari perhatian. Banyak orang mengalami burnout bukan hanya karena volume kerja semata, tetapi karena otak mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk memulihkan diri.
Deloitte Millennial & Gen Z Survey (2024) menunjukkan bahwa mayoritas profesional merasa kelelahan mental kronis akibat tekanan konstan untuk selalu responsif. Overmultitasking juga memicu decision fatigue, yaitu kondisi di mana kemampuan mengambil keputusan menurun drastis karena terlalu banyak keputusan kecil yang harus diambil setiap hari.
Dalam jangka panjang, kondisi ini berdampak pada kepemimpinan, relasi, bahkan spiritualitas. Individu menjadi reaktif, bukan reflektif.
Fokus: Keunggulan Langka di Tengah Dunia yang Bising
Di tengah dunia yang semakin bising, fokus justru menjadi keunggulan yang langka. Profesional yang mampu menjaga kejernihan berpikir, menetapkan batas, dan bekerja dengan kedalaman akan jauh lebih bernilai dibandingkan mereka yang sekadar sibuk. Organisasi masa depan tidak lagi hanya mencari kecepatan, tetapi clarity under pressure. Dan kejelasan ini tidak lahir dari overmultitasking, melainkan dari keberanian untuk berkata “cukup”.
Solusi untuk overmultitasking bukanlah dengan menambah alat atau sistem baru, melainkan mengembalikan ritme hidup yang manusiawi. Ritme yang memberi ruang untuk fokus, istirahat, dan refleksi. Manusia tidak dirancang untuk terus aktif tanpa henti. Bahkan dalam alam, ada musim untuk bekerja dan musim untuk beristirahat. Menghargai ritme ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah kebijaksanaan.
Keheningan yang Menguatkan, Bukan Melemahkan
Mazmur 46:10 mengingatkan, “Berdiam dirilah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah.” Dalam konteks ini, diam bukanlah pasif, melainkan aktif secara rohani. Diam berarti menyerahkan kendali, mengakui keterbatasan, dan mempercayai bahwa hidup tidak harus sepenuhnya digerakkan oleh usaha manusia.
Yesus sendiri sering menarik diri dari keramaian untuk berdoa. Jika Sang Guru memilih jeda, mengapa kita merasa harus selalu bergerak?
Mungkin dunia akan terus menuntut lebih cepat, lebih banyak, dan lebih responsif. Namun, kebijaksanaan sering muncul ketika kita berani berjalan melawan arus. Pertanyaannya bukan lagi, “Seberapa banyak yang bisa aku lakukan?” melainkan, “Apa yang sungguh perlu aku lakukan dengan utuh?”
Overmultitasking mengajarkan kita satu hal penting: hidup bukan tentang mengisi setiap detik, tetapi tentang menghadirkan diri sepenuhnya di momen yang tepat. Dan seringkali, di situlah kedamaian dan makna sejati ditemukan.