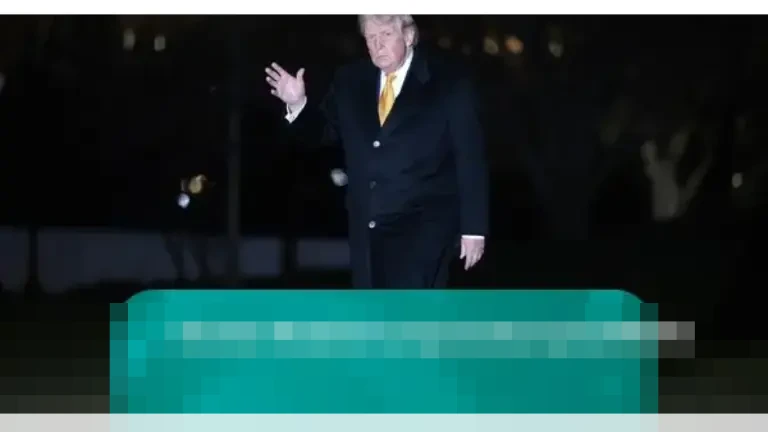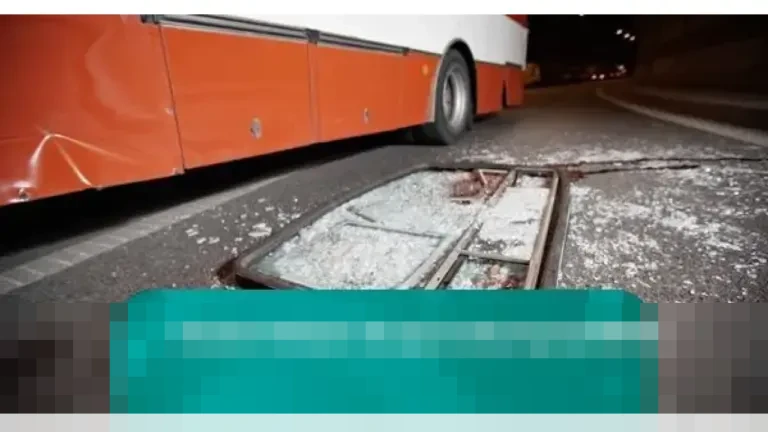Krisis pendidikan di Indonesia bukan sekadar masalah teknis seperti pergantian kurikulum atau fasilitas yang minim. Menurut Panji Dafa Amrtajaya, Sekjen Forum 2045 dan Peneliti di Desanomia, krisis fundamental terletak pada diskoneksi ontologis: keterputusan antara amanat konstitusional “mencerdaskan kehidupan bangsa” dengan realitas pendidikan yang mereduksi manusia menjadi objek produksi sistem ekonomi global. Untuk mengatasi ini, ia menawarkan paradigma transkonstruktif pendidikan yang berpusat pada pedagogi musyawarah, sebuah pendekatan yang mengedepankan dialog, deliberasi, dan ko-konstruksi pengetahuan.
Pembukaan UUD 1945 secara jelas mengamanatkan tujuan bernegara untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Namun, dalam praktiknya, pendidikan justru bergeser menjadi “pabrik” yang mencetak tenaga kerja siap pakai, bukan warga negara yang berdaulat. Mureks mencatat bahwa reduksi manusia menjadi human capital—modal yang diukur dari nilai tukarnya di pasar kerja—menciptakan fragmentasi eksistensial. Siswa mungkin belajar agama tetapi praksis ekonominya eksploitatif, atau menghafal rumus matematika tanpa memahami distribusi kekayaan yang tidak adil. Ironisnya, sistem pendidikan yang mengklaim sebagai pembebas justru menjadi alat reproduksi ketidakadilan.
Liputan informatif lainnya tersedia di Mureks. mureks.co.id
Rekonstruksi Ontologis: Dari Human Capital menuju Manusia Berdaulat
Sistem pendidikan kontemporer cenderung memecah manusia menjadi fragmen terpisah: manusia ekonomi yang produktif, manusia moral yang dididik agama dan Pancasila, serta manusia kognitif yang diukur skor ujian. Fragmentasi ini melahirkan generasi dengan disonansi kognitif-moral, di mana mereka religius dalam ritual namun eksploitatif dalam ekonomi, atau pandai sains namun tumpul terhadap dampak ekologis. Paradigma transkonstruktif mengusulkan integritas tri-subjek: setiap manusia adalah subjek epistemik (mengetahui), subjek ekonomi (bertindak dalam ruang material), dan subjek sosio-ekologis (hidup dalam relasi dengan sesama dan lingkungan) secara utuh.
Ketika seorang anak belajar matematika, ia tidak hanya mengasah kemampuan kognitif, tetapi juga belajar tentang keadilan distribusi, keteraturan semesta, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan harus dirancang sebagai ekosistem yang memungkinkan siswa melihat keterkaitan antara pengetahuan, tindakan, dan konsekuensi. Pelajaran ekonomi, misalnya, harus membahas bagaimana sistem ekonomi tertentu menciptakan ketimpangan atau keadilan sosial, sementara biologi mengajarkan manusia sebagai bagian dari ekosistem yang lebih besar.
Masalah lain dalam wacana pendidikan kontemporer adalah dominasi konsep “kompetensi” sebagai standar keberhasilan. Kompetensi bertanya, “Apa yang bisa kamu lakukan?” atau “Seberapa produktif kamu di pasar kerja?”, yang mereduksi manusia menjadi fungsi yang dapat diukur. Logika ini menciptakan kecemasan struktural dan menghancurkan solidaritas sosial, membentuk masyarakat individualistik. Panji Dafa Amrtajaya mengusulkan pergeseran fondasi pendidikan dari kompetensi menuju martabat. Martabat bertanya, “Siapa kamu dalam hubungan dengan sesama?” dan “Bagaimana kehadiranmu memperkaya kehidupan bersama?” Martabat adalah nilai intrinsik setiap manusia sejak lahir, bukan karena prestasi. Pendidikan berbasis martabat akan menghasilkan manusia yang berorientasi pada kontribusi, bukan kompetisi.
Metafora “membentuk” atau “mencetak” manusia dalam wacana pembangunan SDM sangat problematis karena mengandaikan manusia sebagai material pasif. Paradigma transkonstruktif mengusulkan metafora organik: manusia sebagai benih. Benih memiliki potensi untuk tumbuh, dan yang dibutuhkan adalah ekosistem kondusif, bukan cetakan eksternal. Pendidikan, dalam metafora ini, adalah ekosistem, bukan pabrik. Ini berarti mengakui keragaman, membiarkan pertumbuhan internal, dan memahami bahwa manusia yang tumbuh sehat akan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Metafora ini sangat resonan dengan filosofi “Tut Wuri Handayani” Ki Hadjar Dewantara, di mana guru mendorong dari belakang, bukan menekan dari atas.
Transformasi Epistemik: Dari Hierarki Kuasa menuju Simbiosis Pengetahuan
Paulo Freire mengkritik banking model of education yang mencerminkan relasi kuasa hierarkis, di mana guru adalah subjek aktif dan siswa objek pasif. Model ini terlihat di Indonesia melalui kurikulum sentralistik, buku teks sebagai satu-satunya sumber sah, dan metode ceramah-hafalan. Akibatnya, lahir generasi yang pandai menghafal tetapi tidak mampu berpikir mandiri atau mengajukan pertanyaan kritis terhadap realitas sosial. Mereka menjadi objek sejarah, bukan subjek yang mampu mengubah dunia.
Kritik ini tidak berarti peran guru tidak penting, melainkan harus didefinisikan ulang sebagai arsitek ekosistem belajar. Guru berfungsi sebagai kurator pengetahuan, fasilitator dialog, dan jembatan antara teks dan konteks, membantu siswa menavigasi informasi, berpendapat tanpa takut, dan membumikan kurikulum nasional dalam realitas lokal.
Musyawarah sebagai Pedagogi Inti
Musyawarah, kearifan politik fundamental Indonesia untuk mencapai mufakat, harus menjadi pedagogi inti. Ini berarti mengubah ruang kelas menjadi arena musyawarah epistemik, tempat berbagai klaim pengetahuan diuji, dipertanyakan, dan disintesiskan. Misalnya, dalam pelajaran sejarah kolonial, siswa diajak mendengar cerita dari kakek-nenek, membaca berbagai sumber, lalu bersama-sama membangun pemahaman yang kompleks. Siswa belajar bahwa sejarah adalah interpretasi yang terus diperdebatkan, bukan fakta hafalan. Pedagogi musyawarah juga mengajarkan keterampilan krusial untuk demokrasi: mendengar dengan empati, berargumentasi rasional, dan tetap bersama meski berbeda pendapat, yang sangat mendesak di era polarisasi politik.
Obsesi terhadap standardisasi dalam sistem pendidikan nasional yang sentralistik justru menciptakan ketidaksetaraan yang lebih dalam. Anak di Papua dengan tradisi oral kuat dipaksa belajar berbasis teks, sementara anak pesisir mempelajari materi urban-industrial. Paradigma transkonstruktif mengusulkan kontekstualitas sebagai standar tertinggi. Pendidikan berkualitas di Papua harus berbeda dari Jakarta karena konteks sosial, budaya, ekonomi, dan ekologisnya berbeda. Yang harus sama adalah komitmen untuk menghasilkan subjek yang mampu memahami dan mengubah konteksnya sendiri. Kontekstualitas juga mengakui dan menghargai pengetahuan lokal yang selama ini terpinggirkan.
Visi Sosio-Ekologis: Pendidikan sebagai Organ Ketahanan Hidup Bangsa
Distorsi besar dalam pendidikan kontemporer terletak pada pemahaman ekonomi yang didominasi ideologi neoliberal, di mana ekonomi adalah arena kompetisi. Pendidikan berbasis paradigma ini hanya akan menghasilkan predator. Pasal 33 UUD 1945 menawarkan visi berbeda: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Ini adalah visi ekonomi komunitarian, kooperatif, dan berbasis solidaritas. Tujuan ekonomi bukan memaksimalkan keuntungan atau pertumbuhan GDP, melainkan memastikan setiap anggota masyarakat hidup bermartabat.
Pendidikan ekonomi yang sejalan dengan visi konstitusional ini harus mengajarkan siswa bertanya: Bagaimana usaha ekonomi saya bisa menghidupi orang lain, bukan mematikan ruang hidup mereka? Ini berarti menggeser fokus dari “mencari kerja” menjadi “menciptakan kerja”, dari “menjadi karyawan” menjadi “menjadi entrepreneur sosial”, dan dari “mengeksploitasi sumber daya” menjadi “mengelola sumber daya secara berkelanjutan”. Sekolah dapat mengembangkan koperasi siswa sebagai unit usaha nyata, di mana siswa belajar pembukuan, manajemen, pemasaran, serta prinsip demokrasi ekonomi.
Frasa “seluruh tumpah darah Indonesia” dalam Pembukaan UUD 1945 sering dibaca sempit sebagai kedaulatan teritorial militer. Dalam visi sosio-ekologis, ini harus direkonstruksi sebagai kedaulatan ruang hidup. Manusia hidup dalam ketergantungan mutlak pada ekosistem terbatas. Pendidikan transkonstruktif harus mengintegrasikan ekologi sebagai struktur berpikir (epistemik ekologis), melatih siswa memahami interconnectedness antara tindakan ekonomi dan dampak ekologisnya. Kesadaran ini menggeser posisi manusia dari “penakluk alam” menjadi “penjaga ruang hidup”. Tanpa kemampuan membaca batas daya dukung lingkungan, kecerdasan bangsa akan jatuh menjadi kecerdasan destruktif.
Di masa ketika teknologi digital dan kecerdasan buatan mengancam menggantikan peran manusia, pendidikan yang berorientasi pada keahlian teknis rutin akan memproduksi pengangguran masa depan. Kapasitas manusia yang tidak bisa digantikan algoritma adalah refleksi etis, penilaian nilai, dan kemampuan berdialog di tengah konflik kepentingan. Pendidikan harus bertransformasi menjadi organ ketahanan bangsa yang melatih fleksibilitas adaptif. Subjek yang belajar cara belajar (learning to learn) tidak akan takut pada perubahan teknologi karena ia didefinisikan oleh kemampuannya untuk terus mengalibrasi diri dengan tantangan baru. Ketahanan bangsa dalam visi ini bukanlah ketahanan yang menutup diri, melainkan yang berakar kuat pada identitas dan kebutuhan lokal, namun mampu berinteraksi kritis dengan standar global.
Kalibrasi Masa Depan
Rekonstruksi pendidikan Indonesia harus dimulai dengan mengembalikan martabat manusia sebagai subjek yang utuh—sosio-ekologis, ekonomi, dan epistemik. Kita harus berani mengakui bahwa sistem yang berorientasi semata-mata pada “pasar kerja” telah gagal melindungi tumpah darah dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam arti hakiki. Pedagogi Musyawarah menawarkan jalan keluar dengan meruntuhkan hierarki kuasa yang asimetris dan menggantinya dengan relasi belajar yang dialogis. Di ruang-ruang musyawarah itulah, konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian ekologis dapat dibahas secara dewasa.
Pendidikan bukan lagi peristiwa eksklusif di dalam kelas yang memisahkan anak dari dunianya, melainkan sebagai denyut nadi kehidupan masyarakat yang terus belajar. Penerapan gagasan ini menuntut keberanian dari semua elemen: pemerintah untuk mendesentralisasi otoritas epistemik; guru untuk menjadi arsitek ekosistem daripada sekadar instruktur; dan masyarakat untuk kembali memfungsikan rumah serta komunitas sebagai pusat pendidikan. Akhirnya, pendidikan sejati adalah yang mampu menjawab tantangan dasar eksistensi kita sebagai bangsa merdeka: “Bagaimana kita dapat tetap ada tanpa meniadakan yang lain?” Jika setiap sekolah, keluarga, dan komunitas menjadi ruang latihan bagi pertanyaan ini, cita-cita luhur Pembukaan UUD 1945 akan menjadi realitas hidup yang kita hirup setiap hari.