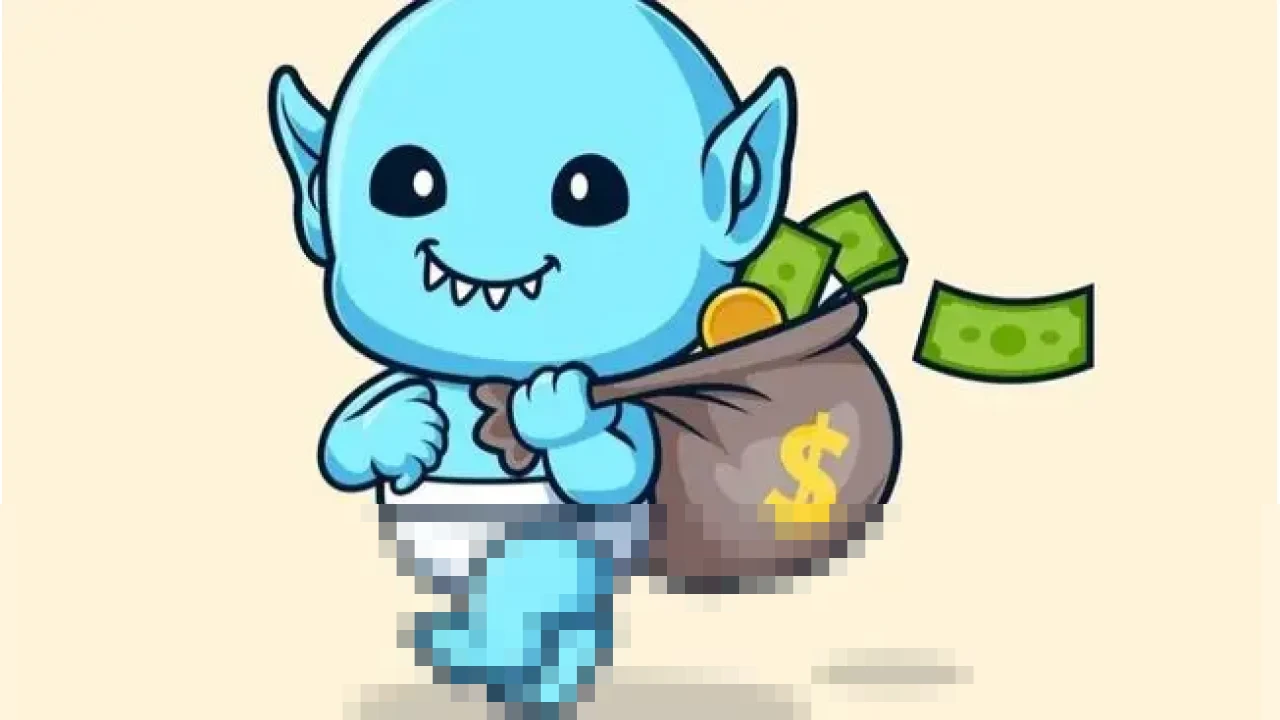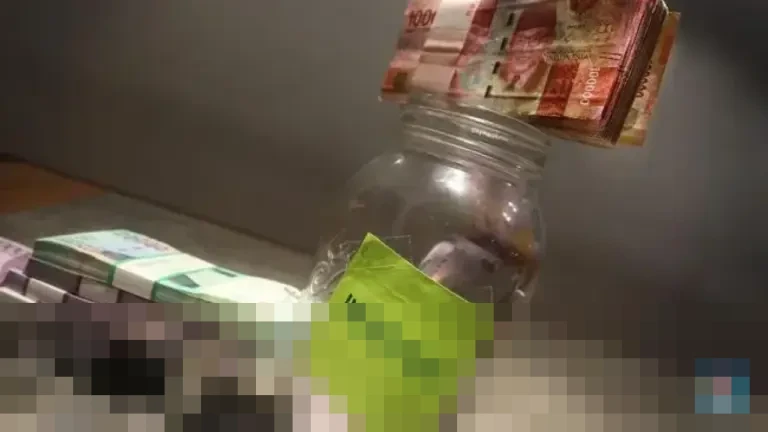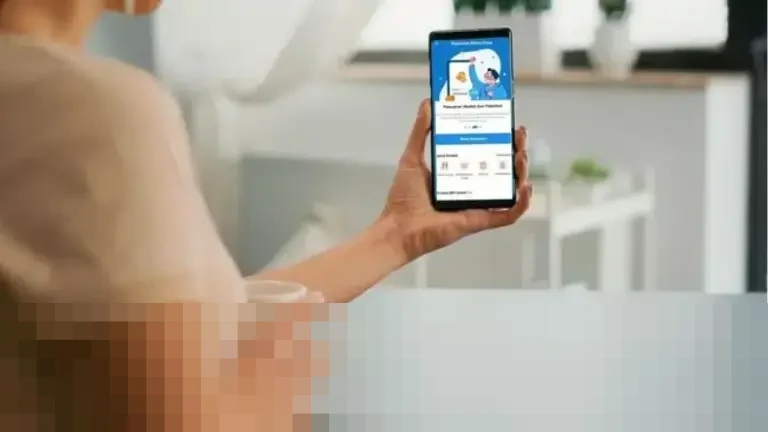Sosok tuyul telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari cerita rakyat Indonesia, dipercaya sebagai makhluk halus berwujud anak kecil yang dipelihara untuk mencuri uang. Konon, tuyul beraksi dari rumah ke rumah, menguras harta demi memperkaya majikannya, bahkan disebut-sebut mampu mengambil barang atau surat berharga lainnya.
Namun, di tengah kepercayaan yang mengakar kuat itu, muncul pertanyaan klasik yang tak pernah terjawab secara mistis: mengapa tuyul tidak pernah mencuri uang di bank atau menguras saldo e-money yang nilainya jauh lebih besar? Hingga kini, tak ada satu pun kasus bank kehilangan dana yang dikaitkan dengan ulah makhluk mistis tersebut.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Jawaban populer yang beredar di masyarakat seringkali bernuansa mistik, mulai dari anggapan tuyul takut logam, brankas, hingga kalah oleh “penjaga gaib” yang konon melindungi bank. Namun, di balik narasi mistis tersebut, tersimpan penjelasan rasional yang justru membongkar asal-usul mitos tuyul itu sendiri.
Akar Mitos Tuyul: Ketimpangan Ekonomi Era Kolonial
Untuk memahami fenomena ini, kita perlu menelusuri kembali ke akhir abad ke-19, tepatnya setelah tahun 1870. Kala itu, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan liberalisasi ekonomi atau yang dikenal sebagai politik pintu terbuka, menggantikan sistem tanam paksa yang telah berlangsung lama.
Kebijakan ini, seperti dijelaskan oleh Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks dalam buku Ekonomi Indonesia 1800-2010, melahirkan rezim kolonial baru. Lahan-lahan perkebunan rakyat diambil alih secara masif dan diubah menjadi perkebunan besar serta pabrik gula. Akibatnya, banyak petani kecil di Jawa kehilangan tanah mereka dan terjerumus semakin dalam ke jurang kemiskinan.
Di saat yang bersamaan, muncul kelompok pedagang, baik pribumi maupun Tionghoa, yang mendadak kaya raya. Kekayaan mereka tumbuh pesat seiring terbukanya arus perdagangan dan berkembangnya ekonomi uang. Fenomena ini menimbulkan keheranan di kalangan petani yang hidup dalam sistem agraris dan terbiasa bertani sekadar untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
Sejarawan Ong Hok Ham menjelaskan, masyarakat agraris kala itu memiliki pandangan bahwa kekayaan haruslah tampak prosesnya. Jika seseorang menjadi kaya, orang lain harus bisa melihat dengan jelas kerja keras atau sumber kekayaan tersebut. Masalahnya, para petani tidak melihat proses itu pada para pedagang kaya baru.
Kebingungan tersebut kemudian berubah menjadi kecemburuan sosial. George Quinn mencatat bahwa dalam pandangan masyarakat Jawa, kekayaan juga harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Ketika asal-usul harta tak bisa dijelaskan secara transparan, muncullah tuduhan bahwa kekayaan itu berasal dari pencurian atau cara-cara gelap.
Dalam masyarakat yang kental dengan mistisisme, tuduhan itu berkembang menjadi keyakinan bahwa orang kaya bersekutu dengan makhluk halus, salah satunya tuyul. Sosok tuyul pun akhirnya menjadi simbol penjelas atas ketimpangan ekonomi yang sulit dipahami oleh masyarakat kecil.
Akibatnya, para pedagang dan pengusaha sukses kerap kehilangan legitimasi sosial. Mereka dicap hina karena dianggap memperoleh kekayaan melalui cara-cara yang tidak halal. Ong Hok Ham bahkan mencatat, stigma ini memengaruhi perilaku orang kaya yang cenderung menyembunyikan harta mereka agar tidak dituduh memelihara setan.
Dari sinilah mitos tuyul menguat dan diwariskan secara turun-temurun lintas generasi. Cerita tuyul, pada dasarnya, bukanlah bukti keberadaan makhluk gaib pencuri uang, melainkan sebuah refleksi sosial atas ketimpangan ekonomi yang timbul akibat perubahan struktur kolonial. Inilah alasan sebenarnya mengapa tuyul hanya “mencuri” dari rumah ke rumah dalam cerita rakyat, dan tak pernah muncul di bank atau sistem keuangan modern.