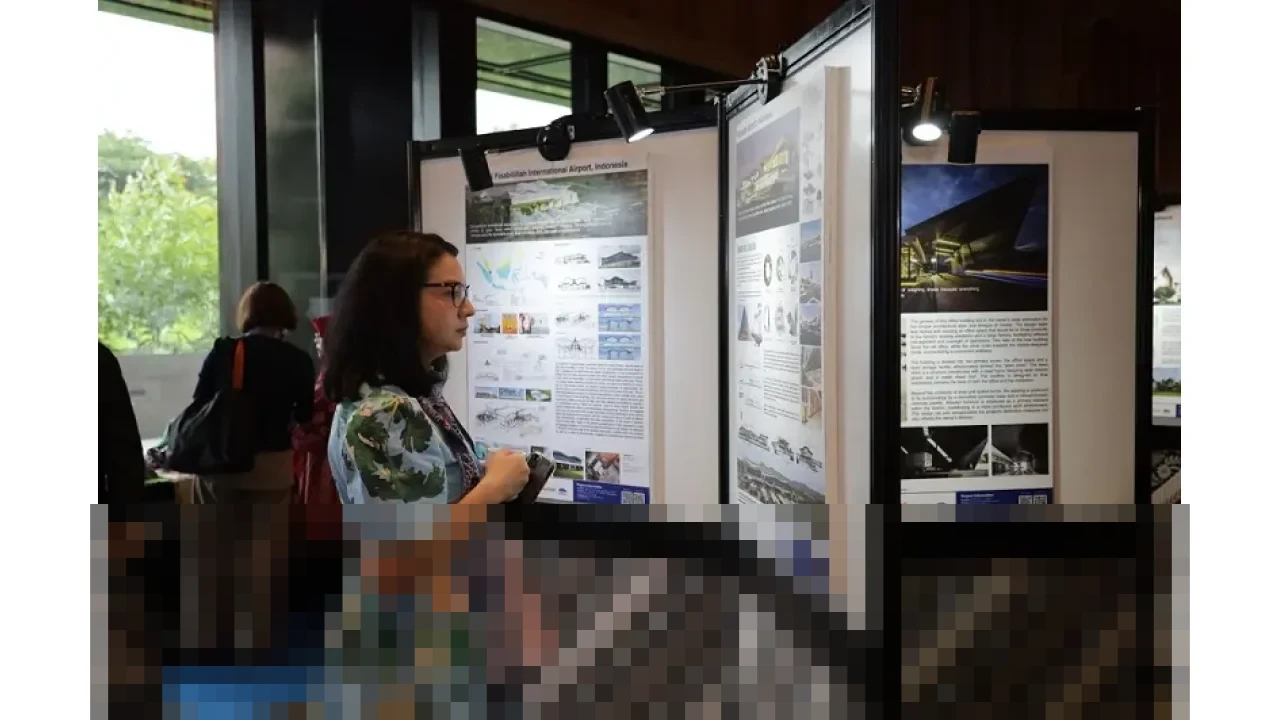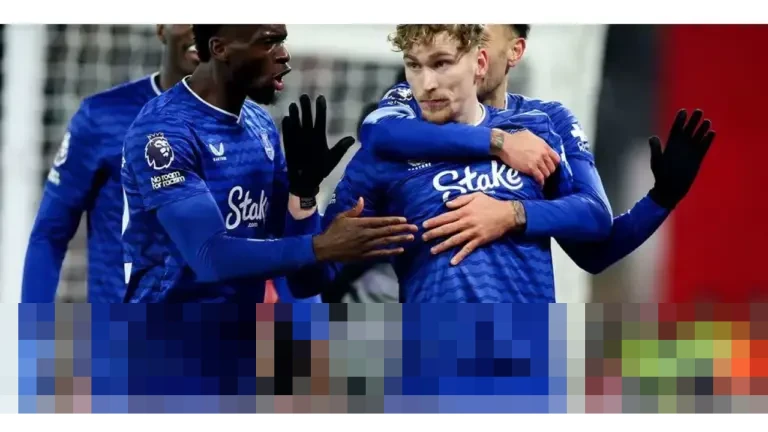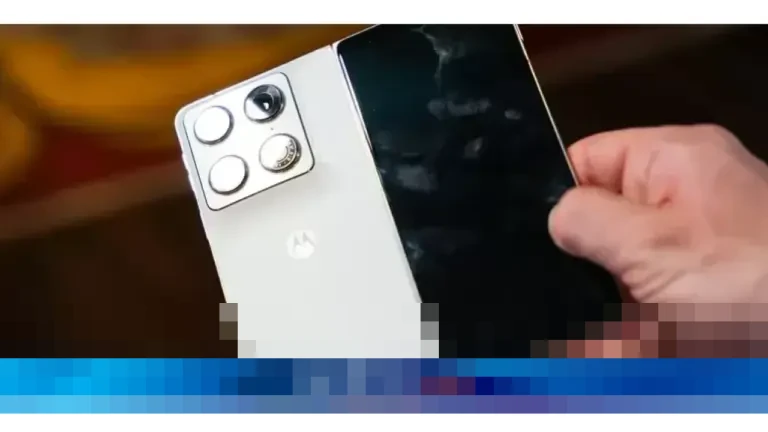Di tengah laju pembangunan infrastruktur Asia Tenggara yang kian masif demi mengejar pertumbuhan ekonomi, muncul sebuah pertanyaan fundamental: bagaimana membangun tanpa merusak? Bagaimana arsitektur modern dapat tetap menghormati identitas lokal sekaligus tangguh menghadapi krisis iklim?
Jawabannya mungkin terletak pada filosofi sederhana: “Touch this earth lightly,” atau sentuhlah bumi ini dengan lembut. Prinsip ini diperkenalkan oleh Glenn Murcutt, satu-satunya arsitek asal Australia peraih Pritzker Architecture Prize, penghargaan tertinggi di dunia arsitektur. Filosofi tersebut kini menjadi kompas bagi pergerakan arsitektur berkelanjutan di kawasan ASEAN. Murcutt menegaskan bahwa bangunan yang baik bukanlah yang mendominasi alam, melainkan yang beradaptasi dengannya, menghormati budaya lokal, serta meninggalkan jejak karbon seminimal mungkin.
Mureks juga menyajikan berbagai artikel informatif terkait. mureks.co.id
Dilema Pembangunan ASEAN: Antara Ambisi dan Keberlanjutan
Asia Tenggara saat ini berada di persimpangan kritis. Di satu sisi, kawasan ini mengalami urbanisasi tercepat di dunia, dengan proyeksi ratusan juta penduduk tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2030. Di sisi lain, wilayah ini juga termasuk yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, mulai dari kenaikan permukaan laut hingga gelombang panas ekstrem.
Kondisi tersebut menuntut pendekatan arsitektur yang tak lagi bisa bergantung pada pola lama build–demolish–rebuild. Diperlukan material dan desain yang tidak hanya estetis, tetapi juga adaptif, tahan lama, dan ramah lingkungan. Dalam konteks inilah evolusi teknologi material, termasuk baja modern, mulai memainkan peran penting.
Menggali Makna “Sentuhan Lembut” dari Sang Maestro
Filosofi “Touch this earth lightly” bukan sekadar wacana normatif. Prinsip ini menjadi salah satu topik utama dalam simposium arsitektur ASEAN yang digelar di Jakarta pada akhir November lalu. Dalam forum tersebut, Ar. Nick Sissons dari Glenn Murcutt Architecture Foundation Australia membedah bagaimana filosofi ini dapat diterjemahkan secara kontekstual di Asia Tenggara yang kaya akan keragaman budaya.
Simposium bertajuk “Shaping Resilient Futures: Heritage and Modernity in Steel Architectural Design” ini berhasil mengumpulkan sekitar 190 pakar arsitektur dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Australia. Mureks mencatat bahwa mereka berkumpul dengan satu misi: merumuskan masa depan arsitektur kawasan yang tidak sekadar mengikuti tren global, tetapi juga berakar kuat pada kearifan lokal.
Ar. Budi Pradono, arsitek senior Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara. “Kemitraan ini menegaskan vitalitas aliansi regional kita dan akan memotivasi komunitas arsitek ASEAN menuju pencapaian yang lebih berani dan berdampak,” ujarnya melalui siaran pers pada Senin (5/1).
Sementara itu, Ar. Steve Woodland dari COX Architecture Australia, yang menjadi keynote speaker, membahas bagaimana teknologi material modern termasuk baja berlapis dapat menjawab tantangan arsitektur masa depan yang kian kompleks.
Baja: Medium Harmoni, Bukan Sekadar Simbol Modernitas
Salah satu gagasan menarik dari forum tersebut adalah pergeseran paradigma dalam memandang material baja. Baja tidak lagi diposisikan semata sebagai simbol modernitas yang monoton dan impersonal, melainkan sebagai medium untuk mencapai tujuan yang lebih besar: menciptakan harmoni antara manusia dan alam.
Jenny Margiano, Country President PT NS BlueScope Indonesia, menjelaskan bahwa baja modern memiliki karakteristik yang sejalan dengan kebutuhan arsitektur berkelanjutan. “Material ini dapat didaur ulang, fleksibel untuk berbagai desain, dan tangguh menghadapi kondisi iklim ekstrem. Kualitas tersebut sangat dibutuhkan ASEAN saat ini,” ujarnya.